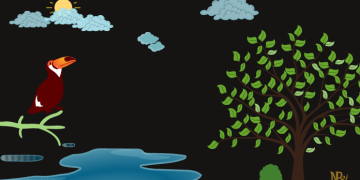Mubadalah.id – Banjir bandang yang menerjang Aceh Barat dan Sumatera Barat bukan sekadar bencana alam biasa yang mengakibatkan kerusakan ekologi. Derasnya air yang menyapu permukiman membawa kita pada sebuah kesadaran, tentang sejauh mana tanggung jawab kolektif kita dalam pelestarian lingkungan?
Pertanyaan ini menjadi pintu masuk kajian Tadarus Subuh ke-173 pada 8 Desember 2025. Membawa tema “Kerusakan Ekologi dan Tanggung Jawab Agama”, diskusi ini menghadirkan tiga perspektif penting: Umi Hanisah Abdullah, pengasuh Dayah Diniyah Darussalam yang menjadi penyintas banjir. Uli Arta Siagian, Eksekutif Nasional WALHI; dan Dr. Faqihuddin Abdul Kodir, Founder Mubadalah.id.
Gerakan Ekologi Islam di Aceh: Dari Fatwa hingga Energi Bersih
Umi Hanisah membuka diskusi dengan realitas pahit di Aceh Barat. Di sana, pertambangan, perambahan hutan, penebangan pohon, hingga konversi hutan menjadi lahan pohon sawit adalah pemandangan yang membuat masyarakat Aceh gigit jari.
Pasalnya, tambang yang dijanjikan membawa kesejahteraan justru melahirkan kemiskinan, hutan yang dirambah terus menipis. Para pengelola tambang ini, juga banyak menyerap para pekerja asing dan meletakkanya di posisi-posisi strategis, sementara masyarakat sekitar hanya kebagian sebagai pekerjaan kasar
Data yang penulis dapat dari situs Mongabay menyebut, bahwa luas tutupan hutan di Provinsi Aceh berkurang setiap tahunnya. Jika kita hitung dari tahun 2020-2024, tutupan hutan yang hilang mencapai 2.181 hektar. Menurut Lukmanul Hakim, Manager Geographic Information System (GIS) Yayasan HAkA, “tutupan hutan berkurang akibat perambahan, pembalakan liar, pertambangan, hingga konversi menjadi kebun.”
Di tengah berbagai ancaman deforestasi dan pencemaran lingkungan, lahir para Tengku Inong, sebutan ulama perempuan di Aceh, yang vokal menyuarakan kampanye ekologis berbasis Islam. Mereka adalah garda terdepan yang memiliki peran penting untuk menyampaikan dakwah-dakwah ekologi ke masyarakat.
Gerakan ini juga tidak hanya berhenti di tataran normatif. Tengku Inong mengembangkan modul ekologi, kurikulum berbasis lingkungan, hingga sekolah energi bersih yang diterapkan dalam dayah-dayah dan pesantren yang mereka asuh. Umi Hanisah memaparkan,
Kini, 70 pesantren telah menggunakan listrik tenaga surya, dan panas bumi. Ke depan, program sekolah energi bersih yang mereka canangkan, harapannya menjadi program yang terus berkembang, menyasar seluruh institusi pendidikan di tanah air. Langkah ini penting, terutama bagi pesantren yang minim dana untuk membayar biaya tagihan PLN.
Kebijakan Politik yang Gagal Mitigasi Bencana
Diskusi pun berlanjut pada, Uli Arta Siagian yang membawa perspektif lebih tajam. Ia menyatakan bahwa bencana ekologis adalah konsekuensi langsung dari hilangnya ekosistem penting seperti hutan, dan diperparah oleh krisis iklim. Aktivis lingkungan WALHI ini memberikan analisis tajam mengenai fenomena siklon yang ditengarai menjadi penyebab utama banjir bandang di Aceh dan Sumatra Barat.
Seharusnya, siklon tidak dapat berkembang besar di wilayah garis khatulistiwa. Namun, suhu permukaan laut yang terus meningkat memberikan energi bagi siklon untuk berkembang dan memutar ke daratan. Dan ketika curah hujan tinggi menghantam infrastruktur ekologis sudah tidak mampu menahan laju air.
Hutan yang semestinya menjadi tulang punggung pulau Sumatra, terlalu ringkih untuk menahan curah hujan tinggi, penyebabnya deforestasi masif demi kepentingan pertambangan dan konversi lahan sawit.
Di samping itu, Uli juga menegaskan, bencana ekologis tidak bisa terlepaskan dari kebijakan politik. Setiap rezim harus kita mintai pertanggungjawaban atas perizinan tambang dan lahan sawit yang mereka berikan tanpa mengindahkan basis data para ahli.
Padahal, konstitusi sudah menjamin kesejahteraan rakyat dan lingkungan, sebagaimana pernyataan dalam pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. Tapi realitanya, penerapan oleh pemerintah jauh panggang dari api.
Uli mendesak dua langkah yang harus dilakukan pemerintah: pertama, evaluasi seluruh perizinan tambang dan sawit di wilayah ekosistem rentan. Kedua, menagih pertanggungjawaban korporasi. Ada fakta memilukan yang ia tampilkan, reklamasi yang harusnya menjadi tanggung jawab perusahaan justru dibayar kas negara.
Riset WALHI mencatat negara harus mengeluarkan 1,01 triliun rupiah per tahun untuk menanggung kerusakan yang mereka sisakan. Pada titik ini rakyat menjadi korban ganda, tidak dapat kucuran kekayaan alamnya, dan harus bertanggung jawab memperbaiki kerusakan yang ditinggalkan oleh para pengelola tambang.
Uli juga mengkritik standar ganda pemerintah: saat bencana, sangat administratif; tapi pada penjahat lingkungan, penegakan hukum nihil. BNPB punya peta rawan bencana, tapi tidak pernah jadi basis utama dalam keputusan tata ruang. Undang-undang malah dipermudah agar izin cepat keluar. Seolah, negara hanya hadir bagi korporat dan menaganaktirikan anak bangsanya sendiri.
Agama sebagai Kontrol Daya Rusak Manusia
Kang Faqih menutup dengan refleksi teologis yang menohok. Permasalahan lingkungan yang terjadi dewasa ini, problemnya terletak pada diri manusia itu sendiri. Al-Qur’an sudah melabeli manusia sebagai dzaluman jahula—makhluk yang cenderung zalim dan bodoh.
Saat manusia pertama diciptakan, Malaikat pun mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang suka menumpahkan darah dan merusak lingkungan. Dengan demikian, karakter perusak ada pada siapa pun, melekat sebagai naluri asli manusia. Sifat perusak ini pun akan memiliki daya rusak yang berlipat ganda saat berada di tangan pemilik kuasa besar.
Di sinilah fungsi agama, sebagai alat untuk mengontrol. Kalau agama diam, pemerintah akan tidur nyenyak. Para ulama’, ormas kegamaan, dan para pendakwah di seluruh Indonesia harus menjadi kepanjangan tangan agama dalam fungsinya sebagai pemberi pesan, pengingat, dan pengawas. Kesadaran akan sifat destruktif pada diri sendiri harus kita tanamkan.
Destruksi Manusia
Lingkungan adalah ayat Tuhan yang menunjukkan bagaimana hidup secara benar, baik, dan maslahat—seperti pesan Surah Yasin ayat 33-35.
﴿وَءَايَة لَّهُمُ ٱلۡأَرۡضُ ٱلۡمَيۡتَةُ أَحۡيَيۡنَٰهَا وَأَخۡرَجۡنَا مِنۡهَا حَبّا فَمِنۡهُ يَأۡكُلُونَ وَجَعَلۡنَا فِيهَا جَنَّٰت مِّن نَّخِيل وَأَعۡنَٰب وَفَجَّرۡنَا فِيهَا مِنَ ٱلۡعُيُونِ لِيَأۡكُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦ وَمَا عَمِلَتۡهُ أَيۡدِيهِمۡۚ أَفَلَا يَشۡكُرُونَ 33-٣٥﴾
Artinya “Dan suatu tanda (kebesaran Allah) bagi mereka adalah bumi yang mati (tandus). Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan darinya biji-bijian, maka dari (biji-bijian) itu mereka makan Dan Kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air agar mereka dapat makan dari buahnya, dan dari hasil usaha tangan mereka. Maka mengapa mereka tidak bersyukur?”
Kang Faqih menegaskan: “Kita semua tidak beragama ketika tidak mengontrol destruksi manusia.”
Ini menjadi tamparan bagi kita, untuk tetap saling mengingatkan, mengontrol dan mengawasi sifat destruktif yang ada pada diri kita. Publik sebagai ruang kebersamaan harus menjadi ruang kontrol dan pengawasan, baik sesama individu maupun terhadap kebijakan negara. Karena ekologi bukan hanya soal kebesaran Tuhan, tapi juga panduan hidup yang maslahat. []