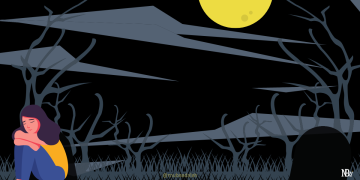Mubadalah.id – Dalam Seminar Nasional Keulamaan Perempuan untuk Pemenuhan Hak-hak Disabilitas di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Selasa 21 Oktober 2025, saya memperkenalkan satu terminologi baru dari rahim KUPI: Fiqh al-Murūnah. Sebuah paradigma fiqh yang lentur, inklusif, dan berkeadilan, yang tumbuh dari pengalaman dan cara pandang penyandang disabilitas sendiri.
Konsep ini hadir sebagai kelanjutan dan penguatan dari inisiatif mulia yang telah digagas para ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam pengembangan Fiqh Disabilitas. Kedua ormas besar Islam ini telah membuka jalan dengan menempatkan isu disabilitas dalam kerangka keislaman yang penuh kasih (rahmah) dan kemanusiaan.
KUPI mengambil semangat dan prinsip-prinsip dasar dari inisiatif tersebut. Yakni penghormatan terhadap martabat manusia dan tanggung jawab sosial umat Islam. Namun melangkah lebih fundamental dan mengusulkan istilah baru yang lebih tepat, yaitu “Fiqh al-Murūnah”.
Fiqh al-Murūnah mengusulkan pergeseran mendasar dari paradigma “keringanan” (rukhsah) dan “kemudahan” (taysīr) yang selama ini terumuskan dari perspektif para non-difabel, menuju paradigma pengakuan terhadap pengalaman difabel sebagai sumber otoritatif fiqh itu sendiri.
Pergeseran ini bukan sekadar perubahan istilah, tetapi perubahan epistemologis. Yaitu dari cara pandang yang melihat difabel sebagai penerima keringanan, menuju pengakuan bahwa mereka adalah penghasil pengetahuan hukum Islam yang sah.
Penyandang Disabilitas adalah Manusia Utuh
Paradigma ini berangkat dari keyakinan bahwa penyandang disabilitas adalah manusia utuh—dengan akal, jiwa, dan fisik. Selain itu subjek penuh (fā‘il kāmil) yang memiliki kapasitas dan otoritas untuk berijtihad dari pengalaman hidupnya sendiri. Dengan demikian, pengalaman mereka tidak lagi terposisikan sebagai kasus khusus yang kita carikan keringanan, melainkan sebagai sumber nilai dan pemahaman yang memperkaya khazanah fiqh Islam.
Arah pergeseran ini sejatinya telah tampak dalam karya-karya Dr. Rof’ah dari Muhammadiyah dan Dr. Arif Maftuhin dari Nahdlatul Ulama. Melalui riset dan pemikiran mereka telah menegaskan pentingnya melihat disabilitas dari perspektif kemanusiaan yang utuh dan berkeadilan.
Saya banyak memetik inspirasi dari keduanya, juga dari buku-buku Fiqh Disabilitas terbitan NU dan Muhammadiyah. Dari sana, saya mencoba merumuskan gagasan ini dalam satu kerangka yang kita harapkan lebih mudah teringat dan kita praktikkan. Terutama untuk kerja-kerja advokasi pemenuhan hak-hak disabilitas melalui cara pandang fiqh yang lentur, partisipatif, dan memberdayakan.
Dalam kerangka paradigmatik ini, azīmah (hukum asal) dan rukhsah (diskon atau keringanan hukum) tidak boleh terukur dari pengalaman mereka yang non-difabel, melainkan harus berpijak pada realitas dan pengalaman penyandang disabilitas sendiri.
Fiqh Islam, pada dasarnya, memang bersifat lentur dan adaptif (murūn). Sebagaimana kaidah taghayyur al-aḥkām bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah — hukum berubah mengikuti perubahan waktu dan tempat. KUPI memperluas prinsip ini dengan menambahkan satu dimensi penting. Wal-aḥwāl al-badaniyyah, bahwa hukum juga perlu menyesuaikan dengan keberagaman kondisi tubuh manusia.
Kerangka yang saya maksud terdiri dari empat prinsip kunci yang menjadi fondasi Fiqh al-Murūnah:
Pertama, level Manhajī (Epistemologis-Metodologis)
Fiqh perlu kita rekonstruksi sejak dari cara pandangnya. Ia harus berangkat dari pengakuan bahwa penyandang disabilitas adalah manusia utuh dan subjek penuh yang memiliki kapasitas spiritual dan intelektual untuk memahami, menafsirkan. Bahkan merumuskan hukum dari pengalaman mereka sendiri.
Dengan demikian, pengalaman hidup difabel bukan lagi sekadar bahan ilustrasi atau kasus pinggiran (furū‘), tetapi sumber pengetahuan yang memiliki legitimasi teologis. Pengakuan terhadap pengalaman ini adalah langkah penting dalam membangun epistemologi fiqh yang lebih setara dan inklusif. Selain itu, menegaskan bahwa otoritas keagamaan tidak pernah bersifat tunggal atau eksklusif.
Kedua, level Murūnah (Fleksibilitas Fiqh)
Fiqh harus lentur dan adaptif terhadap keragaman kondisi dan pengalaman tubuh manusia. Prinsip fleksibilitas ini mencakup bidang ṭahārah, ‘ibādah, dan mu‘āmalah, dengan membuka ruang negosiasi yang adil antara pengalaman difabel dan non-difabel. Dalam konteks ini, Fiqh al-Murūnah bukan berarti “mempermudah” semata, tetapi menata ulang ukuran keadilan dan kesetaraan sesuai realitas setiap individu.
Fiqh yang hidup harus mampu merespons keterbatasan fisik tanpa meniadakan martabat, serta memfasilitasi pengamalan agama sebagai wujud takwa yang kontekstual dan manusiawi.
Ketiga, level Takyīf (Adaptasi Teknologi)
Fiqh yang lentur harus kita sertai upaya nyata untuk menghadirkan sarana dan teknologi yang memungkinkan penyandang disabilitas berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial dan keagamaan. Alat bantu dan teknologi tersebut harus kita pandang bukan sekadar instrumen eksternal, melainkan bagian integral dari diri mereka.
Kursi roda, misalnya, bagi penyandang daksa bukan sekadar alat bantu, tetapi perpanjangan dari tubuh—bagian dari eksistensi jasmani yang harus kita hormati sebagaimana kaki bagi orang non-difabel. Cara pandang seperti ini akan mengubah banyak aspek fiqh, termasuk thaharah, posisi tubuh dalam salat, dan batasan interaksi ritual, yang semuanya perlu kita tinjau ulang agar benar-benar menghargai keberadaan tubuh difabel secara utuh.
Keempat, level Tamkīn (Aksesibilitas untuk Pemberdayaan)
Fiqh tidak berhenti pada tataran individu, tetapi harus mendorong transformasi sosial dan kebijakan publik yang menjamin aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Negara, masyarakat, dan lembaga keagamaan memiliki tanggung jawab moral dan syar‘i untuk memastikan sistem sosial yang enabling, bukan disabling.
Upaya ini—dalam pandangan Fiqh al-Murūnah—merupakan bentuk ijtihād dan jihād Islami yang sesungguhnya, karena menegakkan keadilan struktural dan kemaslahatan universal.
Dengan empat level ini, Fiqh al-Murūnah berupaya menyambung estafet pemikiran keislaman yang telah dirintis oleh para ulama terdahulu. Sekaligus menegaskan satu arah baru: fiqh yang partisipatif, berbasis pengalaman, dan berorientasi pada keadilan sosial. Ia tidak hanya menyesuaikan hukum dengan kebutuhan penyandang disabilitas, tetapi juga menempatkan pengalaman mereka sebagai sumber sah bagi perumusan hukum Islam.
Namun, pertanyaan kritis tetap terbuka:
Apakah Fiqh al-Murūnah sudah cukup menjawab seluruh kebutuhan dan kompleksitas persoalan disabilitas di tengah masyarakat Muslim? Ataukah justru kita perlukan tahap lanjutan, di mana penyandang disabilitas sendiri menjadi penulis utama fiqh tentang diri sendiri. Bukan sekadar narasumber bagi fiqh yang tertulis oleh orang lain?
Pertanyaan-pertanyaan ini bukan akhir dari diskusi, melainkan awal dari ijtihad kolektif berikutnya. Ijtihad yang tidak hanya mencari kemudahan, tetapi juga memperjuangkan pengakuan, kesetaraan, dan kemanusiaan yang seutuhnya. []