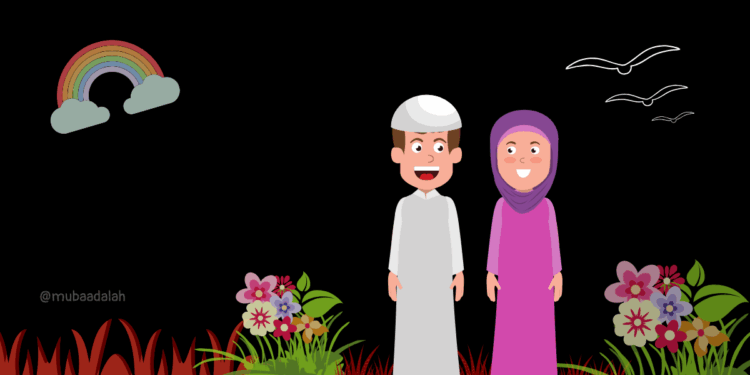Mubadalah.id – Dalam hal perkawinan, fikih harus menegaskan bahwa lembaga perkawinan dalam Islam bukanlah lembaga perbudakan yang meleburkan jati diri seseorang ke dalam jati diri pasangannya.
Karena setiap pasangan tetap memiliki hak kemandiriannya untuk menjadi diri sendiri. Kemandirian ini dipertemukan antara dua diri untuk menjadi kekuatan yang utuh dalam menghadapi tantangan hidup.
Dalam bahasa al-Qur’an, istri adalah pakaian bagi suami dan suami adalah pakaian bagi sang istri (QS. Al-Baqarah, 2:187).
Untuk menjamin kemandirian dan kebersamaan ini, ada beberapa prinsip yang harus keduanya jadikan dasar. Yaitu seperti yang tertulis dalam beberapa ayat al-Qur’an: prinsip-prinsip pertama, kerelaan kedua belah pihak dalam kontrak perkawinan (taradlin) (QS. Al-Baqarah, 2:232–233).
Kedua, tanggung jawab (al-Amanah) (QS. An-Nisa, 4:48). Ketiga, independensi ekonomi dan politik masing-masing (QS. Al-Baqarah, 2:229 dan An-Nisa, 4:20). Keempat, kebersamaan dalam membangun kehidupan yang tenteram (as-sakinah) dan penuh cinta kasih (al-mawaddah wa ar-rahmah) (QS. Ar-Rum, 30:21).
Kelima, perlakuan yang baik antar sesama (mu’asyarah bil ma’ruf) (QS. An-Nisa, 4:19). Kemudian keenam, berembug untuk menyelesaikan persoalan (musyawarah) (QS. Al-Baqarah, 2:233; Ali ‘Imran, 3:159; dan Asy-Syura, 42:38).
Dengan prinsip-prinsip ini, perempuan seharusnya memperoleh jaminan untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif. Apalagi menjadi objek kekerasan dalam relasi perkawinan.
Perempuan Boleh Memilih dan Menentukan
Pada persoalan pilihan pasangan misalnya, perempuan harus diberi kesempatan untuk memilih dan menetukan. Ketika dipaksa menikah, pernikahannya harus dibatalkan atau ia diberi kesempatan untuk menentukan, meneruskan atau membatalkan pernikahan tersebut.
Dengan pemahaman ini, kawin paksa atau perjodohan, seharusnya dihentikan. Kalau kita mau mengambil pelajaran dari dialog yang terjadi antara seorang anak perempuan, ayahnya dan Nabi Muhammad SAW, semestinya praktik kawin paksa terhadap perempuan tidak terjadi dalam masyarakat yang mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad Saw.
Bahkan seribu empat ratus tahun yang lalu, seorang perempuan mengemukakan pernyataan yang sangat lantang di hadapan Nabi SAW dan para sahabat: “Aku lebih berhak tentang perkawinannya daripada ayahku”.
Kisahnya, seperti yang dituturkan Aisyah ra, bahwa ada seorang remaja perempuan yang datang menemuinya seraya berkata:
“Ayahku mengawinkanku dengan anak saudaranya, agar status sosialnya terangkat olehku, padahal aku tidak suka”. “Duduklah, sebentar lagi Rasulullah datang, nanti aku tanyakan”, jawab Aisyah.
Ketika Rasulullah SAW datang, beliau mengungkapkan persoalan perempuan tadi. Beliau memanggil orang tua si perempuan (sambil memberi peringatan), dan mengembalikan persoalan itu kepada si perempuan untuk memberikan keputusan.
Di hadapan mereka, remaja perempuan tadi menyatakan (dengan tegas): “Aku izinkan apa yang telah dilakukan ayahku, tetapi aku ingin memberikan peringatan sekaligus pernyataan untuk semua perempuan: bahwa mereka para orang tua sama sekali tidak memiliki hak atas persoalan (pernikahan) ini”. (Riwayat an-Nasa’i, lihat Jami’ al-Ushul, no. hadis: 8974, juz XII, hal. 142).
Sumber: Buku Pertautan Teks dan Konteks dalam Muamalah karya Dr. Faqihuddin Abdul Kodir.