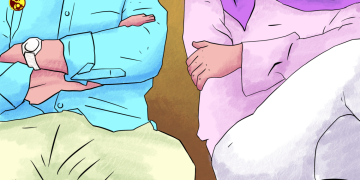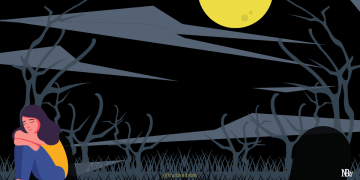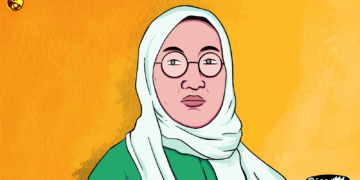Mubadalah.id – Terpatri di kepala, tatkala masih duduk di bangku sekolah dasar, di akhir Januari 2008, penyiar-penyiar di televisi getol mengabarkan berita perkabungan. Rupanya siaran mengenai wafatnya Soeharto (Presiden Ke-2 RI).
Saya ingat betul tayangan berita itu menggeser rating sinetron yang tengah hits kala itu, Namaku Mentari. Tak heran, memang beberapa stasiun televisi (zaman itu) dimiliki anak-anak mendiang Soeharto. Pantas saja bila polesan berita melulu sepak terjang mendiang yang bagus-bagus. Usaha menggoreng citra apik seorang bapak lewat berita berhasil anak-anaknya tandaskan.
Dalam pada itu, mendengar gemuruh usulan pelbagai nama terajukan—salah satunya Soeharto—sebagai pahlawan nasional awal November kemarin, saya merapat ke dalam barisan geram. Maksudnya memihak pada golongan yang menganggap bahwa Soeharto tidak “layak” mendapat gelar terhormat itu. Tentu bukan karena persoalan personal, ini bertaut akan perbalahan kelakuan Soeharto selama menahkodai rezim Orde Barunya.
Semasa mendiang berkuasa, pelbagai kebijakannya (teranggap) menyalahgunakan kekuasaan (abuse of power), melawan hukum, dan membelokkan kebijakan publik bagi keuntungan diri atau kelompoknya. Demikian bisa terinci, di antaranya: Tragedi 1965, Peristiwa Malari (1974), Operasi Petrus (1983), Peristiwa Talangsari (1989), Tragedi Tanjung Priok (1984), Peristiwa Kudatuli (1996), Konflik Aceh dan Papua, Tragedi Trisakti (1998), Penculikan Aktivis (1997-1998), dan masih banyak lagi.
Catatan dan Kuasa
Ihwal peristiwa terakhir, penghilangan paksa aktivis pada 1997-1998, kita bisa membaca catatan kesaksian korban berjudul “Di Kuil Penyiksaan Orde Baru” yang Nezar Patria (kini, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital) tulis. Catatan termaktub dalam majalah Tempo Edisi Khusus Soeharto 10 Februari 2008. Tulisan inilah yang menjadi nadi gagasan Leila S. Chudori menulis novel monumentalnya Laut Bercerita (2017) yang per-Juli 2025 sudah menginjak cetakan ke-100.
Pada 13 Maret 1998, Nezar—aktivis Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID)—bersama kawannya, Aan Rusdianto, digerendel empat orang berbadan kekar memakai seibo di tempat persembunyiannya di rumah susun Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. Nezar mendapat pukulan bertubi, lalu penyiksa membaringkan badannya di atas balok es sembari kaki terikat kabel listrik. Sengatan demi sengatan Nezar rasakan dalam jeda lontaran pelbagai pertanyaan.
Potongan kisah pilu itu bagi Nezar adalah peristiwa yang masih menjadi mimpi buruk. Belum lagi bila mengenang sejumlah kawannya yang hilang dan tak pernah pulang. Mereka adalah Herman Hendrawan, Bima Petrus, Suyat, dan Wiji Thukul. Konon, tim pernah menculik Nezar itu bernama Tim Mawar dari regu Kopassus. Yang ketika itu, Komandan Jenderal Kopassusnya adalah Jenderal Prabowo Subianto (Presiden RI saat ini).
Tragedi dan kekerasan di atas sampai hari ini masih belum mendapat penyelesaian dan pertanggung jawaban dari mendiang Soerharto dan keluarganya. Belum lagi bergeser pada peristiwa kekerasan terhadap rakyat. Seperti terjadi dalam Peristiwa Kedungombo (1985), proyek raksasa yang menenggelamkan 37 desa, terbumbui intimidasi dan terror agar warga melepas lahannya.
Mesin Kekerasan
Membaca rekam jejak gaya memimpin Soeharto, dari awal hingga berakhirnya, Orde Baru memang menumpukan kekuasaan pada kekerasan dan koersi. Terafirmasi oleh Ian Douglas Wilson dalam bukunya Politik Jatah Preman (2018) bahwa “ambisi totaliter” ini memang didamba-dambakan oleh rezim, tetapi tidak pernah tercapai.
Yang benar-benar berhasil dikukuhkan-lanjutkan, lanjut Douglas, ialah pemusatan yang memadai atas sarana utama kekerasan. Dengan dasar itu, tak heran bila Hilmar Farid, sejarawan Institus Sejarah Sosial Indonesia, sependapat mengatakan sejarah Orde Baru adalah sejarah kekerasan.
Peristiwa demi peristiwa kekerasan terjadi semasa Soeharto memimpin rezim Orde Baru. Dia begitu kukuh mempertahankan tampuk kekuasaannya dengan pelbagai macam cara. Culas, kepicikan, hingga kekerasan. Hingga terjadi pada suatu masa, pada saat bangsa ini dipimpin oleh mantan menantunya, upaya pemutihan nama Sang Jenderal tengah diupayakan.
Bermacam ikhtiar tertapis, mulai dari penghapusan segala bentuk kebengisan dalam catatan sejarah bangsa, hingga penganugerahan gelar kehormatan pahlawan nasional. Cara ini mereka (kelompoknya) tempuh demi mengelantang noda durjana yang pernah mendiang lakukan. Begitu naif, sesiapun itu, yang mengusung Soeharto menjadi pahlawan nasional. Tidak cukupkah mendiang dengan segala ketamakannya berkuasa selama 32 tahun?
Seburuk-buruknya hati seseorang, dalam nurani terdalamnya, rasanya bakal menolak seorang penjahat (politik) mendapat sematan sebagai seorang pahlawan nasional. Padahal “pahlawan” menurut KBBI Daringialah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran; pejuang yang gagah berani; hero.
Soeharto memang menonjol dalam pembangunan, pun bermacam kekerasan. Berkorban membela kebenaran? Ah, tentu tidak. Justru dia mengorbankan banyak hal; kemajemukan, kebudayaan, bahasa, rakyat, uang, dan sederet hal lainnya. Untuk disebut pejuang saja dia amat tak pantas, apalagi pahlawan nasional. Jadi superhero bagi keluarganya mungkin cocok.
Sudah sepantasnya, sebagai warga negara, kita tak lagu malu mengisahkan kesejarahan bangsa ini terlepas baik atau buruk. Pantas jika Indonesia masih belum menjadi negara maju seperti Jerman, Jepang, Inggris, atau lainnya. Salah satu faktornya, menurut Dandhy Dwi Laksono, karena Indonesia masih belum selesai dengan sejarahnya sendiri.
Bangsa ini penakut, kata Gus Dur, karena tidak mau bertindak kepada yang bersalah. Eh, yang bersalah malah mendapat nobatan pahlawan nasional. Ampun. Hanya pengecut tulen yang mendukung mati-matian penjahat kemanusiaan agar mendapat sandangan gelar pahlawan nasional. []