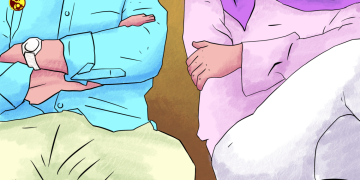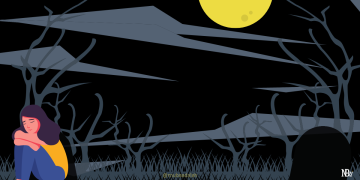Mubadalah.id – Bisma Yang Agung, putra Dewi Gangga, yang telah bersumpah membujang seumur hidup, menjadikan pengabdian seluruh hidupnya hanya kepada Dinasti Kuru sebagai janji kewajiban. Ia tak memiliki motivasi kepentingan pribadinya sendiri, apakah benar-benar bisa kita anggap mulia dan terbebas dari dosa?
Apakah nilai kewajiban yang ia ambil itu tak luput dari bias dan noda? Dan dalam semua itu, apakah ia lantas serta merta bisa tergelari Pahlawan?
Mari kita berpikir. Simaklah dialog epic—saya menyebutnya demikian—antara Bisma dan Krisna saat perang Baratayuda. Di serial Mahabarata yang dulu rutin tayang di ANTV, dialog tersebut menyuguhkan pemahaman tidak mainstream untuk kita pahami kembali.
Kerucut yang kiranya dapat kita pahami dari dialog tersebut ternyata keterikatan janji kewajiban dan keteguhan Bisma dalam memegang sumpahnya justru menjadi penghalang bagi seluruh kesejahteraan manusia dan takdirnya.
Terlepas dari interpretasi macam-macam tentang kemenangan pihak Pandawa berkat politisasi kesadaran yang Krisna lakukan terhadap panglima-panglima perang pihak Kurawa, termasuk yang dilakukan terhadap Bisma.
Ada satu benang merah pelajaran yang sungguh-sungguh harus kita pahami dari setiap dialog epic yang selalu menyertai gugurnya panglima-panglima tersebut. Bahwa seluruh nilai kebaikan, kesejahteraan, dan keadilan haruslah kita pahami dari sudut pandang nasib hidup umat manusia secara menyeluruh—bukan dari golongan, apalagi dinasti.
Relasi Kuasa
Sampai saat ini, kita sadari atau tidak, logika berpikir kebaikan, kesejahteraan, dan keadilan yang kita pahami serta lakukan hampir seluruhnya bersifat golongan dan penuh relasi kuasa. Prinsipnya sudah bisa kita tebak: dari atas ke bawah.
Seperti kebiasaan tokoh-tokoh pejabat kita yang gemar sekali melakukan pembangunan atas nama pemerintah demi nasib baik hidup rakyat, tetapi justru mereka lakukan dengan mengintervensi cara berpikir rakyat. Alhasil, capaian pembangunan hanya tampak berhasil secara statistik-kuantitatif. Sedangkan secara substantif-kualitatif nasib rakyat tetap gitu-gitu aja. Bahkan semakin memprihatinkan.
Dialog epic antara Bisma dan Krisna, saya pikir sedang memberi pengetahuan dan mengajari kita bahwa sosok Bisma, yang keagungannya menggema di seluruh wilayah Arya, ternyata juga dapat mengalami bias egoistis.
Menganggap serta-merta janji dan sumpahnya itu adalah sebuah jalan kemuliaan memperjuangkan keadilan. Padahal, janji serta sumpahnya tersebut justru membelenggunya mengambil keputusan penting. Malah membikin nasib seluruh umat manusia mati sia-sia, hingga perang besar terjadi.
Kekeliruan Bisma terletak pada ketidaktahuan dan kekolotannya memahami janji serta sumpahnya. Oleh karenanya, boleh kita katakan, Bisma merupakan potret dari keagungan tokoh yang gagal memahami keadilan bagi seluruh nasib rakyat gara-gara sumpah dan janjinya sendiri.
Barangkali Bisma tidak secara langsung dan sengaja merusak kesejahteraan manusia dan takdirnya. Namun, ia tetaplah bersalah. Ia tergelincir masuk terjebak pamrih atas janji dan sumpahnya sendiri. Padahal, janji dan sumpah haruslah membebaskan, bukan malah membelenggu. Melanggar janji dan sumpah demi (membebaskan) nasib hidup seluruh umat manusia adalah hal yang tidak pernah Bisma lakukan.
Problem Bisma dan Gelar Pahlawan Soeharto
Mari kita refleksikan problem Bisma tersebut pada kabar terkini bertepatan peringatan Hari Pahlawan 2025. Jika Bisma sebagai seorang Dewata Agung yang memilih menihilkan kesenangan pribadinya masih saja implisit menjadi penyebab kehancuran kesejahteraan manusia dan takdirnya. Meski tanpa tersadari dan ia sengaja.
Pertanyaannya, lantas bagaimana dengan tokoh yang jelas-jelas teridentifikasi (terang-terangan) menjadi dalang bagi melayangnya ratusan ribu nyawa manusia demi pamrih kesejahteraan hidup hanya untuk anak-turunnya sendiri?
Soeharto tentu saja bukan Bisma. Sangat jauh untuk kita perbandingkan, lebih-lebih kita samakan. Hanya saja ada sambungan nilai yang dapat kita refleksikan sangat mendasar. Terutama dalam upaya bangsa ini memahami motivasi, cara main, dan dampak-dampak dari setiap tindakan yang dilakukan tokoh-tokohnya bagi nasib hidup umat manusia dan takdirnya. Dengan cara demikian itulah seharusnya bangsa ini memahami figur Soeharto pula.
Ujian Moral Ingatan Kolektif Bangsa
Pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional hari lalu telah membawa kita ke dalam pusaran persoalan yang kian rumit sebagai ujian moral bagi ingatan kolektif bangsa.
Baiklah, tidak dapat kita nafikan, bilamana Soeharto dianggap pernah membawa stabilitas ekonomi dan terkenal sebagai “bapak pembangunan”. Tapi ingatlah baik-baik bahwa pembangunan ala modern yang kawin-mawin dengan kapitalisme selalu menciptakan cost kemanusiaan yang serius.
Toh, capaian baiknya sangat tak seberapa daripada kerusakan kemanusiaan yang dihasilkan. Mulai dari menindas kebebasan, membungkam oposisi, memperkaya kroni, dan membiarkan pelanggaran HAM berat tanpa pernah ada pertanggungjawaban. Khususnya yang terjadi pada tragedi 1965–1966.
Lalu penembakan misterius, hingga pembantaian di Timor Timur. Lagi-lagi belajar dari sosok Bisma, bahwa cara terbaik membangun logika pahlawan—secara moral dan historis—haruslah terukur. Bukan semata-mata dari hasil fisik yang diberikan, melainkan lebih pada cara dan nilai-nilai yang kita perjuangkan.
Apa yang kita warisi sebagai bangsa dari sosok Soeharto hampir seluruhnya adalah luka sejarah yang tak pernah berkenan mempertanggungjawabkan diri. Jadi, kalau negara memberi gelar “pahlawan nasional” tanpa pernah menuntaskan kebenaran sejarah dan keadilan bagi korban, itu bagai menulis ulang sejarah bangsa dengan tinta manipulasi. Penghargaan semacam itu jelas berpotensi menghapus luka publik. Bahkan, ada gejala melegitimasi kekuasaan otoritarian masa lalu sebagai “prestasi”.
Situasi Epistemik Bangsa
Mari kita elaborasi agak filosofis. Hannah Arendt, ketika menulis banality of evil, merefleksikan figur Eichmann untuk menjelaskan lahirnya kejahatan bisa terjadi dari kepatuhan yang tidak berpikir. Dalam maksud ini, ketidakmampuan berpikir (sekaligus ketidaktahuan) adalah modal strategis bagi cara rezim melahirkan dan merawat kejahatan demi kekuasaan yang langgeng.
Kalau kita tarik dalam sosok Soeharto dan situasi politik (pengetahuan) Indonesia, kita bisa menyaksikan sendiri sesuatu yang jauh lebih sistemik dan berbahaya. Bahwa bukan sekadar banalitas kejahatan yang terjadi, tapi instrumentalisasi kejahatan.
Dengan kata lain, kekerasan, penindasan, dan kebohongan (epistemik) tidak lagi dapat kita pahami sebagai produk sampingan kekuasaan. Melainkan telah menjadi pondasi kekuasaan itu sendiri: menjadi “alat rasional” negara.
Jadi kalau Arendt melihat banalitas kejahatan sebagai hasil dari hilangnya kemampuan berpikir kritis, maka di negeri ini kita bisa melihat kelakuan pemerintah yang secara sadar dan sengaja justru memproduksi kondisi tersebut.
Cara yang pemerintah lakukan adalah dengan memanipulasi ingatan kita atas sejarah bangsa. Ketika simbol utama rezim otoritarianisme semacam itu terangkat kembali dengan memakaikan baju “kepahlawanan.” Maka, sebetulnya telah terjadi proses re-normalisasi kejahatan masa lalu yang sedang diupayakan.
Merawat Daya Kritis terhadap Sejarah Bangsa
Pola yang sebetulnya umum kita jumpai karena terlampau sering dilakukan. Negara, dengan segala instrumen kekuasaannya, hampir selalu berupaya bahu-membahu menulis ulang moral publik dengan mengotak-atik fakta-fakta sejarah bangsa dengan cara tidak adil. Sampai pada upaya itu berhasil dilakukan, maka terjadilah sophisticated evil: kejahatan yang sadar diri dan terstruktur rapi.
Tak hanya itu saja. Situasi pengetahuan kebangsaan kita juga semakin genting ketika sosok Marsinah diangkat pula sebagai pahlawan berbarengan dengan figur Soeharto. Jelas ini bukan sekadar ironi moral, tetapi merupakan penghinaan yang membalik moral.
Marsinah adalah representasi filosofis-emansipatif tentang situasi pengetahuan dan ketidakadilan bangsa. Menyandingkan sosok Marsinah dengan figur represif yang menjadi dalang di balik pembunuhannya justru sedang menyuguhkan “kolase sinis” khas produk psudo-nationalism.
Alarm bahaya epistemik sudah berbunyi. Situasi pengetahuan bangsa sedang genting—dan terus akan genting. Kita jangan sampai kehilangan diri dan harus terus merawat daya kritis terhadap sejarah bangsa. Jadi, mulai dari sekarang segera kita teguhkan hati: ini bukan hanya soal sikap moral, tetapi sekaligus upaya menggugat dan menemukan status ontologis pikiran bangsa. []