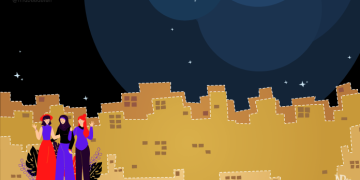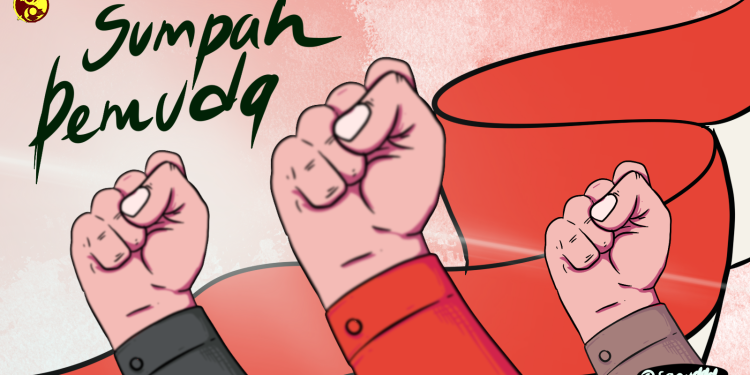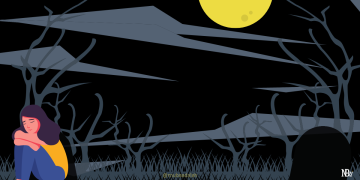Mubadalah.id – Sumpah Pemuda adalah pijakan kemerdekaan. Tidak cukup sekadar memperingatinya, kita mesti pula memahami dan memaknainya. Sejauh mana imajinasi pengetahuan kita hari ini merefleksikannya menjadi penentu kemana arah masa depan bangsa akan berlabuh.
Ada banyak cara merefleksikan makna Sumpah Pemuda di hari ini yang penting kita lakukan demi sebuah cita-cita luhur bangsa yang berkemanusiaan dan berkeadilan. Satu di antara sekian cara merefleksikan makna Sumpah Pemuda bisa kita mulai dengan mengelaborasi rumusan pertanyaan. Bagaimana Sumpah Pemuda dipahami dalam epistemologi mubadalah?
Rumusan tersebut lahir tatkala saya purna mengikuti diskusi daring “97 Tahun Sumpah Pemuda: Berbangsa melalui Lensa Kesalingterhubungan Praktik Berpengetahuan” yang terselenggara oleh Forum Guru Besar ITB.
Ada banyak butir-butir insight yang bermunculan dalam diskusi tersebut. Namun saya hanya akan mengacu pada telaah yang tersampaikan oleh Prof. Musdah Mulia. Beruntung sekali saya dapat membaca makalah utuhnya “Menghidupkan Kembali Praktik Berpengetahuan Perempuan: Menuju Pendidikan dan Pembangunan Bangsa yang Emansipatoris”.
Berkat uraian Prof. Musdah Mulia pulalah saya akhirnya dapat menyusun rumusan pertanyaan yang pas sebagaimana telah saya sebut sebelumnya—dan menjadi pemandu tulisan ini diketik. Barangkali dalam imajinasi kita, meski Sumpah Pemuda sudah berumur 97 tahun. Pemahaman kita terhadapnya bisa jadi masih sangat bernuansa maskulin. Sulit bagi kita untuk tidak membayangkan Sumpah Pemuda berwujud barisan laki-laki yang satu di antaranya berpidato secara gagah: berikrar tentang satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa.
Padahal, fakta membuktikan bahwa di balik peristiwa bersejarah itu, tulis Prof. Musdah Mulia, “perempuan Nusantara juga sedang berjuang dalam diam dan sunyi, memperjuangkan ruang dan martabatnya di tengah struktur sosial yang timpang.”
Hal demikian juga ditegaskan oleh Susan Blakburn (2004), seorang peneliti sejarah gerakan perempuan Indonesia yang menegaskan bahwa gerakan perempuan Indonesia tidak pernah terpisah dari sejarah nasionalisme itu sendiri. Keterlibatan perempuan dalam membangun gagasan Indonesia justru dalam posisinya sebagai entitas moral, bukan semata-mata politik.
Sumpah Pemuda dan Makna Emansipatoris
Kita mesti memahami bahwa, sebagaimana Prof. Musdah Mulia tuliskan, “Sumpah Pemuda sejatinya bukan hanya tentang persatuan bangsa, tetapi juga tentang emansipasi manusia”. Karena itu, dalam konteks hari ini, membaca dan merefleksikan ulang makna Sumpah Pemuda dari perspektif perempuan berarti berupaya mengembalikan makna emansipatorisnya. Artinya, harus kita pahami bahwa Nasionalisme 1928 bukanlah nasionalisme eksklusif yang memusat pada negara, tetapi nasionalisme inklusif yang berakar pada kemanusiaan.
Frasa “Tanah Air” mengandung makna yang merepresentasikan ruang hidup, ibu pertiwi, dan etika pemeliharaan. Frasa “Bangsa” merepresentasikan mengenai solidaritas gender dan kebangsaan moral. Adapun frasa “Bahasa” merepresentasikan suara, kesadaran, dan alat pembebasan. Masing-masing memiliki aksentuasi kebermaknaan yang bisa kita jadikan titik pijak bagi upaya kita menyongsong masa depan banga yang berkemanusiaan dan berkeadilan.
Memahami Sumpah Pemuda melalui perspektif emansipatoris harus kita mulai dengan menempatkan Sumpah Pemuda sebagai teks terbuka yang mengundang interpretasi baru. Tanah air bukan hanya ruang geografis, tetapi rumah kemanusiaan yang harus bebas dari kekerasan dan ketimpangan.
Bangsa bukan sekadar identitas politik, melainkan solidaritas etis yang menghormati hak setiap warga tanpa diskriminasi. Terakhir, bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi sarana dialog yang membebaskan dan meneguhkan keberagaman.
Ada benang merah yang dapat kita tarik pada simpul yang sama tentang praktik berpengetahuan perempuan (dan gerakannya), epistemologi mubadalah, sekaligus wacana emansipatoris. Ketiganya apabila kita jadikan instrumen untuk merefleksikan Sumpah Pemuda, maka sejatinya kita sedang berupaya memperbarui makna Sumpah Pemuda sebagai “Sumpah Kemanusiaan”. Hal inilah yang juga menjadi kerucut yang hendak tersampaikan Prof. Musdah Mulia dalam rangka memperingati 97 Tahun Sumpah Pemuda.
Sumpah Pemuda dan Demokratisasi Pengetahuan
Saya dan Anda tentu sepakat bahwa epistemologi modern yang kita warisi dari kolonialisme telah menanamkan logika patriarki dalam cara pikir pendidikan dan kebudayaan hidup kita. Rasionalitas kita anggap unggul, universal, maskulin, dan netral. Sementara pengalaman emosional, afektif, dan relasionalitas—yang itu terasosiasikan dengan sosok perempuan—kita anggap tidak ilmiah. Dalam hal ini, sebetulnya kita sedang mengalami krisis sekaligus keterputusan epistemik.
Kita membutuhkan apa yang disebut demokratis pengetahuan dengan melakukan revisi paradigma ilmu pengetahuan agar tidak lagi bersifat maskulin, kolonial, dan elitis. Kita memerlukan adanya praktik berpengetahuan perempuan yang mengintegrasikan akal dan nurani sangat penting kita lakukan untuk menyongsong masa depan bangsa yang berkemanusiaan dan berkeadilan.
Dengan kata lain, kita perlu memahami pengetahuan bukan sebagai dominasi, tetapi sebagai care, yaitu kepedulian terhadap sesama bahkan alam. Kita perlu mengenal dunia bukan dengan jarak, tetapi dengan kedekatan. Kita perlu memaknai ilmu bukan sebagai kekuasaan, melainkan sebagai tanggung jawab untuk merawat kehidupan. Inilah yang oleh Carol Gilligan (1982) disebut ethics of care.
Bilamana kita terapkan pada konteks kebangsaan, maka ethics of care tersebut dapat menjelma menjadi nationalism with compassion. Nasionalisme yang penuh rasa empati dan solidaritas. Jika kita jernih, sebetulnya epistemologi semacam inilah yang cocok dengan watak kultur pengetahuan kita. Yakni cara berpengetahuan yang memiliki keseimbangan antara akal dan nurani, antara rasionalitas dan kasih sayang.
Oleh karenanya, Bangsa Indonesia sudah semestinya kita bangun di atas prinsip kemanusiaan yang memberi ruang bagi bentuk pengetahuan yang penuh empati, keadilan, dan cinta kasih.
Sebuah Upaya “Menjadi Indonesia”
Sebagai kelanjutan dari upaya melakukan demokratis pengetahuan, kita memerlukan pula standpoint epistemology yang jelas dengan mengintegrasikan, misalnya, pengalaman perempuan di lingkungan patriarkis, kelompok marjinal di lingkungan hegemonik.
Selain itu juga komunitas-komunitas adat sebagai sumber pengetahuan yang sah. Kemudian, perlu pula untuk mendorong model penelitian partisipatoris dan reflektif yang menempatkan masyarakat bukan sebagai objek riset, tetapi sebagai subjek yang turut memproduksi pengetahuan.
Peran pemerintah tentu sangat kita perlukan guna menegaskan mengenai visi pendidikan yang emansipatoris dalam arah kebijakan nasional yang dibuat. Bukan hanya mengejar kompetensi teknis semata. Apalagi sekadar berorientasi pada capaian produktivitas berupa grafik dan angka-angka belaka. Pemerintah harus mulai belajar melihat persoalan bangsa kita secara kualitatif-substansial.
Refleksi demikian sangat kita perlukan sekaligus penting untuk terimplementasikan hasilnya bagi bangsa kita. Tidak hanya lantaran sesuai dengan kultur epistemik masyarakat (Nusantara), tetapi juga dalam posisi bangsa kita sebagai Global South.
Artinya, sumber pengetahuan bukan lagi kita agung-agungkan dengan mengambilnya dari negara bagian utara saja, tetapi juga dari negara bagian selatan. Di mana sebetulnya jauh lebih memiliki kekayaan epistemik melimpah dalam ranah pengetahuan. Demikianlah cara awal kita memahami makna Sumpah Pemuda dalam konteks kekinian.
Maka dengan berbagai realita-realita persoalan kebangsaan yang sedang Indonesia hadapi saat ini. Sumpah Pemuda sejatinya sedang mengingatkan kita, bahwa untuk membangun bangsa (dan “menjadi Indonesia”) yang benar-benar beradab. Upaya membangun praktik berpengetahuan kesalingterhubungan (mubadalah), emansipatoris, dan demokratis.
Lalu mengusung etika kepeduliaan harus menjadi fondasi pendidikan dan kebijakan kita. Sederhana saja, hal ini karena “bangsa (kita) ini tidak butuh manusia yang hanya cerdas otaknya, tapi kering hatinya. Kita butuh manusia yang mampu berpikir dan berempati sekaligus,” tulis Prof. Musdah Mulia. []