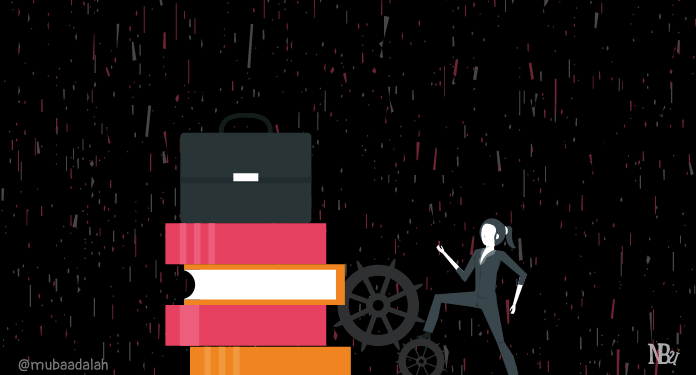Mubadalah.id – Sejak tahun 2009 setiap tanggal 20 Februari diperingati sebagai Hari Keadilan Sosial Sedunia (Social Justice Day). Peringatan ini dideklarasikan oleh PBB sebagai bentuk mengupayakan pembangunan sosial dan martabat kemanusiaan. Social Justice Day diperingati untuk terus menyuarakan misi global yang sedang diperjuangkan oleh setiap negara, yakni kemiskinan, diskriminasi, dan juga kesetaraan gender.
Merujuk pada tema besar yang diusung pada peringatan Social Justice Day 2022, yakni “Achieving Social Justice through Formal Employment“, mencapai keadilan sosial melalui pekerjaan formal. Jika melihat tema ini, tentu perjalanan panjang dan mungkin cukup terjal masih menjadi tantangan bagi para perempuan pekerja. Pasalnya, hingga hari ini peran perempuan dalam pekerjaan-pekerjaan formal masih sangat minim.
Dari data Badan Pusat Statistika, dalam tiga tahun terakhir saja jumlah perempuan yang bekerja di sektor formal masih berada di bawah 50%. Pada tahun 2019 mencapai angka 39,19% dan mengalami penurunan pada tahun 2020 yang disebabkan faktor-faktor selama pandemi, menjadi 34,65%. Angka ini cukup rendah jika dibandingkan tahun sebelumnya, dan pada tahun 2021 lalu mengalami sedikit peningkatan menjadi 36,20%.
Namun angka-angka ini masih saja berada dibawah angka 50%, yang memberikan gambaran bahwa keterlibatan perempuan dalam pekerjaan formal masih jauh dengan laki-laki. Karena mayoritas perempuan sudah diberatkan dengan pekerjaan-pekerjaan domestik. Apalagi beban ini menjadi berkali-kali lipat selama terjadi pandemi sejak 2020 lalu.
Tidak heran jika tema peringatan Social Justice Day kali ini berfokus untuk mencapai keadilan sosial melalui pekerjaan formal. Karena memang keadilan dan kesetaraan pada sektor ini masih jauh, terlebih bagi perempuan. Berdasarkan data ILO (2015), secara global jumlah angkatan kerja perempuan mencapai 51%, namun masih sangat jauh dengan keterlibatan laki-laki dalam angkatan kerja yang mencapai sekitar 82% .
Terkait lecilnya angka keterlibatan perempuan ini UNFPA (2014) menuliskan bahwa disebabkan adanya kecenderungan untuk mengkategorikan perempuan sebagai bukan angkatan kerja. Karena dalam kehidupan sehari-hari perempuan lebih banyak menghasilkan produk untuk dikonsumsi dalam rumah tangganya sendiri, mulai dari menyiapkan makanan, merawat anak, hingga merawat orang tua yang ada di rumah. Di mana tugas-tugas ini hampir seluruhnya menjadi tugas perempuan, yang berdampak pada ketersediaan perempuan untuk bekerja.
Ragam Diskriminasi Perempuan Pekerja
Selain hal-hal mendasar di atas dalam Jurnal Perempuan Edisi 107, Gadis Arivia menyebutkan dalam formulasi teori interseksualitas pada isu kerja dan gender, terkait praktik diskriminasi terhadap perempuan yang harus dibongkar di tempat kerja, yakni
Hypermasculinity, pengalaman buruk perempuan dalam menghadapi persaingan kerja dengan laki-laki. Pekerjaan formal cenderung memiliki wajah yang sangat maskulin, sehingga tak jarang beberapa pekerjaan dianggap tidak pantas bagi perempuan. Hal ini berujung pada bentuk diskriminasi yang kedua, yakni selective exit, persaingan dan kondisi yang buruk membuat perempuan mengundurkan diri dari dunia kerja atau menerima pekerjaan yang lebih rendah. Untuk menghindari persaingan yang kerap kali perempuan berada di posisi yang kalah dari laki-laki, perempuan akan memilih untuk resign ataupun memilih pekerjaan yang lebih rendah.
Perempuan yang memilih pekerjaan pada level yang lebih rendah akan berujung pada bentuk diskriminasi yang selanjutnya, yakni sticky floor practice adanya kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan pada data ILO (2015) tercatat pendapatan perempuan berada jauh pada kisaran 23% bahkan lebih rendah dari laki-laki, pada pekerjaan yang sama sekalipun.
Bentuk diskriminasi yang terakhir berkaitan dengan pengalaman biologis yang dialami perempuan yakni mulai dari hamil, melahirkan hingga menyusui, yang disebut dengan istilah mommy tax, perempuan yang hamil dan membesarkan anak akan mau tidak mau memperlambat laju karirnya.
Hal ini menjadi kegelisahan bagi perempuan-perempuan yang sudah memiliki anak untuk tetap bekerja, karena hal yang diterima dari masyarakat bukan dukungan melainkan bully-an dianggap tidak menjadi ibu yang baik. Padahal hal seperti itu adalah hak privasi perempuan yang tidak membutuhkan validasi dari masyarakat.
Kesetaraan dan Keadilan bagi Perempuan Pekerja
Berdasarkan ragam diskriminasi terhadap perempuan di atas tentunya menjadi penghambat untuk pemberdayaan perempuan dalam dunia kerja. Sejalan dengan ini, Prof. Musdah Mulia dalam buku Muslimah Reformis menjelaskan setidaknya ada tiga hal yang menjadi penyebab utama lambatnya pemberdayaan perempuan dalam sektor ekonomi, yakni
Persoalan kultural, hal ini merupakan dampak panjang dari sistem patriarki yang mengakar di masyarakat yang menyebabkan perempuan secara budaya ditempatkan pada kerja-kerja domestik. Karena pekerjaan publik hanya ditujukan bagi laki-laki yang memiliki tanggung jawab lebih mencari nafkah untuk membiayai perempuan (istri).
Dalam konteks ini pula, pekerjaan-pekerjaan domestik dianggap sebagai pekerjaan yang tidak bernilai ekonomi. Padahal tidak dapat dipungkiri bahwa tugas perempuan tidak hanya melakukan tugas domestik saja, akan tetapi tugas reproduksi dan tugas sosial masyarakat kerap kali dibebankan kepada perempuan yang membuatnya mengalami multiple burden, yang pekerjaannya tidak memiliki nilai jual.
Persoalan struktural, perbedaan peran laki-laki dan perempuan saat berkeluarga secara struktural diatur dalam undang-undang. dalam UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 31 Ayat (3) menyebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Sehingga dari bunyi pasal ini saja, terlihat jelas bahwa saat berkeluarga laki-laki memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan istrinya (menafkahi) sedangkan perempuan secara tidak langsung ‘dilabeli’sebagai ibu rumah tangga.
Hal ini membuat konstruk yang dibangun di masyarakat semakin kuat, di mana jika ada laki-laki tidak memiliki pekerjaan mapan dianggap sebagai suami yang tidak bertanggung jawab, begitu pula sebaliknya jika istri bekerja melebihi suaminya dianggap perempuan yang tidak baik.
Dua hambatan diatas kemudian diperkuat dengan hadirnya persoalaan interpretasi agama, di mana beberapa ayat Al Qur’an dimaknai secara tekstual terkait kewajiban suami untuk menafkahi dengan bekerja dan istri tidak wajib bekerja, dan jika istri harus bekerja pendapatannya bukan sebagai pendapatan utama keluarga.
Ayat yang banyak dirujuk untuk membenarkan statemen ini biasanya QS. At Thalaq [65]: 7 dan QS. Al Baqarah [2]:233, padahal jika dicermati lebih detail kedua ayat tersebut tidak ada yang melarang perempuan untuk bekerja. Ditambah jika melihat kondisi perekonomian saat ini yang semakin pelik, maka antara suami dan istri sudah seharusnya saling berkolaborsi untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama sehari-hari.
Tiga hambatan ini menjadi semacam pokok permasalahan timbulnya ragam diskriminasi bagi perempuan pekerja. Crenshaw menuliskan dalam Schnall (2020), bahwa jika kita gagal dalam mengidentifikasi persoalan (masalah) maka kita akan gagal mencari solusi. Sama halnya dalam menemukan solusi untuk mencapai kesetaraan dan keadilaan bagi perempuan pekerja. Dari ragam bentuk diskriminasi dan juga hambatan dalam upaya keterlibatan perempuan dalam pekerjaan formal, merupakan hal mendasar yang diperlukan untuk menemukan solusi dalam mengatasi minimnya keterlibatan perempuan dalam pekerjaan formal kedepannya.
Moment Social Justice Day seharusnya menjadi titik refleksi bersama untuk kemudian seluruh elemen masyarakat baik secara struktural maupun kultural, menguatkan kembali peran dan posisi perempuan pekerja pasca dua tahun melewati pandemi.
Tema yang cukup kuat dalam peringatan di tahun 2022 ini, cukup menjadi pemantik untuk aksi-aksi nyata dalam proses pemberdayaan perempuan pekerja. Karena tidak dapat kita pungkiri jika kesetaraan dan keadilan diperoleh oleh perempuan pekerja tentunya akan meningkatkan kesejahteraan perempuan yang otomatis memiliki dampak pada peningkatan perekonomian negara. []