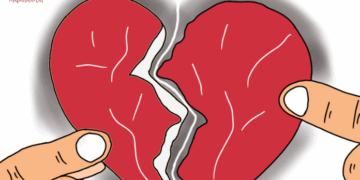Mubadalah.id– Sepekan terakhir ini saya agak risau, pasalnya di tengah kondisi yang membuat kita ‘terbatas’ kampanye atau glorifikasi nikah muda populer lagi. Sebenarnya saya juga bingung akan menyebut itu sebagai nikah muda atau nikah anak. Kampanye nikah muda kali ini dilakukan oleh influencer yang memiliki subscriber dan follower cukup banyak di platform youtube dan instagram.
Salah satu dari mereka bahkan mengumbar konten berbau seksual dengan judul yang clickbait macam “bagaimana rasanya pertama kali tidur dengan suami” hingga konten-konten yang mengandung bumbu kebaperan bagi jomblo macam saya. Sebenarnya, kegelisahan yang saya alami bukan karena saya tidak bisa melakukan hal yang sama, tapi lebih kepada bayangan pengalaman orang di sekitar saya.
Barangkali nikah muda bisa terjadi pada sahabat milenial saya yang hanya melihat glorifikasi nikah muda ala-ala influencer “berada” dengan cerita kemudahan dan kebahagian yang meliputi proses mereka membangun rumah tangga. Apa semua orang bisa melakukan hal yang sama dan mendapatkan glorifikasi yang sama? Bisa jadi tidak.
Saya percaya bahwa pengalaman setiap orang akan berbeda karena latar belakang personal, kondisi psikologis, fisik hingga ekonomi yang berbeda. Bahkan pengalaman itu juga masih dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya di masa mereka masing-masing.
Saya teringat salah satu pengalaman tentang nikah muda dari orang di sekitar saya yang terjadi pada teman saya. Kala itu kami masih kelas 10 Madrasah Aliyah, di usia sekitar 15-16 tahun, teman saya terpaksa harus meninggalkan bangku sekolah karena telah dilamar tunangannya. Bahkan tak segan, sang tunangan menyatakan tak lagi bisa menunggunya jika ia menolak.
Kala itu saya bertanya-tanya, mengapa perempuan tak bisa mendapatkan pilihan yang lebih bagus, bahkan harus merelakan masa-masa produktif dalam mengenyam pendidikan. Tapi pikiran macam itu hanya ada dalam benak saya tanpa mampu saya sampaikan di saat itu.
Mungkin saya pura-pura lupa dan menghapus ingatan bahwasanya ibu saya menikah di usia yang juga terbilang muda, 19 tahun. Tapi faktanya itu tidak terjadi hanya pada ibu saya, melainkan juga mbah Putri saya pun demikian. Perjodohan dan pernikahan yang diatur oleh Mbah Buyut saya bahkan dilakukan ketika Mbah Putri ada di usia 13 tahun, hingga melahirkan ibu saya pada usia tidak genap 15 tahun.
Pernikahan itu juga tidak dapat bertahan lama, karena beberapa hal, Mbah Putri dan Mbah Kakung berpisah sebelum Mbah Putri melahirkan ibu. Karena berpisah di usia yang muda, Mbah Putri pun melanjutkan kembali pendidikannya.
Meskipun di masa itu nikah muda masih marak dan karena belum ada undang-undang yang mengatur hal tersebut, bahkan di tengah kondisi ekonomi Mbah yang lebih dari cukup, perpisahan itu tetap terjadi. Saya jadi berandai-andai, apakah semisal kondisi ekonomi Mbah jauh di bawah, pernikahan itu akan tetap ada atau tidak.
Dua pengalaman perempuan yang saya ketahui itu mengajarkan pada saya bagaimana dampak pernikahan di usia muda dari sudut perempuan, bagaimana repotnya Mbah Putri saya ketika memiliki anak di usia 15 tahun.
Bahkan di tengah kondisi “berada”-pun, nikah muda tak selalu membawa kesan glorifikasi seperti yang banyak digaungkan. Apalagi misalnya di tengah pasangan muda yang timpang (baik latar belakang pengetahuan, finansial, hingga nasab sekalipun) tanpa karakter dewasa yang dimiliki.
Meskipun begitu, saya tidak hendak menyudutkan mereka yang memilih menikah di usia muda. Saya hanya berharap mereka yang terlanjur menikah di usia muda belajar membangun karakter kesalingan sehingga beban dan rintangan yang akan mereka hadapi tidak hanya ditanggung pada seorang saja, melainkan sama-sama dipikul dan dijinjing.
Lebih lagi, agar mereka tidak hanya berkampanye keenakan dan pamer kemesraan saja, melainkan memberi edukasi tentang bertanggungjawab memelihara kesalingan. Yakni, kesalingan untuk memahami, menyayangi, dan membantu satu sama lain, hingga kesalingan untuk memuliakan dan membangun keadilan dalam mahligai rumah tangga yang bahagia. []