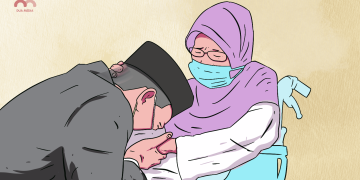Mubadalah.Id- Salah satu cerpen terbaik adalah yang berjudul Rumahku Surgaku. Dalam cerpen Rumahku Surgaku bercerita tentang rumah, yang seharusnya menjadi surga bagi seseorang. Berikut versi lengkap cerpen; rumahku surgaku.
Be it ever so humble, it’s more than just a place.
It’s also an idea—one where the heart is.
(Verlyn Klinkenborg)
Kuningan, 23 Desember 2011
Matahari belum lagi sempurna pancarkan sinarnya. Sementara, penghancuran telah sempurna berlangsung di rumah saya. Ruang tamu yang sekaligus berfungsi sebagai ruang keluarga dan juga ruang kerja, tak lagi pantas disebut ruang tamu. Tak ada titik yang tersisa bagi tamu macam apa pun untuk duduk. Aneka mainan terserak berantakan memenuhi seluruh ruang.
Gadis cantik berambut pirang teronggok begitu saja tanpa tangan dan kaki. Ada juga gadis dengan tubuh semampai tergeletak di sisi televisi tanpa kepala. Tubuh gadis lain terjuntai di atas ranjang tanpa sehelai benang pun menutupi tubuhnya. Tetapi, kaki gadis itu tinggal satu.
Genangan air dengan warna beraneka akibat campuran cat warna, lipstik, bedak, dan juga bubuk pacar tersebar membuat becek ruang tamu hingga dapur. Kertas gambar, kertas tisu, dan sobekan-sobekan kertas koran berserakan di antara kereta dan mobil-mobilan.
Pagi ini rumah kami seperti diterjang badai topan. Aneka barang dan perabotan terserak berantakan. Boneka-boneka barbie dengan gaya rambut dan warna kulit beraneka terserak di mana-mana dengan tubuh yang nyaris semuanya tidak utuh.
Malam tadi, Aisyi, cucu saya nginap di rumah kami. Usianya baru tujuh tahun. Tubuhnya mungil. Gerak-geriknya lincah. Ia jadi kawan bermain yang paling akur untuk anak saya, Hagia, yang berusia lima tahun. Meski usianya lebih tua, Aisyi manggil anak saya dengan panggilan bibi, “bibi kecil”. Ya, seperti itulah tradisi kami, orang Sunda, mungkin juga suku-suku lain di Indonesia.
Begitu saja, saat seorang bayi dilahirkan, ia telah menjadi ayah, juga sekaligus kakek, paman, dan lain-lain. Aisyi manggil saya “aki” karena neneknya adalah kakak saya. Maka, ia manggil Hagia “bibi”. Kadang-kadang saya merasa risih ketika orang yang berumur jauh lebih tua bersalaman dan mencium tangan saya, semata-mata karena bapak atau ibunya adalah adik bapak atau ibu saya.
Karena sudah lama mentradisi, sering kali saya berjumpa orang yang saat bersalaman ingin agar tangannya dicium. Mencium tangan saat bersalaman menandakan penghormatan, penghargaan, ketundukan, ketaatan, dan lain-lain. Karena itulah kita sering melihat orang yang dicium tangannya saat bersalaman menunjukkan pandangan yang bangga—karena dirinya merasa terhormat.
Aisyi, cucu saya itu, berlibur di kampung kami, di rumah neneknya, kakak perempuan saya. Pagi-pagi, Hagia telah bermain bersama Aisyi di ruang tamu, kamar tidur, hingga dapur dan kamar mandi. Semua ruang yang kering dan datar mereka jelajahi. Bekas-bekas permainan tadi malam belum lagi diberesi.
Pagi ini, kehancuran menjadi-jadi. Anteng bermain, tiba-tiba seekor burung Gereja, yang tampaknya masih sedang belajar terbang, masuk ruang tamu kami dari pintu depan yang terbuka. Meski berumah di atas masjid atau di atas rumah naib, mereka tetap disebut burung gereja.
Terbang mengitari ruang beberapa saat, burung itu sadar, ia tersesat. Ia sadar, ini bukan rumahnya. Ini bukan tempatnya sehingga ia berusaha mencari lubang keluar. Beberapa kali ia nabrak kaca jendela—dikiranya lubang besar tanpa penghalang.
Ilusi. Aisyi dan Hagia, yang melihat burung itu masuk ruangan, bergegas menutup pintu depan sehingga burung itu terjebak di dalam. Meski rumah saya ini jauh lebih besar dari sarangnya, burung itu merasa ia tak layak dan tak semestinya berada di sini. Ia tidak betah berada di rumah kami.
Kini, gerak dan lintasan terbangnya terlihat semakin panik. Tabrak sana tabrak sini. Aisyi dan Hagia teriak-teriak mengejar burung itu. Keduanya lalu memanggil seraya menarik tangan saya.
“Akiiii… itu ada burung masuk….” teriak Aisyi.
“Iya, aki tahu,” huh… rada berat nyebut diri sendiri “aki” meski telah banyak rambut kelabu tumbuh di kepala saya.
“Paa… tangkap burungnya…” timpal Hagia.
Bagi anak kecil, burung adalah barang langka yang lucu dan menarik untuk dijadikan mainan, sama halnya ketika mereka melihat ikan-ikan kecil, atau mempermainkan kumang. Mereka ingin agar burung gereja yang tersesat itu ditangkap.
Saya bergegas mengejar burung itu. Saya berusaha memojokkannya di sudut ruang, juga di daun jendela, antara kaca dan tirai. Akhirnya, setelah beberapa lama, burung itu terpojok di bawah lemari pakaian. Saya berhasil menangkapnya, lalu membuka pintu dan berniat melepaskannya.
Tetapi kedua gadis kecil itu berteriak melarang. Mereka ingin menjamah, menyentuh, bermain-main dengan burung itu. Akhirnya, saya letakkan burung itu pada sebuah tempat sampah berongga. Bagian atas tempat sampah itu saya tutup dengan plastik transparan sehingga anak-anak bisa bermain-main dengan burung itu. Mereka memberinya beras, nasi, juga secangkir air.
Meski sarang itu dipenuhi makanan dan minuman, burung itu tak pernah diam. Ia tak mau mematuki beras yang terserak. Ia berusaha mencari jalan keluar. Ia ingin lari melepaskan diri dari sarang yang sarat makanan.
“Pa, kenapa burung itu tidak mau makan?”
“Tidak tahu, mungkin ia merasa tidak betah meskipun banyak makanan di sini. Ini bukan rumahnya, dan Gia bukan ibunya.”
“Ya udah, biarin aja, nanti juga kalau kelaparan, dia makan,” ujar Gia sambil berlalu meninggalkan tempat sampah yang jadi sangkar burung.
Puas mempermainkan burung itu, anak-anak kembali pada permainan awal, boneka barbie. Burung malang itu loncat dan terbang dalam tabung kecil tempat sampah tertutup plastik transparan. Kasihan melihat burung itu, saya berkata kepada anak-anak, “Gia, Aisyi, burungnya dilepas saja ya …”
“Jangan!!” keduanya teriak serempak sambil berlari mendekati.
“Tapi, kasian burung itu masih kecil. Ibu-bapaknya pasti sedih nyariin dia,” saya mencoba membujuk.
“Ya udah, tangkep aja ibu-bapaknya, jadi gak ada yang sedih…” Hagia berujar kalem.
Saya tersenyum dengar ujarannya, juga terhenyak hingga tak bisa berkata apa-apa. Saya merasa, jawaban anak saya itu sangat logis. Mungkin jika burung ini hidup bersama ibu dan bapaknya, ia mau makan beras atau biji-bijian lain yang diberikan anak-anak. Cukup lama burung itu dibiarkan loncat-loncat di dalam sangkar-dari-tempat-sampah.
Akhirnya, setelah membujuk cukup lama, mereka mau melepaskan burung itu. Bersama-sama kami melepasnya ke alam bebas. Burung itu terbang bebas, mengitari pucuk pohon mangga, hinggap di salah satu rantingnya, lalu terbang lagi.
Mungkin dia harus terbang jauh, atau berebut dengan burung lain untuk mendapatkan satu atau dua biji beras atau seekor ulat, tidak seperti di tempat sampah kami yang penuh biji beras. Meski begitu, ia senang karena dapat terbang bebas. Ia senang meski sarangnya kecil dan basah di saat hujan.
Rumah, sejatinya, meski kecil, jelek, dan sempit, akan selalu menjadi tempat yang paling dirindukan. Meki kita mengembara jauh, melintasi ribuan kilometer, menyeberangi samudera, dan menyambangi tempat-tempat yang jauh lebih indah, hati kita akan selalu terpaut ke rumah.
Meskipun kita menginap beberapa malam atau pekan di sebuah kamar presidential hotel bintang enam dengan segala kelengkapan dan fasilitasnya yang supermewah, kita akan selalu merindukan tidur di rumah kita sendiri. Sejatinya, seperti itulah makna rumah: tempat kita mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan kesenangan. Mungkin karena itulah Rasulullah Saw. pernah bilang bahwa rumahnya adalah surganya (baytî jannatî).
Padahal, rumah Rasulullah dan keluarga beliau (menurut riwayat) sangatlah sederhana, kecil, dan sempit. Mungkin keadaannya seperti rumah-rumah bedeng yang dokontrakkan, atau kos-kosan. Beberapa kotak seukuran kurang lebih 3 X 6 meter berderet di samping Masjid Nabawi.
Rumah yang paling dekat dan berdampingan dengan Masjid adalah rumah Aisyah r.a. Perabotannya pun sangat jauh dari lengkap. Hanya ada perlengkapan masak, perangkat untuk makan, dan perlengkapan tidur. Ranjang Nabi saw. hanya dialasi anyaman pelepah kurma sehingga ketika bangun tidur, tampak bekas-bekas anyaman itu pada pipi dan bagian tubuh beliau yang lain. Keadaan itulah yang pernah membuat Umar ibn al-Khatthab menangis.
Namun, Rasulullah Saw. dengan bangga menyebut rumah beliau sebagai surga. Sebab, rumah semestinya menjadi tempat ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Bahkan, pada beberapa orang, rumah juga menjadi sumber kesehatan.
Sebagai contoh, dalam bahasa Inggris dikenal istilah “homesick”, yang berarti keadaan seseorang yang tidak nyaman, tidak tenang, tidak betah, karena berada di tempat yang bukan rumahnya. Situasi psikologis itu kerap terwujud dalam bentuk sakit fisikal, seperti sakit perut, sakit kepala, dan lain-lain.
Mungkin karena itulah dalam bahasa Arab rumah disebut “maskan”. Kata maskan merupakan ism makân (kata benda menunjukkan tempat) yang berasal dari kata kerja sakana-yaskunu yang berarti merasa tenang dan nyaman.
Dengan demikian, seharusnya rumah menjadi sumber ketenangan bagi para penghuninya. Meskipun sangat sederhana, kecil, dan semmpit, rumah selalu menjadi pilihan kita untuk mendapatkan ketenangan dan kenyamanan. Ada satu ayat Alquran yang sering dikutip dalam khutbah nikah dan ceramah tentang pernikahan, yaitu surah al-Rûm ayat 21:
Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan)-Nya ialah Dia menciptakan dari diri (jenis) kalian pasangan untuk kalian supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih (mawaddah) dan rasa sayang (rahmah).
Sungguh dalam hal itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Dalam surah al-Nahl ayat 80, Allah berfirman, “Dan Allah menjadikan dari rumah-rumah kalian (buyûtikum) sebagai tempat tinggal (sakanâ)”. Ayat itu, dengan kata lain, menunjukkan bahwa ada pula rumah (bayt) yang tidak menjadi tempat tinggal (sakanâ), atau tempat ketenangan. Banyak pula rumah yang menjadi sumber kemarahan, konflik, dan pertengkaran.
Ibn Katsir, dalam kitab tafsirnya, mengatakan, “Allah ta’ala menyebutkan kesempurnaan nikmat-Nya atas hamba-Nya, dengan apa yang Dia jadikan bagi mereka rumah-rumah yang merupakan tempat tinggal mereka. Mereka kembali kepadanya, berlindung, dan memanfaatkannya dengan berbagai macam manfaat.”
Jadi, tujuan adanya pasangan dan hidup berpasangan adalah untuk mendapatkan dan meraih ketenangan. Jika setelah menikah dan berrumah tangga kita justru kehilangan rasa tenang dan damai, berarti ada yang keliru dalam pernikahan itu. Bisa jadi, modal yang telah dinaugerahkan oleh Allah berupa mawaddah dan rahmah telah hilang atau berkurang sehingga sakînah tak kita rasakan.
Maka, agar kita kembali mendapatkan sakinah, kita harus berusaha menumbuhkan dan menjaga mawaddah serta rahmah agar tidak menipis, berkurang, apalagi menghilang. Tanpa mawaddah dan rahmah, bukan sakînah yang akan kita dapatkan, melainkan saqîmah, yang berarti derita, rasa sakit, atau kepedihan.
Persis seperti burung yang saya tangkap dan disimpan di sangkar dari tempat sampah. Meski berlimpah makanan dan minuman, juga aman dari angin atau hujan badai, burung itu terus mencari jalan keluar agar terbebas dari kurungan yang bukan rumahnya.
Demikian bunyi cerpen; rumahku surgaku. Semoga cerpen rumahku surgaku bermanfaat. (Baca juga: Cerpen Cinta Perlu Dijaga)