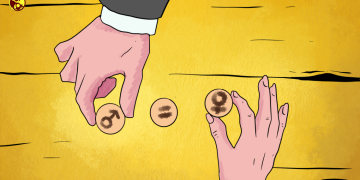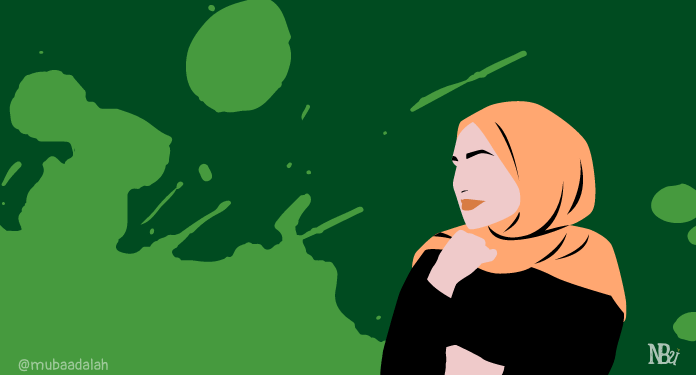“The most courageous act is still to think for yourself. Aloud.”
Coco Chanel
Mubadalah.id – Kapan terakhir kali kamu merasa merdeka? Bukan hanya bebas dari tekanan luar, tapi benar-benar merdeka: untuk memilih, untuk diam, untuk percaya pada jalan hidupmu sendiri?
Aku bertanya ini karena sedang memikirkannya juga.
Satu tahun lagi sebelum aku genap berusia 30. Aku belum menikah. Dan baru saja resign dari pekerjaan yang selama ini dianggap “cita-cita keluarga.” Aku belum punya rumah, belum punya pasangan, belum punya stabilitas versi masyarakat. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa… merdeka.
Dan ternyata, rasa damai itu jauh lebih berharga daripada validasi sosial yang selama ini aku kejar.
Selama ini, kita merayakan kemerdekaan dengan bendera dan kembang api. Tapi bagi perempuan, kemerdekaan sering kali hadir dalam bentuk yang sangat senyap. Ketika kita berkata “tidak” pada ekspektasi yang membelenggu, ketika kita berkata “cukup” untuk relasi yang menyakitkan, atau ketika kita memilih diam, berhenti, dan mengatur ulang hidup yang tak lagi kita kenali.
Kemerdekaan perempuan, bagiku, adalah momen ketika aku memilih keluar dari pekerjaan yang membuatku merasa kehilangan arah. Pekerjaan itu mungkin stabil, mapan, terhormat di mata keluarga. Tapi nilai-nilai di dalamnya perlahan menggerogoti nilai yang kupegang. Aku tahu aku bisa bertahan, tapi aku tidak ingin bertahan hanya untuk terlihat berhasil.
Kemerdekaan juga hadir ketika aku menerima bahwa belum menikah di usia 29 bukanlah kegagalan. Bahwa tubuhku bukan jam dinding yang terus berdetak menuju “expired.” Bahwa hidupku tak harus sesuai urutan yang mereka tetapkan. Angka 30 bukanlah hantu yang menakutkan.
Lagipula, timeline siapa sih yang kita ikuti?
Perempuan sering dipaksa untuk hidup dalam “timeline sosial” yang kaku. Iya? Misalnya, usia 25 harus menikah, lalu 27 punya anak. Menginjak 30 sudah mapan secara ekonomi, dan usia 35 entah apa lagi. Terus begitu, tidak ada habisnya. Jika kita melenceng sedikit saja dari urutan ini, akan ada tatapan iba, pertanyaan basa-basi yang tajam, atau komentar-komentar kecil yang terasa seperti luka:
“kamu nggak takut kesepian?”
“kenapa resign, sayang banget padahal.”
“kasihan sekali kamu, belum ada pasangan.”
Semua seolah berlomba-lomba mengingatkan bahwa waktu kita tinggal sedikit. Bahwa perempuan punya “masa pakai.” Tapi pertanyaannya: timeline itu milik siapa? Dan untuk apa kita berlomba dalam lintasan yang tak kita pilih?
Aku tidak sedang menunda hidup. Justru aku sedang menjalaninya sepenuh hati. Dengan lebih pelan, lebih sadar, dan lebih jujur.
Kemerdekaan, dalam kasusku, adalah keberanian untuk tidak mengikuti suara paling nyaring di luar sana.
Ia adalah keputusan sadar untuk mempercayai proses, bukan hanya hasil. Untuk memeluk pertanyaan, bukan buru-buru mencari jawaban.
Seperti kata hadis riwayat Abu Nu’aim berikut:
“Barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya.”
Dan aku percaya, Tuhan tidak menyuruhku untuk tergesa. Aku percaya bahwa jalan setiap perempuan berbeda, dan tidak semua harus berujung pada pernikahan, anak, atau rumah bertingkat dua.
Dalam perspektif Islam yang adil gender, sebagaimana yang diperjuangkan oleh pemikiran Mubadalah, perempuan adalah subjek. Bukan sekadar objek keputusan. Artinya: kita punya otoritas atas hidup kita sendiri. Kita boleh bermimpi, memilih, dan menetapkan jalan. Bahkan jika jalan itu tampak sepi, bahkan jika banyak orang mempertanyakannya.
Aku tahu, laki-laki pun punya tantangan mereka sendiri, tidak ada jalan yang benar-benar mudah. Tapi sebagai perempuan, kita memikul beban yang sering kali tak terlihat: ekspektasi yang menekan dari segala arah, penilaian yang datang bahkan sebelum kita bicara, dan jam sosial yang terus berdetak di telinga. Tantangan ini unik, khas, nyata, meski kadang dianggap sepele.
Kemerdekaan bukan tentang hidup tanpa batas. Tapi tentang berdaulat atas pilihan, yang didasarkan pada nilai, kesadaran, dan keimanan.
Dan dari sanalah harga diri tumbuh.
Kedamaian yang kurasakan sekarang bukan karena semuanya sudah beres. Bukan. Justru banyak yang belum selesai. Aku masih menata kembali impian. Belum tahu arah karier berikutnya. Aku masih bertanya-tanya tentang cinta. Tapi aku tahu satu hal: aku tidak lagi terburu-buru.
Karena selama ini aku hidup dalam ketergesaan: ingin segera berhasil, segera menikah, segera membuat orang bangga. Tapi siapa yang benar-benar peduli ketika aku tergeletak lelah?
Sekarang aku memilih mencintai proses. Mencintai langkah kecil yang kuambil tiap hari. Mencintai versi diriku yang tidak sempurna, tapi jujur.
Jadi, aku ingin bilang pada diriku sendiri, dan juga kepada kalian semua (yang mungkin sedang berada di tempat yang sama. Kita tidak sedang salah sarah.
Mungkin dunia ingin kita bergerak lebih cepat. Tapi siapa bilang kita harus selalu lari?
Mungkin mereka menunggu kita menikah. Tapi siapa bilang perempuan hanya bisa bahagia jika punya pasangan?
Mungkin mereka menganggap kita gagal. Tapi siapa bilang keberhasilan harus selalu tampak di permukaan?
Kemerdekaan yang sejati adalah ketika kita bisa berkata:
“Aku mungkin belum sampai. Tapi aku tahu ke mana aku melangkah.” Dan itu cukup.
Aku menulis ini bukan karena aku sudah tahu semuanya. Tapi justru karena aku sedang belajar.
Menjelang usia 30, aku tidak ingin merayakan pencapaian materi atau relasi. Aku ingin merayakan keberanianku. Keberanian untuk meninggalkan yang tak lagi sesuai. keberanian untuk hidup di tengah ketidakpastian. Keberanian untuk menjadi perempuan merdeka, yang berdiri di atas keyakinannya sendiri.
Dan kalau itu terdengar sepi bagimu, ketahuilah: kita sedang menapaki jalan yang mungkin sunyi, tapi penuh cahaya.
Selamat merdeka, perempuan. Kita tidak terlambat. Kita sedang tumbuh, perlahan tapi pasti. Dan itu adalah bentuk cinta paling tinggi yang bisa kita beri pada diri sendiri. []