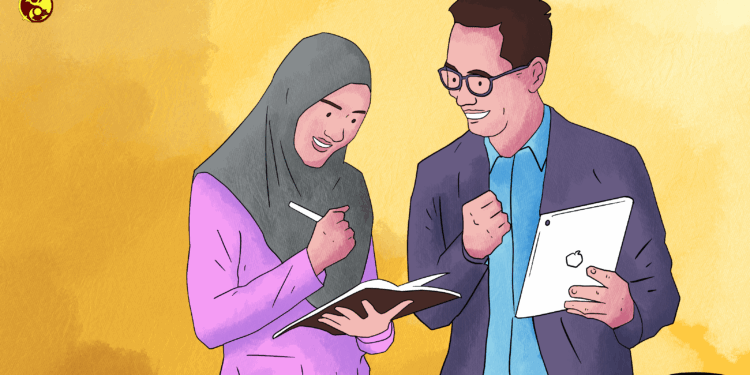Mubadalah.id – Ketika Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mempertanyakan apakah gaji guru dan dosen, yang diakuinya rendah, harus sepenuhnya menjadi tanggungan negara? Ataukah memerlukan partisipasi masyarakat? Ia mengungkit keresahan lama yang terkatup rapat dalam sanubari bangsa.
Pertanyaan yang terlontarkan oleh bendahara negara itu berangkat dari sebuah realitas yang tak terbantahkan. Keterbatasan anggaran negara. Dengan alokasi dana pendidikan yang telah menyentuh angka fantastis Rp 724,3 triliun, atau 20% dari total APBN 2025. masalah kesejahteraan guru dan dosen memang ironisnya masih menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung usai.
Data memaparkan sebuah realitas yang memilukan, di mana gaji pokok seorang dosen di perguruan tinggi negeri hanya sedikit di atas upah minimum regional. Sebuah angka yang setara dengan daya beli 143 kilogram beras. Tertinggal jauh di belakang negara-negara tetangga seperti Malaysia (3,41 kali), Vietnam (3,42 kali), dan Thailand (3, 41 kali). Sri Mulyani melihat ini sebagai sebuah “tantangan bagi keuangan negara”.
Dia menyoroti inefisiensi, menunjuk contoh sekolah yang menghabiskan dana BOS untuk mengecat pagar atau membeli kursi baru yang tidak perlu. Seolah-olah masalahnya terletak pada ketidakmampuan di level hilir untuk mengelola dana, bukan pada kebijakan di level hulu. Namun, argumen efisiensi ini terasa sumbang ketika kita letakkan di samping skala prioritas anggaran lainnya.
Paradoks Keterbatasan Anggaran
Ketika pemerintah menyajikan argumen keterbatasan anggaran, publik sontak menoleh pada kemewahan-kemewahan lain yang justru dibiayai tanpa banyak tanya. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) dengan tajam menyoroti ketimpangan skala prioritas ini. Alokasi anggaran sebesar Rp 32,85 triliun untuk sekolah kedinasan yang kontras dengan dana hanya Rp 7 triliun untuk membiayai seluruh mahasiswa di perguruan tinggi negeri.
Di saat yang sama, ribuan guru honorer masih menerima upah yang jauh di bawah standar kelayakan hidup. Maka, kita layak bertanya “Partisipasi pajak rakyat selama ini di kemanakan?”. Pernyataan Sri Mulyani, alih-alih terlihat sebagai ajakan untuk bergotong-royong, justru tampak seperti upaya negara untuk “melepas” tanggung jawab yang seharusnya menjadi tugas utamanya.
Wacana Sri Mulyani ini bukan hanya kekhilafan sesaat. Ini adalah bagian dari pola pikir beliau yang beberapa kali ia munculkan ke permukaan. Saya ingat ketika pada 2018 silam Sri Mulyani menyatakan bahwa tunjangan guru besar namun kualitas pendidikan belum meningkat, atau usulannya pada 2024 untuk mengkaji ulang mandatory spending 20% untuk pendidikan.
Pernyataan-pernyataan tersebut, meskipun tertolak oleh Komisi X DPR, terkesan memposisikan pendidikan dan kesejahteraan tendik sebagai “beban” yang harus kita efisienkan. Bukan sebagai “investasi” fundamental yang harus kita prioritaskan. Inilah yang memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk dari content creator Jerome Polin, yang menyuarakan kesedihan dan keheranannya.
Pernyataan yang Tidak Bermoral
Beberapa ekonom bahkan menyebut pernyataan Sri Mulyani itu sebagai pernyataan yang “tidak bermoral”, karena mengaburkan tanggung jawab negara sambil mengabaikan kontribusi pajak rakyat yang selama ini menjadi sumber utama APBN.
Bukankah pasal 31 UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa negaralah yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi? Pernyataan Sri Mulyani itu jelas telah mencederai amanat luhur ini. Ia mengaburkan batas antara kewajiban negara dengan partisipasi publik.
Partisipasi masyarakat dalam pendidikan tentu adalah hal yang mulia, namun ia seharusnya bersifat komplementer. Sebagai penguat, bukan sebagai pengganti dari kewajiban dasar negara. Apa yang Sri Mulyani lontarkan merupakan sebuah pertanda yang mengkhawatirkan tentang cara negara memandang masa depannya.
Apakah para guru dan dosen ini adalah aset paling vital untuk membangun peradaban, atau hanya sekadar beban fiskal yang perlu kita tekan? Jawaban atas pertanyaan inilah yang akan menentukan apakah visi Indonesia Emas 2045 kelak akan menjadi kenyataan, atau hanya slogan kosong di atas kertas. []