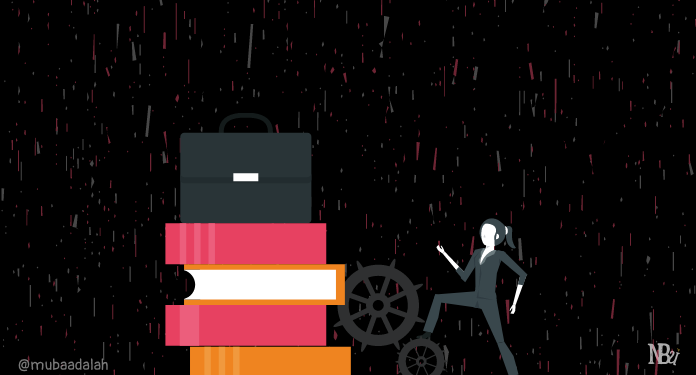Mubadalah.id – Perjuangan hak pilih perempuan di Inggris awal abad ke-20 merupakan salah satu bab terpenting dalam sejarah demokrasi modern. Periode ini memperlihatkan ketegangan antara dua arus besar dalam gerakan perempuan. Suffragist, yang berfokus pada jalur damai dan diplomasi, serta suffragette, yang memilih jalan radikal demi percepatan perubahan.
Emmeline Pankhurst, pendiri Women’s Social and Political Union (WSPU), tampil sebagai simbol keberanian sekaligus kontroversi. Militansi yang ia pilih menimbulkan tuduhan keras dari lawan-lawannya, termasuk tuduhan “blackmail politik.”
Suffragist, yang dipimpin oleh Millicent Garrett Fawcett melalui National Union of Women’s Suffrage Societies (NUWSS), menekankan jalur persuasi dan diplomasi. Mereka percaya bahwa kesetaraan politik dapat tercapai melalui lobi parlemen, pengumpulan tanda tangan, dan penyampaian argumentasi rasional. Strategi ini mencerminkan keyakinan pada nilai-nilai deliberasi dalam demokrasi. Perubahan tercapai lewat argumen yang meyakinkan, bukan tekanan atau kekerasan.
Namun, strategi ini berjalan sangat lambat. Petisi demi petisi mereka ajukan ke parlemen, tetapi hampir selalu terabaikan. Bahkan ketika perempuan kelas menengah mulai membentuk jaringan luas untuk mendukung gerakan, suara mereka tetap dipandang tidak signifikan oleh politisi laki-laki. Kekecewaan terhadap ketidakmampuan pendekatan damai untuk menghasilkan perubahan konkret melahirkan kerinduan akan metode yang lebih tegas.
“Deeds, not words”, Perbuatan, Bukan Kata-kata
Di sinilah Emmeline Pankhurst dan para suffragette mengambil peran penting. Pankhurst mendirikan WSPU pada 1903 dengan moto “Deeds, not words” — perbuatan, bukan kata-kata. Mereka menilai bahwa diplomasi tanpa tekanan hanyalah sia-sia. Karena itu, berbagai aksi radikal mereka lakukan: memecahkan kaca jendela kantor pemerintah, melakukan mogok makan di penjara, bahkan membakar kotak surat sebagai simbol perlawanan.
Langkah-langkah ini memang menimbulkan simpati sekaligus ketakutan. Media sering menggambarkan mereka sebagai perempuan yang “kehilangan kewarasan,” sementara kalangan konservatif menyebut aksi-aksi tersebut sebagai bentuk pemerasan politik. Istilah ini muncul karena militansi Pankhurst dianggap memaksa pemerintah membuat kebijakan bukan karena persetujuan rasional, tetapi karena ketakutan akan kerusakan lebih lanjut.
Namun, dari perspektif teori sosial, tuduhan itu perlu kita baca ulang. Perubahan sosial besar sering kali lahir bukan dari persuasi semata, melainkan dari ketegangan yang sengaja diciptakan oleh kelompok yang sebelumnya terabaikan.
Analisis Lewis Coser (1956) tentang teori konflik sosial memberikan kunci untuk memahami mengapa militansi Pankhurst dapat kita benarkan secara historis. Menurut Coser, konflik bukan sekadar gangguan dalam masyarakat, melainkan mekanisme penting untuk menghasilkan perubahan sosial. Ketika kelompok subordinat dikecualikan dari proses politik, konflik menjadi jalan untuk menuntut perhatian dan memaksa sistem beradaptasi.
Dalam kerangka ini, Pankhurst tidak semata-mata melakukan “pemerasan politik,” melainkan menyalurkan konflik yang laten menjadi nyata. Dengan kata lain, militansi suffragette menciptakan krisis yang membuat status quo tidak lagi dapat dipertahankan. Tuduhan blackmail sebenarnya mencerminkan ketakutan elite politik terhadap tekanan yang tak bisa lagi mereka abaikan.
Dilema Etis
Sejarah menunjukkan efektivitas strategi tersebut. Pada 1918, parlemen Inggris akhirnya mengesahkan Representation of the People Act, yang memberi hak pilih kepada perempuan di atas 30 tahun. Meski terbatas, ini merupakan tonggak penting yang tidak bisa dilepaskan dari tekanan gerakan suffragette. Tanpa militansi, kemungkinan besar hak politik perempuan akan tertunda lebih lama.
Pankhurst sendiri menuliskan pengalaman perjuangannya dalam otobiografi My Own Story (1914), di mana ia menegaskan bahwa militansi bukan pilihan pertama, melainkan jalan terakhir setelah segala bentuk diplomasi gagal.
Sejarawan Martin Pugh (2001) menekankan bahwa keberhasilan keluarga Pankhurst tidak bisa terlepaskan dari kombinasi strategi radikal dan dukungan moral dari kelompok lain. Sementara Sandra Holton (1996) menunjukkan bahwa kisah suffragette adalah bukti bagaimana perempuan mampu menggunakan konflik politik untuk meraih posisi yang lebih setara.
Tentu saja, pilihan Pankhurst tetap menghadirkan dilema etis. Ada korban sampingan dari aksi-aksi militan, baik dalam bentuk kerusakan properti maupun keresahan sosial. Tetapi, dalam bingkai teori konflik sosial, dilema ini dapat terpahami sebagai konsekuensi yang wajar ketika sistem politik menutup pintu bagi negosiasi damai. Konflik, meski destruktif di permukaan, memiliki fungsi konstruktif dalam jangka panjang: ia membuka ruang baru bagi inklusi politik.
Refleksi
Refleksi atas Pankhurst membawa kita pada pertanyaan penting di masa kini. Perempuan kini memang memiliki hak pilih di hampir semua negara, tetapi ketidaksetaraan gender belum sepenuhnya sirna. Representasi perempuan di parlemen masih rendah di banyak negara, kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan terus bertahan, dan diskriminasi struktural dalam dunia kerja maupun politik tetap nyata.
Apakah jalur diplomasi saja cukup untuk mengatasi persoalan tersebut? Atau adakah ruang bagi gerakan yang lebih tegas, bahkan konfrontatif, sebagaimana dilakukan Pankhurst seabad lalu? Jawabannya mungkin berbeda-beda, tetapi sejarah suffragette mengingatkan kita bahwa ketidakadilan sering kali membutuhkan suara keras untuk didengar.
Emmeline Pankhurst mungkin dipandang salah di mata hukum pada masanya, tetapi ia benar di mata sejarah. Tuduhan “blackmail politik” yang mengarah kepadanya tidak sepenuhnya salah, tetapi perlu kita pahami dalam konteks teori konflik sosial. Militansi Pankhurst menunjukkan bagaimana konflik bisa menjadi sarana efektif untuk menantang dominasi dan menciptakan perubahan.
Hak pilih perempuan di Inggris tidak lahir dari diplomasi lembut saja, melainkan dari keberanian sekelompok perempuan untuk memaksa sistem mendengar. Pesan Pankhurst tetap relevan hingga kini: keadilan tidak selalu datang dengan sendirinya, dan kadang kita membutuhkan keberanian untuk menimbulkan konflik demi memperjuangkan masa depan yang lebih setara. []