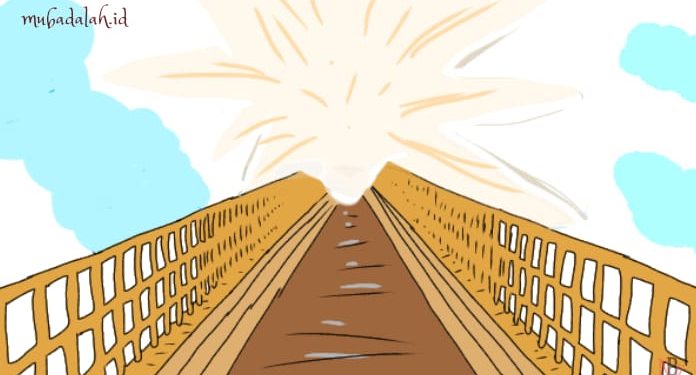Mubadalah.id – Drumas (20) selama lima belas tahun selalu melaksanakan salat Jumat di dalam masjid. Namun pada Jumat, empat Juni 2023, pengurus Masjid Al Muslimin Jakarta Selatan melarangnya masuk ke ruang utama masjid. Pengurus beralasan ingin menjaga kesucian masjid dari kemungkinan najis yang berasal dari kursi roda Drumas. Akibat larangan itu, Drumas dan ayahnya melaksanakan salat Jumat di pelataran masjid.
Peristiwa ini kemudian viral di TikTok dan memicu banyak komentar negatif dari warganet. Setelah penelusuran lebih lanjut, terungkap bahwa larangan itu muncul dari komentar jemaah. Ada jemaah yang mempertanyakan kebersihan roda dan kemungkinan adanya najis. Menanggapi pertanyaan itu, pengurus masjid mengubah kebijakan. Mereka awalnya memperbolehkan Drumas masuk ke ruang utama salat, kemudian membatasi aksesnya hanya sampai selasar masjid.
Masjid dan Pembatasan bagi Difabel
Fenomena pembatasan difabel, khususnya pada kasus Drumas memperlihatkan cara masyarakat memaknai tubuh difabel. Maftuhin dalam: Mengikat Makna Diskriminasi Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas (2016) menjelaskan bagaimana diskriminasi bekerja melalui bahasa dan definisi.
Maftuhin menunjukkan bahwa diskriminasi tidak selalu hadir dalam bentuk larangan kasar atau kekerasan terbuka. Diskriminasi sering muncul melalui cara masyarakat memberi nama dan makna pada seseorang. Ketika masyarakat menyebut seseorang “cacat”, “tidak normal”, atau “bermasalah”, masyarakat pada dasarnya sedang membangun jarak sosial. Bahasa membentuk cara pandang, dan cara pandang membentuk tindakan.
Dalam kasus Drumas, pengurus masjid tidak menyebut dirinya sebagai pelaku diskriminasi. Mereka menggunakan alasan menjaga kesucian masjid. Namun alasan itu berangkat dari asumsi bahwa kursi roda membawa potensi najis. Asumsi tersebut tidak netral, ia lahir dari cara masyarakat memandang tubuh difabel sebagai berbeda dan berisiko.
Maftuhin menjelaskan bahwa diskriminasi sering bekerja melalui proses pelabelan. Masyarakat menempelkan identitas tertentu pada tubuh difabel. Setelah itu, masyarakat menganggap pembatasan sebagai tindakan wajar. Dalam situasi ini, larangan masuk ruang utama masjid tampak seperti keputusan administratif biasa. Padahal keputusan itu membatasi hak seseorang untuk beribadah dengan setara.
Lebih jauh Maftuhin menekankan bahwa perubahan istilah dari “penyandang cacat” menjadi “difabel” atau “penyandang disabilitas” bukan sekadar soal bahasa. Perubahan istilah mencerminkan perubahan cara pandang. Ketika masyarakat tetap memelihara cara pandang lama, maka diskriminasi tetap terjadi meskipun istilah sudah berubah.
Kasus Drumas memperlihatkan bahwa masalah utama bukan hanya pada aturan masjid. Masalahnya terletak pada makna yang terlabeli pada tubuh difabel. Selama masyarakat masih melihat tubuh difabel sebagai ancaman terhadap norma kesucian, maka pembatasan akan terus muncul dalam berbagai bentuk.
Perspektif Sosial pada Disabilitas
Fenomena Drumas mempertegas inklusifitas rumah ibadah bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga perspektif. Aspek perspektif ini yang dikritik oleh disabilitas model sosial.
Model sosial tidak menempatkan masalah disabilitas pada tubuh difabel. Ia justru menempatkan masalah difabel ada pada lingkungan dan sistem sosial. Dengan kata lain, masyarakatlah yang menciptakan ketidakmampuan, bukan tubuh difabel.
Dalam kasus Drumas terlihat masalah utamanya ada pada perspektif dan cara berpikir pada disabilitas. Dalam pandangan non-difabel melihat kursi roda bukan sebagai alat bantu mobilitas, melainkan barang asing, di luar tubuh difabel.
Padahal, dalam pandangan difabel, banyak anggapan bahwa kursi roda adalah bagian dari tubuh mereka. Pandangan difabel ini menjelaskan kenapa difabel daksa tidak mau lepas dari kursi roda, karena tanpanya mereka “tidak berdaya”.
Cara Pandang terhadap Penyandang Difabel Perspektif Sosial
Cara pandang difabel kontras dengan orang-orang non-difabel yang menganggap kursi roda sebagai barang asing. Karena non-difabel pada kasus Drumas adalah pengelola, mereka punya kuasa, jadi mudah saja mengatur: boleh dan tidak. Sedangkan Drumas yang minoritas harus tunduk, karena ia minoritas, sekaligus tidak punya kuasa.
Cara pandang non-difabel, mayoritas-minoritas dan relasi kuasa, ini yang dikritik oleh model disabilitas sosial. Model ini tidak bertanya apa kekurangan Drumas, tapi bertanya hambatan apa yang masjid ciptakan pada Drumas. Ketika pengurus melarang akses ke ruang salat utama, mereka menciptakan hambatan sosial. Hambatan itu tidak berasal dari tubuh Drumas, tapi dari keputusan institusional.
Selain itu, model sosial menekankan bahwa ruang ibadah termasuk ruang publik sosial. Ruang publik harus melayani semua warga tanpa kecuali. Jika pengurus membatasi akses karena asumsi tertentu, maka mereka mengurangi partisipasi warga. Dalam konteks ini, pembatasan tersebut menjadi bentuk eksklusi sosial.
Lebih jauh lagi, model sosial mendorong perubahan pada sistem, bukan pada tubuh difabel. Karena pada dasarnya model sosial adalah kritik sosial atas eksklusi yang lahir dari tatanan sosial yang telah mapan. Tatanan sosial ini sering memarginalkan minoritas, dan solusinya adalah mendekonstruksi dan mengonstruksi ulang tatan sosial yang lebih inklusif.
Kasus Drumas juga memperlihatkan bagaimana opini mayoritas dapat membentuk kebijakan. Ketika beberapa jemaah menyampaikan kekhawatiran, pengurus segera menyesuaikan aturan. Mereka tidak menguji asumsi tersebut secara kritis, tidak mempertimbangkan dampaknya terhadap hak difabel. Dinamika ini menunjukkan bahwa tekanan sosial sering lebih kuat daripada prinsip inklusi.
Karena itu, perspektif sosial mengajak kita memindahkan fokus dari belas kasihan ke keadilan. Difabel tidak membutuhkan izin untuk hadir. Difabel memiliki hak yang sama untuk beribadah di ruang utama salat. Jika masyarakat ingin membangun rumah ibadah yang inklusif, masyarakat harus mengubah cara pandang dan cara mengatur ruang bersama. Dengan perubahan itu, inklusivitas tidak berhenti pada slogan, tetapi hadir dalam praktik nyata. []
*)Artikel ini merupakan hasil dari Mubadalah goes to Community Surakarta, kerjasama Media Mubadalah dengan UPT Perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta.