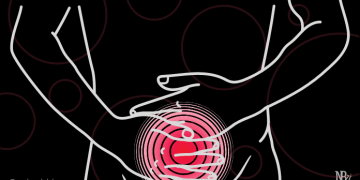Mubadalah.id – Tadarus Subuh ke-181 menghadirkan satu pertanyaan reflektif yang menggugah dari Arifah Millati, ulama perempuan muda dari UIN Tulungagung. Ia menyinggung pembedaan klasik dalam fiqh antara haid dan istihadah. Dalam haid, penetrasi seksual dilarang. Dalam istihadah, sekalipun darah tetap keluar, penetrasi dibolehkan secara fiqh.
Pertanyaannya sederhana tetapi tajam. Jika dalam istihadah tetap ada darah, sementara perempuan bisa merasakan nyeri dan berisiko mengalami infeksi, mengapa penetrasi dibolehkan? Apakah pertimbangan medis dan pengalaman tubuh perempuan pernah benar-benar menjadi bagian dari perumusan hukum, khususnya dalam fiqh menstruasi ini?
Pertanyaan ini membuka ruang yang lebih luas. Bagaimana fiqh menstruasi selama ini kita rumuskan?
Karakter Kitab Klasik
Kitab-kitab fiqh klasik sangat rinci membahas warna darah, tekstur, bau, durasi, dan perhitungan hari. Namun hampir semuanya tertulis oleh laki-laki yang tidak pernah mengalami menstruasi. Mereka mendeskripsikan tubuh perempuan dari luar, bukan dari pengalaman langsung. Lebih dari itu, rujukan mereka murni berbasis interpretasi normatif atas teks-teks para ulama pendahulu. Bukan pada kajian medis dan bukan pula pada pengalaman nyata para perempuan.
Padahal al-Qur’an dan Hadis sendiri tidak pernah merinci warna, jenis, atau durasi darah. Yang dibicarakan oleh kedua sumber ini adalah etika dan hukum ketika menstruasi terjadi, bukan anatomi dan klasifikasi biologisnya.
Al-Qur’an menyebut haid sebagai adha—sesuatu yang mengandung ketidaknyamanan—dan mengatur etika menjauhi hubungan seksual selama masa itu (QS. al-Baqarah: 222). Fokusnya adalah perlindungan dan kehati-hatian, bukan kategorisasi medis yang detail. Di sini terlihat bahwa teks wahyu berbicara pada level prinsip. Menjaga kenyamanan, menghindari mudarat, dan menghormati kondisi tubuh perempuan.
Namun dalam perkembangan fiqh, pembahasan menstruasi menjadi sangat teknis dan biologis, seakan-akan hukum bergantung sepenuhnya pada klasifikasi darah. Ironisnya, klasifikasi itu lahir tanpa partisipasi aktif perempuan sebagai subjek pengalaman. Padahal kita tahu, dalam adab berfatwa, pengalaman subjek yang terdampak oleh fatwa seharusnya tergali dan kita serap secara sungguh-sungguh.
Panggilan kepada Ulama KUPI
Karena itu, pertanyaan Arifah Millati seharusnya tidak berhenti sebagai pertanyaan di Tadarus Subuh semata. Ia adalah panggilan epistemologis sekaligus teologis, terutama kepada para ulama perempuan jaringan KUPI, termasuk dirinya sebagai alumni pengkaderan ulama perempuan Indonesia.
Sudah saatnya para ulama perempuan dalam jaringan KUPI—yang mengalami menstruasi secara nyata—mengambil peran utama dalam merumuskan ulang fiqh menstruasi. Bukan untuk menolak tradisi, tetapi untuk melanjutkan dan menyempurnakannya. Tradisi fiqh selalu berkembang melalui ijtihad, dan ijtihad menuntut dua hal. Pengalaman nyata dan ilmu pengetahuan yang sahih.
Bukankah Imam Syafi’i telah mengajarkan bahwa kita bisa menulis sendiri fiqh menstruasi atas dasar istiqra’ (riset lapangan), yakni dengan menanyakan kepada sejumlah perempuan tentang pengalaman menstruasi mereka?
Lalu mengapa para ulama sesudahnya tidak lagi melakukan hal serupa? Yang terjadi justru pengulangan dan pengutipan pendapat-pendapat terdahulu, yang seluruhnya ditulis oleh laki-laki yang tidak mengalami menstruasi. Pendapat laki-laki dijelaskan oleh laki-laki, berkembang di antara laki-laki, lalu mereka serahkan untuk dijalankan oleh perempuan.
Merujuk Ilmu Medis dan Pengalaman Perempuan
Hari ini, ilmu kedokteran telah berkembang pesat. Ginekologi menjelaskan siklus hormonal, endometriosis, infeksi, gangguan reproduksi, serta berbagai risiko kesehatan yang dapat timbul dari aktivitas seksual dalam kondisi tertentu. Mengabaikan ilmu medis dalam merumuskan fiqh menstruasi berarti memisahkan hukum dari realitas tubuh.
Fiqh tidak boleh berdiri di atas asumsi biologis yang tidak teruji. Ia harus berpijak pada maqasid syariah. Menjaga jiwa, menjaga kesehatan, dan menjaga martabat. Jika suatu praktik secara medis berpotensi membahayakan perempuan, maka pertimbangan tersebut harus menjadi bagian dari proses istinbath hukum.
Lebih dari itu, dalam kredo KUPI, pengalaman perempuan sendiri merupakan sumber pengetahuan. Rasa nyeri, kelelahan, ketidaknyamanan, dan risiko infeksi bukanlah detail kecil. Semua itu adalah bagian dari realitas yang tidak boleh terabaikan dalam perumusan fiqh. Ia menjadi sumber otoritatif untuk membantu menjelaskan makna-makna al-Qur’an, Hadis, serta ijtihad para ulama.
Karena itu, yang kita butuhkan adalah kolaborasi. Ulama perempuan dan dokter ginekolog duduk bersama. Pengalaman tubuh bertemu dengan ilmu medis. Prinsip maqasid bertemu dengan data klinis. Dari sinilah dapat lahir fiqh menstruasi yang lebih adil, lebih ilmiah, dan lebih rahmah—digalang oleh para ulama perempuan jaringan KUPI.
Posisi Strategis KUPI
Ini bukan sekadar isu perempuan, melainkan isu integritas metodologi fiqh. Jika fiqh ingin tetap relevan dan benar-benar menjadi rahmat, ia harus terbuka pada pengalaman subjek yang diatur serta pada perkembangan ilmu pengetahuan. Secara paradigmatik, teologis, dan metodologis, Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) memiliki modal kuat dalam hal ini, karena secara eksplisit mengakui pengalaman perempuan dan ilmu pengetahuan sebagai sumber otoritatif dalam perumusan hukum Islam.
KUPI juga memiliki posisi strategis untuk memulai langkah ini. Jaringan ulama perempuan yang luas, pengalaman advokasi yang panjang, serta komitmen pada keadilan hakiki adalah modal besar. Pertanyaannya kini bukan lagi “bolehkah kita merumuskan ulang?”, melainkan “kapan kita mulai?”
Fiqh menstruasi tidak boleh terus kita tulis dari jarak biologis. Ia harus lahir dari pengalaman nyata, tertopang oleh ilmu medis, dan diarahkan oleh maqasid syariah. Sebab tubuh perempuan bukan sekadar objek kajian. Ia adalah amanah yang harus kita pahami dari dalam.
Para ulama perempuan jaringan KUPI, mari segera memulai. []