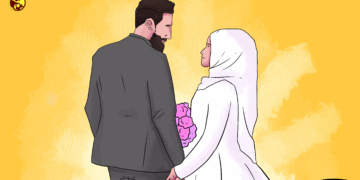Mubadalah.id – Satu hal, di Indonesia, yang acap menyumbang pembicaraan dari pelbagai sisi adalah konsep pernikahan. Ia laksana lapangan olahraga yang tribun memutarinya, ia dikepung di sana-sini. Frasa pernikahan dini, pernikahan beda agama, angka pernikahan turun, dan lainnya tak selesai-selesai menjadi perbincangan publik.
Jika seseorang belum menikah di usia ideal, misalnya, pasti omongan orang terus menghantui telinganya dengan beribu pertanyaan. Atau, Anda sudah menikah tapi masih belum menampakkan lelaku sebagaimana suami-istri, nyaris bakal jadi bahan komentar orang juga. Ragam-ragam kerumitan itulah yang membikin pernikaha menjadi unik, di samping terus terhimpit persoalan demi persoalan.
Atas lapik itulah (mungkin), Juli lalu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyigi angka pernikahan turun setiap tahun. Keterangan “setiap tahun” yang Menag Nasarudin maksud masih general, sehingga dengan berbaik hati saya bantu membatasainya, sesuai data BPS, dalam lima tahun terakhir (2020-2024). Dan, memang benar, terus menurun.
Rantai Persoalan
Pada dekade mutakhir, penurunan angka pernikahan bukanlah barang baru. Korea Selatan, misalnya, angka pernikahan di sepuluh tahun turun sebanyak 40 persen. Belum lagi di beberapa negara macam Jepang dan Cina yang lebih dulu terkenal akan persoalan ini. Lalu apa sebenarnya persoalan yang melatari mengapa angka pernikahan bisa turun?
Pelan-pelan kita akan membahasnya. Namun, dengan dasar penurunan angka ini Kementerian Agama RI konon menarget sampai dua juta pernikahan di tahun ini (2025). Rupa-rupa usaha tergelar, lewat nikah massal, contohnya. Saya pernah menulis di laman ini, mengenai pesimisme praktik nikah massal program Kemenag ini. Sebab, bagi saya, nikah massal bukan solusi tepat untuk memompa angka pernikahan. Ia justru serupa residu persoalan sebelumnya sekaligus pangkal persoalan berikutnya.
Dari metode penguraian persoalan di atas, kedapati siklus tak ajeg yang bakal terus berkelindan dalam pola-pola kebijakan serupa. Permasalahan akan stagnan di situ-situ saja. Tawaran jalan keluar di luar hal-hal instan—macam nikah massal—ini perlu dipikirkan. Saya memegang nasihat Dr. Sindhunata (Pemimpin Umum Majalah Basis) bahwa sesuatu yang instan tidak mungkin membuat perubahan yang nyata.
Rantai persoalan ini perlu mendapat perhatian lebih lewat pembedahan akar penyebabnya. Kita bisa melihat rincian kemelut persoalan pernikahan penyebab perceraian lewat salah satu indikator, di antaranya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa) menjabarkan data lima tahun terakhir (2020-2024) angka kekerasan meningkat dengan tempat kejadian rumah tangga memayoritas.
Statistik memang sebatas sekumpulan angka tetapi ia sedikitnya mewujud alasan dan bukti betapa tak sedikit persoalan pernikahan terjadi di tubuh masyarakat Indonesia. Barang kali indikator KDRT inilah yang menjadi satu di antara penyebab mengapa lima tahun terkahir angka pernikahan menurun.
Bagaimana tidak, pernikahan sebagai ikatan suci mesti dikotori dengan warna-warna kekerasan. Lewat gambaran ini—hipotesis sederhana—seseorang, perempuan khususnya, menjadi dua kali mikir dalam mengambil keputusan menikah.
Kualitas Pernikahan
Bukti empiris sudah nyata bahwa historis pernikahan yang terjadi melulu berisi kekerasan dan berujung menyisakan luka. Walhasil tak perlu heran bilamana hadir pernyataan junto pernyataan: “Untuk apa menikah bila hanya untuk jadi korban kekerasan?”.
Satu penyebab ini tentu mengubah paradigma masyarakat—utamanya perempuan—bagaimana mereka memaknai pernikahan. Daripada menikah sakit, lebih baik menundanya, atau tidak sama sekali, itu mungkin dumelan yang bakal kita dengar. Sejauh praktik-praktik kekerasan dalam rumah tangga terus terproduksi, sedalam itu pula angka-angka pernikahan semakin defisit.
Problem demikian yang mestinya Kementerian Agama melalui Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam sasar dalam menjangkau kualitas pernikahan yang ada. Ya, kualitas pernikahan, bukan kuantitas. Mengapa kita selalu terpikat-pana pada kuantitas? Apakah yang besar, banyak, dan naik itu selalu baik dan positif? Kan, tidak juga.
Kuantitas itu hanya soal dua arah. Naik-turun, besar-kecil, banyak-sedikit. Kurang cerdas rasa-rasanya, bila hari ini, apa-apa—apalagi kebijakan pemerintah—selalu kita nisbatkan pada hal berhubungan dengan kuantitatif, mengenyampingkan sesuatu yang krusial soal mutu. Membahas kualitas pernikahan itu lebih beradab alih-alih bertungkus lumus meribut-nargetkan soal kuantitas seperti yang Kementerian Agama RI lakukan.
Boleh jadi, sesuatu yang menurun itu teranggap buruk. Bagi saya, turunnya angka pernikahan teramini sebagai bentuk evaluasi cara masyarakat Indonesia menjalankan syariat agamanya sebagai warga negara. Akan sia-sia juga, umpamnya, angka pernikahan meningkat, tapi di sisi lain perceraian pun terus meningkat. Ini tak lebih dari istilah gali lubang tutup lubang.
Mari dengan bijak mengurai persoalan pernikahan ini dengan melihat lumbung dasarnya dulu. Kementerian Agama RI sebagai pihak yang berhak, yang kuasa, jangan sembrono junto gegabah tanpa pengkajian dan riset mendalam. Pertimbangan dari pelbagai faktor, sisi, dan ruang itu amat perlu. Karena pernikahan ini amat kompleks, perlu ada sikap realibilitas dalam menanggapinya. []