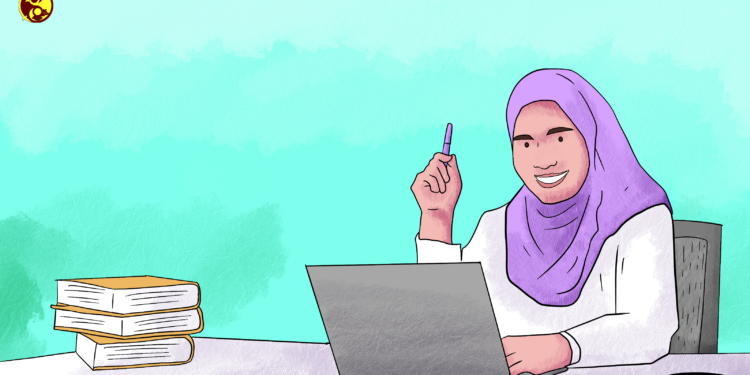“Girls, jangan pernah berhenti bekerja. Dunia nggak ramah sama perempuan yang gak punya power finansial. Berdiri di atas kaki sendiri itu bukan pilihan, tapi keharusan!”
Mubadalah.id – Kira-kira sederet kalimat itulah mutakhir berseliweran di jagat maya, sekaligus menjadi alasan saya menulis esai ini. Kutipan itu amat ramai dibagi-teruskan oleh warganet, terutama perempuan. Saya berusaha menelusur, siapa gerangan pembuat kutipan yang menyigi benang merah relasi antara “perempuan dan bekerja” ini.
Naga-naganya, si pembuat tulisan ialah akun Instagram bernama @abouthify (koreksi bila saya keliru). Akun berpengikut 1,2 juta itu, menulis frasa “Teman Sefrekuensimu.” di biodatanya. Postingannya berisi kalimat bernada curhat sekaligus penguat ihwal lelaku hidup; terutama bagi perempuan. Sebagian ada pula yang mengarah pada soal percintaan.
Kutipan tersebut, bagi saya—walau secara tata bahasa belum sempurna tapi—mengandung interpretasi mendalam. Di kalimat pertama saja seolah memberi pengertian bahwa bekerja adalah “hak” sesiapapun. Tak memandang jenis kelamin, agama, ras, dan suku.
Memang, di satu fase, bekerja (mempunyai pekerjaan) akan menjadi suatu kewajiban seseorang. Menjadi seorang kepala rumah tangga, misalnya, ia terkenai keharusan mencari nafkah lewat bekerja. Atau mereka yang masih sendiri, bekerja untuk menyiapkan masa depan. Bagi dirinya, pasangan, dan keluarganya kelak.
Sumbu Pemufakatan
Dalam kanon tadi, keharusan bekerja tersemat secara universal. Bingkai rumah tangga sedikitnya mencontohkan, umumnya (artinya tidak semua) kedua mempelai sebelum menikah memiliki pekerjaan. Lantas setelah menikah, salah satu berhenti bekerja (ini sering teralamatkan pada perempuan). Alasannya beragam; dilarang suami atau kemauan sendiri—suami tak melarang melain antara mereka membuat pemufakatan.
Alasan pertamalah yang menjadi sumbu polemik. Semacam ada pemotongan hak “kerja” perempuan. Apa karena telah berstatus istri, hak kerja perempuan lantas terkebiri? Kalau-kalau saja sang suami menarik alasan pada doktrin agama, maka ia, bagi saya, terlalu saklek menginterpretasikannya.
Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA. (Menteri Agama RI sekarang) membabarkan dalih dalam buku Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur’an (1999) mengenai persoalan ini. “Konsep kesetaraan jender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun urusan karier profesional, tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama meraih prestasi optimal.” tandasnya.
Suami (lelaki) tak seharusnya menjadikan perkawinan sebagai penebas hak istrinya (perempuan) untuk tetap bekerja. Ibarat ini, menurut Nasarudin, bentuk dari penindasan. Manakala kedapati sebuah pemahaman bersifat menindas atau menegasikan nilai luhur humanisme, maka ia sejatinya perdebatan terbuka untuknya.
Relasi Fluktuatif
Melihat keragaman dimensi keluarga yang fluktuatif, seorang istri mesti berlatih mandiri secara finansial maupun mental. Bukan maksud melangkahi rasa penghormatan dan kemampuan suami. Paling tidak, jika ia bekerja—walaupun bukan kewajiban—penghasilannya bisa untuk tabungan masa depan atau dana darurat.
Dalam kasus berbeda, penghasilan istri justru menolongnya bila suami (amit-amit) menelantarkannya. Tak ada sumbu harapan lebih dari suami durjana yang tega menelantarkan istri dan keluarganya selain mencari jalan mandiri demi kelanjutan hidup layak. Mulanya, tak salah jika istri bekerja dengan niatan apik; membantu menguatkan finansial keluarga.
Namun, pemutlakan bekerja tak berarti mengenyampingkan kewajibannya sebagai istri. Lagi-lagi saya teringat omongan seoranga dosen, Dr. Layyin Mahfiana, soal keberimbangan dirinya antara menjadi dosen, istri, dan ibu. “Saya ini seorang dosen, tapi saya juga seorang ibu,” ungkapnya. Ada pemufakatan seia sekata antara Bu Layyin dan suaminya dalam membangun rumah tangga.
Dalam pada itu, sikap hormat tak berlebihan saya berikan pada mereka (para suami) yang mengizinkan istrinya tetap bekerja. Andai kata mereka sudah mapan pun, bekerja tak melulu bertujuan menambah kekayaan semata. Ada tanggung jawab lain di luar finansial yang lewat bekerja bisa tertunaikan.
Rupanya kutipan di atas berusaha menyentil kita yang kerap melihat remeh persoalan bekerja. Apalagi bila mengaitkannya dengan persoalan jalan hidup hingga keluarga.
Jika normatif dan kolot memaknai doktrin agama, bekerja hanya termaknai dosa dan bentuk pembangkangan istri terhadap suami semata. Itu menutup kemungkinan bahwa niat mulia kerja muncul dari kesadaran dan hati nurani setiap insan. Demi penghidupan layak. Demi perwujudan misi. Dan demi menuju rida-Nya. Maka saya ucapkan. Girls, kalian jangan berhenti bekerja (dulu). []