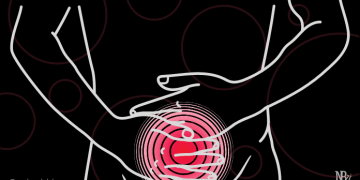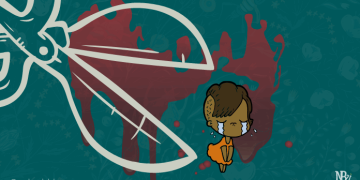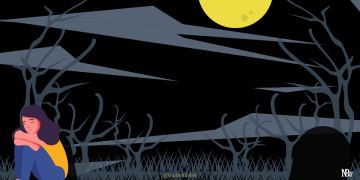Mubadalah.id – Gelombang demonstrasi yang terjadi pada penghujung Agustus 2025 seharusnya menjadi momentum bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memperlihatkan fungsinya sebagai wakil rakyat. Ribuan mahasiswa, buruh, dan elemen masyarakat sipil berkumpul di depan Gedung DPR RI untuk menyuarakan aspirasi.
Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Tidak ada satu pun pimpinan atau anggota DPR yang keluar menemui mereka. Ketua DPR, Puan Maharani, pun memilih diam ketika ditanya awak media soal ketidakhadiran wakil rakyat dalam menyapa demonstran.
Di titik ini, publik berhadapan dengan paradoks. Di satu sisi, Presiden Prabowo Subianto mendorong DPR untuk membuka ruang dialog dengan demonstran. Namun di sisi lain, lembaga legislatif justru memilih diam dan berlindung di balik pagar Senayan. Situasi ini menegaskan bahwa kita sedang menghadapi krisis representasi politik yang serius.
Untuk membaca fenomena ini, relevan kiranya menghadirkan teori demokrasi deliberatif yang dikembangkan oleh Jurgen Habermas. Dalam karya monumentalnya Between Facts and Norms (1996), Habermas menekankan bahwa legitimasi politik hanya akan lahir melalui komunikasi yang rasional, terbuka, dan partisipatif antara warga negara dengan penguasa. Demokrasi tidak semata-mata berhenti pada prosedur elektoral, tetapi harus hadir dalam bentuk ruang deliberasi, yaitu pertemuan gagasan dan aspirasi antara rakyat dengan wakilnya.
Komunikasi Politik
Dalam konteks Indonesia, DPR RI sejatinya tidak hanya berfungsi sebagai lembaga legislasi atau pengawas pemerintah, melainkan juga sebagai arena komunikasi politik. Gedung DPR bukan sekadar tempat merumuskan undang-undang, tetapi seharusnya menjadi simbol keterhubungan antara rakyat dan negara. Ketika fungsi itu absen, yang terjadi adalah pengosongan makna representasi.
Sikap diam DPR di tengah demonstrasi mencerminkan betapa komunikasi politik kita masih bersifat prosedural, bukan substansial. Alasan “belum ada surat resmi” jelas menunjukkan bahwa wakil rakyat lebih mementingakan tata cara formal dibanding kebutuhan riil rakyat yang mendesak. Padahal, demonstrasi itu sendiri merupakan wujud artikulasi politik yang sah dalam demokrasi.
Habermas menolak model demokrasi yang hanya menekankan prosedur tanpa substansi. Demokrasi, menurutnya, harus tertopang oleh diskursus publik yang rasional. Ketika DPR memilih diam, maka proses diskursus itu berhenti. Rakyat bicara di jalan, sedangkan wakil rakyat menutup pintu di Senayan. Kesenjangan komunikasi ini memperlebar jarak antara elite politik dan masyarakat akar rumput.
Lebih jauh, diamnya Puan Maharani mempertegas absen-nya komunikasi politik. Bukannya memberikan penjelasan argumentatif, ia justru menghindar dari pertanyaan publik. Dalam teori Habermas, tindakan semacam ini bisa terbaca sebagai kegagalan dalam membangun “ruang publik” yang sehat, tempat argumen teruji secara terbuka.
Legitimasi Parlemen
Krisis komunikasi politik ini berdampak langsung terhadap legitimasi parlemen. Menurut David Easton, legitimasi adalah keyakinan masyarakat bahwa lembaga politik memiliki hak untuk membuat keputusan yang mengikat. Ketika DPR tidak mau menemui rakyat, keyakinan itu kian rapuh. Akibatnya, kepercayaan publik tergerus, dan parlemen hanya kita pandang sebagai institusi formal tanpa substansi.
Situasi ini juga memperkuat fenomena delegative democracy (O’Donnell, 1994), yaitu demokrasi yang hanya berjalan saat rakyat memberi mandat lewat pemilu, tetapi setelah itu wakil rakyat merasa tidak lagi terikat untuk mendengar aspirasi. Demokrasi hanya hidup lima tahun sekali, pada saat pemilu, sementara di antara itu, rakyat kehilangan saluran komunikasi yang efektif dengan wakilnya.
Jika fenomena ini terus berulang, demokrasi Indonesia berisiko jatuh ke dalam formalisme belaka. Artinya, prosedur pemilu tetap berjalan, tetapi substansi demokrasi, yakni partisipasi, komunikasi, dan deliberasi, tidak hadir. Pada akhirnya, rakyat akan semakin apatis terhadap institusi politik, dan jurang antara elite dan akar rumput makin melebar.
Demonstrasi Adalah Suara Rakyat
Opini publik seharusnya menjadi peringatan bagi DPR bahwa demokrasi tidak bisa mereka pertahankan hanya dengan aturan dan pagar tinggi. Demokrasi harus kita hidupkan melalui keberanian untuk mendengar, berdialog, dan membuka ruang deliberasi dengan masyarakat. Seperti Habermas tegaskan, legitimasi politik lahir dari proses komunikasi yang sehat, bukan dari sekadar prosedur formal.
Kehadiran DPR di tengah rakyat bukanlah pilihan, melainkan kewajiban. Demonstrasi adalah suara rakyat yang sah, bukan gangguan. Dengan menolak menemui rakyat, DPR justru mengkhianati fungsi representatifnya.
Kasus DPR yang memilih diam di tengah demonstrasi adalah cermin bahwa demokrasi deliberatif kita masih absen. Habermas sudah mengingatkan, tanpa komunikasi publik yang terbuka, demokrasi hanya akan menjadi prosedur kosong.
Jika DPR tidak segera mengembalikan fungsinya sebagai forum deliberasi, maka krisis representasi politik akan semakin dalam. Pada akhirnya, demokrasi Indonesia akan kehilangan makna substantifnya, dan rakyat hanya akan melihat Senayan sebagai gedung megah yang jauh dari kehidupan mereka. []