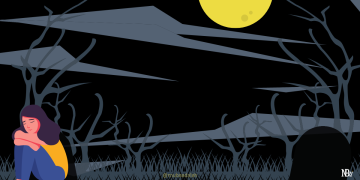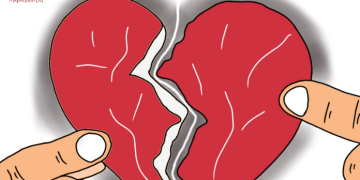“……Agama Islam yang sekarang kita pegang teguh, harus kita pelajari lebih dalam lagi. Sebab di luaran sana banyak sekali kelompok yang bersimbol Islam tapi berlainan dengan Islam yang kita pelajari selama ini…”
Mubadalah.id – Demikianlah, sekelumit kata dari pembina upacara dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 kemarin. Nampaknya, beliau memprihatinkan akan gerakan-gerakan yang bersimbolkan Islam. Namun apa yang mereka lakukan sangat berlainan dengan isi dari ajaran Islam itu sendiri.
Jika kita amati, dalam perjalanan sejarah Indonesia, agama memiliki peran yang sangat krusial dalam memperjuangkan hari kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sebut saja, gerakan Islam dalam Resolusi Jihad yang tercetuskan oleh KH Hasyim Asy’ari. Ia telah berhasil menggerakkan masyarakat dan santri untuk mengusir para penjajah. Resolusi itu, menegaskan bahwa membela Tanah Air untuk tidak dijajah kembali oleh Belanda dan sekutunya adalah wajib hukumnya bagi setiap individu muslim (fardhu ain).
Namun di sisi lain, banyak sekali kronik kekerasan di negara kita yang justru lahir dari sebuah paham agama. Selain yang telah saya sebutkan di muka, barangkali belum hilang dari memori kita akan tragedi ledakan di Bali yang telah merenggut 180 lebih nyawa manusia, atau insiden pembubaran rumah ibadah di Sukabumi dan Riau pada bulan lalu.
Intoleransi dan Diskriminasi
Setara Institute dalam laporanya membeberkan fakta, bahwa pada tahun 2024 terdapat sejumlah 260 tindakan intoleransi dan diskriminasi terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Data tersebut mengalami kenaikan yang pada tahun 2023 hanya terdapat 216 pelanggaran.
Hal demikian, menandakan bahwa gerakan agama di negeri kita memiliki sisi paradoksal. Satu sisi perdamaian dan solidaritas sosial adalah cita-cita utamanya. Namun faktanya, tidak jarang kita temukan kekerasan yang terjadi justru muncul dari beberapa gerakannya.
Sehingga, persoalan demikian sangat membutuhkan peran aktif dari kita. Selain itu juga pemerintah untuk memutuskan sebuah hukum yang final dan mengikat, agar tidak lagi terjadi kekerasan yang berbasis agama. Di mana dalam legal theory Islam (ushul fiqh) tersebutkan, “hukmul hakim yarfa’u al-khilaf, sebuah keputusan pemerintah dapat mengangkat dan mengikat semua perbedaan.
Karena di sisi lain, negara hukum Indonesia menganut aliran positivisme yuridis, yang menyatakan bahwa sesuatu yang dapat kita terima sebagai kebenaran hukum adalah apa yang telah ditentukan secara positif oleh negara (Wahid, 2014).
Langkah pemerintah yang sedemikian juga bersandar pada legal maxims Islam yang mengatakan: “adh-dhararu yuzalu”, segala bentuk kerusakan harus segera kita hilangkan.
Sebab, meskipun, alam demokrasi kita telah memberikan ruang pada semua ekspresi keagamaan, namun negara Indonesia –dalam umurnya yang sudah menginjak delapan puluh tahun ini, juga harus bersih dari ekspresi keagamaan yang cepat atau lambat bisa mengancam demokrasi kita.
Selain itu ekspresi keagamaan yang memaksakan kebenarannya kepada pihak lain adalah musuh demokrasi itu sendiri. Apalagi ia berpotensi menjatuhkan banyak korban dengan sebuah luka, yang sama sekali tidak mencerminkan cita-cita agama. Yakni untuk menghadirkan perdamaian dan menolak segala bentuk kerusakan.
Mengingat Kembali Konsep Ukhuwah
Maka, menjadi sangat penting bagi kita untuk mengingat kembali konsep ukhuwah (persaudaraan) yang diusung oleh KH Ahmad Shiddiq. Beliau adalah sosok intelektual muslim kelahiran Jember, untuk mengawal hari kemerdekaan yang damai tanpa kekerasan berbasis agama.
Konsep dari KH Ahmad Shiddiq pada dasarnya manusia adalah saudara bagi manusia lainnya. Beliau memberikan tiga klasifikasi mengenai konsep persaudaraan ini: Pertama, persaudaraan yang berbasis kemanusiaan (ukhuwah basyariyah), yang memberikan paham bahwa manusia berasal dari negara, agama, atau golongan manapun adalah saudara.
Kedua, persaudaraan yang berdasar kebangsaan (ukhuwah wathaniyyah), yang berarti atas dasar satu bangsa dan satu negara, kita semua adalah saudara. Ketiga, persaudaraan Islam (ukhuwah islamiyyah), yang harus menjadi instrumen bersatunya umat muslim dari golongan manapun.
Andai saja kita mengerti bahwa kita dan mereka adalah saudara, maka segala bentuk militansi agama itu tidak akan terjadi, atau setidaknya bisa untuk kita bendung.
Selain itu, terdapat banyak motif yang menjadikan agama tidak lagi menampilkan wajahnya yang humanis, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan menjadi perekat perpecahan primordial. Satu di antaranya adalah motif politik.
Kelompok Keagamaan di Indonesia
Kesaksian al-Asymawi, salah satu sosok intelektual Mesir dalam karyanya, Al-Islam al-Siyasi (Islam Politik), yang dikutip oleh Mun’im A Sirry. Beliau adalah sosok intelektual muslim Indonesia, dalam bukunya yang berjudul Membendung Militansi Agama (2003), ia menyampaikan:
“Islam sesungguhnya diturunkan sebagai Agama, namun sebagian umat muslim menyeretnya ke ranah politik. Dari sini, Islam justru menjadi variabel pembeda dan tak jarang mendorong atas terjadinya konflik.”
Tentu saja, hal serupa bukan persoalan Islam semata. Sebut saja, kelompok Protestan Evangelical di Amerika Serikat yang memiliki orientasi politik yang cukup kuat. Kelompok tersebut -pada masanya- juga aktif menyebarkan fitnah dan kebencian terhadap kaum muslim.
Namun demikian, yang lebih mengagumkan lagi mereka mendapat penolakan keras dari kelompoknya sendiri. Sehingga, masjid-masjid dan pusat-pusat Islam di sana mendapat penjagaan dan terproteksi oleh orang-orang non-muslim (Sirry, 2003).
Hal itu, menjadi cerminan kita akan terjadinya banyak kekerasan di Indonesia, yang lahir dari sebuah paham agama. Dalam artian, tidak seyogianya kekerasan dalam bentuk apapun itu terjadi, namun sebaliknya perdamaian yang menjadi visi utama dari berbagai gerakan spiritual harus terus kita kampanyekan.
Di samping itu, dari apa yang telah al-Asymawi sampaikan, sulit bagi kita untuk menafikan tidak adanya hasrat duniawi. Termasuk kepentingan pribadi dalam ruang politik di dada sejumlah kelompok keagamaan di Indonesia.
Atas Nama Kemerdekaan, Tidak Ada Lagi Kekerasan Berbasis Agama
Menjelang kemerdekaanya di tahun 1945, isu relasi Agama dan Negara menjadi pokok pembahasan para the founding fathers negara Indonesia. Masing-masing mengutarakan pendapatnya dengan segenap argumentasinya. Pada akhirnya perdebatan itu menemui titik kompromi, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusinya.
Pancasila sebagai dasar negara telah merepentasikan bahwa Indonesia bukanlah negara teokrasi, dan bukan pula sebagai negara yang sekuler. Namun demikian, negara Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai agama, hal ini tercermin pada Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Agama sebagai landasan moral, etis, bagi bangunan sosial, ekonomi, dan politik negara-bangsa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial (Muhammad, 2024).
Pancasila dan UUD 1945 telah menjadi titik temu kehendak dari berbagai agama dan kelompok lainnya yang sudah lama hadir di wilayah republik ini, sebelum menjadi merdeka. Bahkan mereka bersatu bersama untuk maju melawan dan mengusir penjajah demi kemerdekaan Indonesia.
Sehingga, atas nama kemerdekaan Indonesia yang ke delapan puluh ini, segala jenis kekerasan berbasis agama harus kita hilangkan dan kita bendung dengan sekuat tenaga. Sebab ia, di samping tidak selaras dengan nilai-nilai agama, juga telah mengabaikan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh negara Indonesia. []