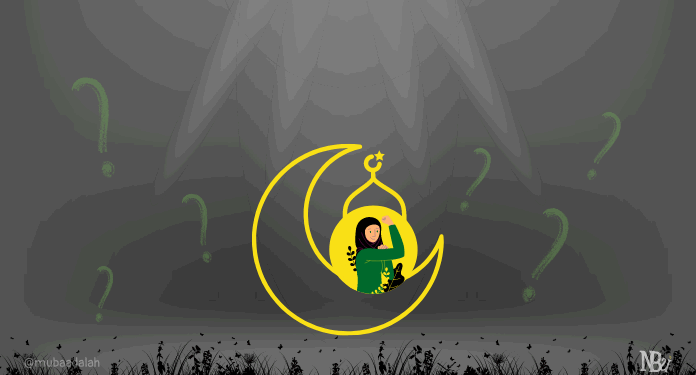Mubadalah.id – Di era kontemporer ini, kritik tajam mengenai pembatasan kesaksian perempuan banyak terlontar. Salah satu ulama yang melakukan kritik tajam adalah Syaikh Muhammad al-Ghazali, pemikir kontemporer asal Mesir.
Syaikh al-Ghazali menyayangkan timbulnya penyimpangan dalam pemikiran Muslim yang menjauhkan perempuan dari kesempatan memberikan kesaksiannya dalam berbagai bidang peradilan yang sangat transparan, yakni dalam qishash dan tindak pidana, serta hal-hal yang bersangkutan dengan nyawa dan kehormatan manusia.
Sebagai argumennya, ia mengemukakan beberapa pertanyaan retoris. Ia mempertanyakan, jika pencuri dapat memasuki rumah-rumah pada siang dan malam hari, apa artinya menolak kesaksian perempuan dalam soal pencurian?
Dan jika pelanggaran terhadap jiwa dan tubuh salah seorang anggota keluarga terjadi seperti pembunuhan dan perkosaan. Sementara yang ada saat itu seorang perempuan, apa artinya menolak kesaksian dalam hal ini?
Menyitir pendapat Ibnu Hazm, Syaikh Muhammad Al-Ghazali berpendapat bahwa penolakan terhadap kesaksian perempuan dalam masalah pidana dan qishash sama sekali tidak mempunyai dasar dalam sunnah nabawiyah.
Ia, lebih lanjut mengatakan, tidak ingin melemahkan Islam di hadapan hukum internasional dengan suatu sikap yang tidak berdasarkan nash-nash yang kuat hanya karena berpegang pada nash-nash yang putus. Sangat tidak tepat jika kehormatan diri limaratus juta perempuan muslimah dilemparkan begitu saja demi mengikuti persepsi seseorang.
Demikian juga bukan sebuah kemaslahatan, menggugurkan kesaksian perempuan dalam ribuan peristiwa yang justru berlangsung di hadapan mata mereka. Bukan pula sebuah kemaslahatan, memprioritaskan pendapat suatu mazhab yang lebih banyak merugikan Islam daripada menguntungkannya. Demikianlah kritik kesaksian perempuan yang Syaikh Muhammad al-Ghazali sampaikan.
3 Kesimpulan
Melihat perkembangan pemikiran di seputar fiqh kesaksian dari yang paling menafikan perempuan sampai yang memberikan hak yang sama untuk perempuan sebagaimana di atas, dapat kita sampaikan hal-hal sebagai berikut:
Pertama, fiqh kesaksian yang sangat membatasi hak perempuan pada dasarnya dibangun bukan di atas landasan dalil yang punya kekuatan pasti melainkan lebih pada asumsi-asumsi yang apriori tentang perempuan.
Buktinya, di kalangan ahli fiqh sendiri ada yang menolak sama sekali pembatasan-pembatasan seperti itu. Hal ini karena tidak adanya argumen teologis yang cukup kuat.
Kedua, pembatasan hak kesaksian perempuan ternyata menimbulkan masalah hukum yang jauh lebih substansial. Yakni tidak tercapainya keadilan yang merupakan tujuan hukum itu sendiri.
Dalam sebuah kasus di mana perempuan adalah saksi kunci dan keadilan tidak bisa ditegakkan kecuali dengan kesaksiannya, membatasi ruang kesaksian perempuan adalah menzalimi orang yang menjadi korban.
Lebih dari itu dengan dibatasinya ruang kesaksian perempuan peluang melakukan tindak pidana dan berbuat kriminal terhadap dan atau di hadapan perempuan. Maka semakin terbuka karena pelaku kejahatan tahu perempuan tidak punya hak untuk bersaksi.
Ketiga, saat ini pengadilan yang berlaku di negeri-negeri Muslim menerima kesaksian perempuan dalam berbagai perkara, termasuk perkara pidana dan kriminal. Masyarakat muslimpun tidak menolak fakta itu. Ini semua menunjukkan bahwa fiqh kesaksian yang diskriminatif terhadap perempuan dengan sendirinya telah tertolak oleh zaman.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, demi terciptanya keadilan hukum dan sosial, fiqh kesaksian tidak bisa lagi dibangun atas dasar asumsi-asumsi yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan tuntutan penegakan hukum yang adil buat si korban.
Melihat fakta dan realitas sosial yang ada fiqh kesaksian. Maka sesungguhnya tidak bisa lagi menolak hadirnya perempuan untuk bersaksi dalam seluruh bidang kesaksian. []