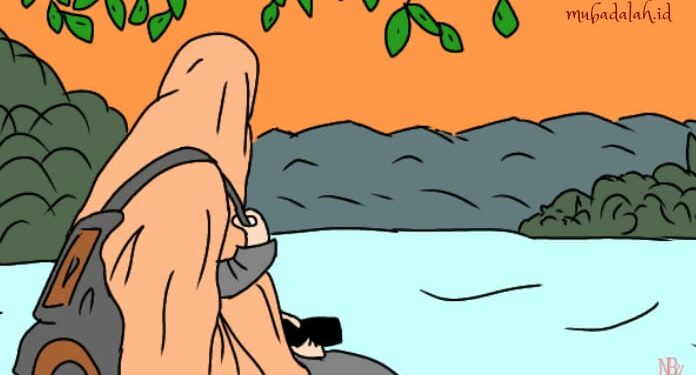Mubadalah.id – Suatu hari sepulang bermain anakku mengadu dengan mata berair,
“Bu, tadi aku dikata-katain sama temen aku. Katanya ibu tuh pernah sinting. Jadi, aku anak orang sinting !?”
Deg, darahku seperti mendidih mendengar kalimat skizo itu sinting. Tapi segera saja aku ambil napas dalam-dalam, berusaha meredakan amarahku dan otakku langsung mencari susunan kalimat yang cocok untuk menjelaskan hal ini pada anakku.
Aku meletakkan kedua tanganku di pundak anak berusia 8 tahun itu, dan mulai berkata perlahan,
“Sayang, kamu kesel ya? Hmm…, jadi gini, ibu memang pernah sakit, dan banyak orang yang menyebutnya ‘gila’ karena waktu itu perilaku ibu seperti orang gila. Nama penyakitnya ski-zo-fre-nia.”
Ekspresi anakku mulai berubah, mengernyitkan kening, berusaha mencerna kata-kata yang baru didengarnya dan mencoba mengejanya perlahan,
“Ski-zo-fre-nia? Apa itu?”.
Misi pertamaku berhasil, anakku mulai terlihat lebih tenang.
“Gini, kamu pernah pakai komputer atau laptop ibu kan?”
Dia mengangguk, aku melanjutkan,
“Nah, pernah nggak sewaktu kamu pakai, terus laptopnya loading lamaaa sekali, atau terlihat kacau, gak berfungsi, bahkan mati sendiri?”
Dia mengangguk lagi,
“Iya, pernah, bu”.
“Nah, otak kita yang di dalam kepala kita ini, cara kerjanya mirip dengan komputer, di dalamnya banyak kabel-kabel, kalau di dalam otak namanya syaraf. Terkadang terjadi kerusakan di dalam mesin atau kabelnya sehingga terjadi konslet atau kekacauan. Bisa jadi karena komputernya dipakai terus-menerus, jarang dimatikan, jadi mesinnya terlalu panas. Otak kita pun sama, bisa jadi syarafnya atau ‘kabelnya’ terganggu atau konslet, mungkin karena kurang istirahat, ketumpahan air, dan banyak sebab lainnya.”
Skizo bukan Gila
Anakku mengangguk-angguk dan tampak mulai berpikir,
“Jadi ibu nggak gila kan? Tapi kenapa orang-orang bilang ibu pernah gila?”.
Aku tersenyum kecut, membayangkan apa yang ada di pikiran orang-orang.
“Ibu dan orang-orang gila di luar sana, yang sering kita lihat berkeliaran di jalan itu tidak gila, nak. Ibu cuma sakit, mereka juga sakit. Makanya setelah ibu berobat ke dokter dan minum obat, ibu sembuh kan?”
Anakku mengangguk paham, matanya sekarang sudah berbinar kembali.
“Jadi, mereka itu orang sakit, ya, bu? Bukan orang gila?”
Aku menimpali, “Ya, mereka sakit, dan akan sembuh jika dibawa ke dokter dan diobati.”
Sejak saat itu, anakku tidak lagi menyebut orang-orang di jalanan itu dengan sebutan “orang gila”. Ketika kami di jalan dan melihat ada orang yang bertingkah laku aneh dan tidak terurus di pinggir jalan, anakku tidak lagi menunjukkan rasa takut atau jijik, melainkan empati,
“Bu, kasihan ya itu orang sakit.”
Pun ketika hari itu dia pulang dari bermain, dengan terengah-engah karena berlarian, dia bercerita,
“Bu, tadi pas temanku ngata-ngatain ibu lagi, aku bilang kalo ibuku nggak sinting, ibuku sakit, namanya ski-zo-fre-nia! Betul, kan Bu…” katanya dengan bangga.
Aku terharu mendengarnya. “Bagus, nak ! Kamu hebat bisa bilang begitu sama temanmu.”
Stigma pada Skizo
Namun beberapa minggu kemudian anakku kembali bercerita bahwa kata orang tua temannya yang ustadzah, aku mengalami sakit mental seperti itu karena kurang dzikir.
“Emang iya bu, itu gara-gara kurang dzikir?”
Meski kali ini tidak dengan mengeluarkan air mata, tetap saja aku merasa kesal, kenapa harus anakku yang turut menanggung stigma ini? Kenapa orang-orang tidak langsung saja berhadapan denganku, heh!?
“Nak, dzikir itu kan mengingat Allah. Jadi yang paling tahu siapa yang cukup dzikirnya dan siapa yang kurang dzikirnya itu ya hanya gusti Allah. Kita manusia tidak pernah tahu apa yang ada di hati manusia lainnya dan tidak tahu persis bagaimana amalan orang lain. Jadi, kita tidak berhak untuk menilai orang lain apakah kurang dzikir atau kurang bersyukur dan sebagainya. Itu namanya sama saja sok-sokan jadi Tuhan!”
Kali ini aku tidak bisa menyembunyikan rasa kesalku. Ini sudah kedua kalinya dan ini tidak bisa dibiarkan!
Hari itu aku menuliskan pengalamanku beberapa tahun yang lalu, ketika aku terkena skizofrenia. Aku menceritakan apa yang aku alami, bagaimana rasanya ketika dihujani firasat aneh, bagaimana rasanya mendengar bisikan-bisikan yang teramat jelas, penglihatan yang aneh, juga penciuman yang berbeda dari biasanya.
Aku juga menceritakan bagaimana bisikan-bisikan itu mengambil alih alam sadarku, menginstruksikan tubuhku untuk melakukan sesuatu yang di luar nalar, dan bagaimana diriku yang asli terpenjara, pasif, tak mampu melakukan apa-apa. Sesuatu itu, tokoh-tokoh halusinasi itu telah mengambil alih kontrol atas tubuhku! Orang menyebutnya : kesurupan.
Speak Up
Tulisan itu ku-upload di akun media sosialku sebanyak tiga kali unggahan. Dan betapa terharunya aku ketika tulisan itu menarik simpati banyak orang dan justru banyak yang bertanya tentang penyakit skizofrenia dikarenakan sebagian dia antara pembaca ada yang sedang menjadi caregiver. Bahkan beberapa penyintas pun membuka obrolan di ruang pribadi, mencari cara agar bisa sembuh dari penyakit yang menakutkan ini.
Suatu hari salah seorang temanku yang penulis menghubungiku, meminta waktu untuk berbincang dan meminta kesediaanku untuk menjadi salah satu narasumber. Dia sedang menulis sebuah novel yang bertema skizofrenia. Tentu saja aku bersedia.
Buatku speak up adalah hal terbaik dan terberani yang pernah aku lakukan sejak kesembuhanku tahun lalu. Orang-orang harus tahu, apa itu skizofrenia, bipolar, dan penyakit mental lainnya, sehingga stigma negatif yang melekat pada pasien dan penyintas bisa terhapus.
Dan, orang-orang pun harus tahu, apa yang harus dilakukan ketika diri atau keluarganya atau temannya mengalami penyakit ini. Orang-orang pun harus tahu bahwa sakit mental itu sama seperti penyakit fisik lainnya, bisa sembuh jika diobati.
Akhirnya aku patut bersyukur pada-Nya, berbangga pada diri sendiri, juga berterimakasih kepada semua orang yang telah mendukungku. Aku kembali pulih, bahkan aku merasa menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Jika masih ada yang mengatakan aku gila, aku jawab saja,
“Nah, gilanya saja kayak gini : bisa mengajar, bisa berkarya, bisa bekerja, … Apalagi warasnya !? Hahaha!” []