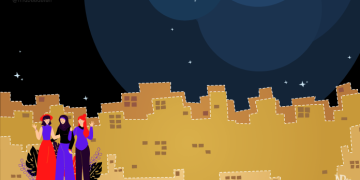Mubadalah.id – Krisis ekologi yang bermunculan di media massa dan disaksikan oleh masyarakat luas. Tidak hanya mempermasalahkan secara teknis seperti eksploitasi sumber daya alam, melainkan menyentuh pada urusan persoalan filosofis, etis hingga politik.
Model relasi dominan antara manusia dan non manusia selama berabad-abad terbentuk oleh paradigma antroposentrisme. Dalam bukunya Eileen Crist, Abundant Earth: Toward an Ecological Civilization (2019) cara pandang yang menempatkan manusia sebagai pusat dan penguasa atas alam. Meskipun konsekuensinya, alam hanya kita anggap sebagai objek eksploitasi, bukan entitas dengan nilai intrinsik.
Kajian politik dan etika lingkungan hadir sebagai wacana tandingan, yang mana relasi manusia dan non manusia terlihat sebagai hubungan timbal balik yang tak dapat terpisahkan.
Oleh karena itu, yang menjadi kegelisahan penulis hingga menerka-nerka fenomena ketimpangan alam dan kekacauan ekosistem. Apakah non-manusia (hewan maupun tumbuhan) mempunyai hak? Apakah etika juga harus melampaui kepentingan manusia? Bagaimana posisi lingkungan dapat memfasilitasi relasi antara manusia dan non-manusia?
Manusia dan Non-Manusia: Dari Antroposentrisme ke Ekosentrisme
Beberapa kajian akademik, terutama pendekatan western secara umum tradisi modern Barat menempatkan manusia dan non-manusia terbentuk oleh warisan filsafat Cartesian. Yakni dengan memisahkan subjek (manusia) dan objek (alam).
Dalam bukunya Arne Naess, Ecology, Community, and Lifestyle (1989), memaparkan bahwa pandangan René Descartes menempatkan alam sebagai “mesin” yang dapat termodifikasi bahkan termanipulasi sesuai dengan kebutuhan manusia. Sehingga paradigma ini melahirkan antroposentrisme, yang mana nilai moral hanya berlaku untuk manusia.
Sebagai respon, gagasan Arne Naess melalui gerakan deep ecology menekankan ekosentrisme, berpandangan bahwa semua makhluk hidup memiliki nilai intrinsik dan berhak hidup terlepas dari manfaatnya bagi manusia. Dalam kerangka inilah, hutan, sungai hingga spesies non-manusia bukan sekadar “sumber daya,” melainkan bagian dari komunitas ekologis yang setara. (Naess, 1989).
Filsuf lingkungan, Aldo Leopold dalam bukunya A Sand County Almananc and Sketches Here and There, mengusulkan land ethic. Yakni menempatkan prinsip manusia merupakan bagian dari komunitas tanah (land community) mencakup tanah, air, tumbuhan dan hewan. Dalam pandangannya Leopold, tindakan manusia dianggap benar jika ia menjaga integritas, stabilitas, dan keindahan komunitas ekologis (Leopold, 1949).
Politik dan Etika Lingkungan: Relasi Manusia-Non Manusia
Jika etika lingkungan membahas mengenai paradigma moral, maka politik lingkungan berupaya membahas paradigma representasi. Tentu menjadi pertanyaan penulis atau bisa jadi kita semua, dapatkah non-manusia terbahas dan direpresentasikan dalam wacana politik atau dalam kajian etika lingkungan?
Bruno Latour, dalam bukunya Politics of Nature: How to Bring The Sciences into Democracy (2004), menggagas konsep parliament of thing, menempatkan ide tentang parlemen ekologis di mana bukan hanya menyoal manusia, melainkan non manusia, mendapatkan ruang representasi. Meski non manusia tidak hanya bicara dalam bahasa manusia, melainkan hadir melalui ilmuwan, aktivis, dan masyarakat adat yang menyuarakan kepentingan ekologis mereka.
Kasus politik iklim global menunjukkan bagaimana “aktor non manusia” seperti emisi karbon, lapisan ozon, atau spesies terancam punah, masuk dalam arena perundingan internasional. Dalam persepktif ini, politik tidak serta merta urusan tentang manusia, melainkan adanya koneksi dengan non manusia.
Merujuk pendapat Paul W. Taylor, dalam bukunya Respect for Nature: A Theory of Environmental Ethics, dan Rosi Braidotti, dalam bukunya The Posthuman, etika lingkungan dapat kita kembangkan melalui paradigma yang lebih plural, diantaranya:
Pertama, Biocentrism, mengakui nilai intrinsik semua makhluk hidup (bukan hanya manusia). Kedua, Ecocentrism, memperluas fokus etika ke sistem ekologis secara komprehensif. Ketiga, Posthumanism, menolak dikotomi manusia-non manusia serta menekankan keberlangsungan bersama dalam ekologi kehidupan.
Dalam konteks global, praktik ini tampak pada pengakuan hak alam. Misalnya, Konstitusi Ekuador 2008 yang memberikan hak legal kepada alam (terkenal Pachamama), kemudian diikuti oleh Undang-Undang Bolivia 2010 tentang Hak-Hak Ibu Bumi (Ibu Pertiwi).
Keduanya memberikan hak bawaan kepada alam (hak untuk hidup, bergenersi, dan bebas dari polusi) dan memungkinkan warga negara dapat menuntut atas nama alam jika terjadi pelanggaran hak. Model hukum tersebut menunjukkan pergeseran radikal dalam cara politik melalui entitas non manusia sebagai subjek hukum.
Perspektif Lokal di Indonesia: Tantangan dan Implikasi Politik-Etika dalam Relasi Manusia-Non Manusia
Dalam tinjauan kosmologi masyarakat adat di Indonesia, relasi manusia-non manusia tidak pernah sepenuhnya terpisah. Bagi masyarakat adat, alam dipandang sebagai bagian yang integral dari kehidupan manusia, dengan status moral dan spiritual.
Contohnya, masyarakat Dayak melihat hutan bukan sekadar sumber ekonomi, melainkan rumah dari roh leluhur. Masyarakat Baduy menjaga larangan eksploitasi berlebihan karena keyakinan akan keseimbangan kosmos.
Pendekatan adat dapat kita pahami sebagai bentuk etika lingkungan tradisional yang selaras dengan wacana ekosentrisme modern. Namun, dalam kajian politik formal di Indonesia, paradigma antroposentrisme dan pembangunan masih dominan.
Dalam bukunya Tania Murray Li, Land’s End: Capitalist Relations on an Indigenous Frontier (2014), masifnya proyek ekstraktivisme seperti pertambangan, perkebunan sawit, serta proyek energi kerap mengabaikan relasi harmonis ini.
Tantangan dalam membangun politik dan etika lingkungan, dengan mengakui relasi manusia-non manusia di antaranya: (Dobson, 2007) Pertama, kapitalisme global, terus mendorong ekstraktivisme demi pertumbuhan ekonomi. Kedua, hegemoni pembangunan, di negara berkembang sering mengorbankan aspek ekologis demi modernisasi. Ketiga, keterbatasan hukum internasional, dalam menegakkan hak-hak ekologis secara efektif.
Namun terdapat peluang transformatif, menurut Andrew Dobson dalam bukunya Green Political Thought, demokrasi harus diperluas untuk mencakup kepentingan suara ekologis. Etika lingkungan dapat memikul tanggung jawab lintas generasi, menempatkan manusia wajib menjaga bumi untuk manusia dan non manusia pada masa depan.
Penutup
Relasi manusia dan non manusia dalam kajian politik dan etika lingkungan menunjukkan pergeseran yang mendasar, dari paradigma antroposentris ke ekosentris, dari relasi dominasi menuju koeksistensi. Manusia tidak dipandang sebagai makhluk hidup mempunyai otoritas tunggal sebagai penguasa jagad raya, melainkan bagian dari komunitas ekologis yang luas.
Etika lingkungan hadir sebagai nilai intrinsik makhluk non-manusia. Sedangkan politik lingkungan hadir sebagai representasi bagi mereka dalam sistem pengambilan keputusan. Praktik di masyarakat adat dan eksperimen politik global, seperti pengakuan hak alam, menunjukkan bahwa paradigma ini dapat dioperasionalisasikan.
Namun, dalam perjuangan masih berhadapan dengan kekuatan kapitalisme global dan paradigma pembangunan modern. Oleh karenanya, membangun relasi manusia dengan non manusia menjadi kian relevan. []