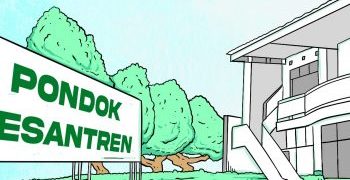Mubadalah.id – Mengapa otoritas keagamaan sering jadi alat legitimasi kesepihakan? Pertanyaan ini kembali menyeruak kala mendengar kabar tentang oknum kyai di Bekasi yang merudapaksa anak angkatnya beberapa waktu lalu.
Sementara, di negeri seberang, kita tentu belum lupa dengan peristiwa nahas yang mendera Suster Vassa Larin. Liturgis Ortodoks Rusia kelahiran Amerika Serikat itu kehilangan posisinya sebagai biarawati lantaran hobi mengkritik invasi Rusia ke Ukraina.
Mirisnya, keputusan pencopotan itu datang dari pemimpin tertinggi gereja ortodoks Rusia, Patriark Kirill, figur yang masyhur sebagai loyalis Vladimir Putin.
Alih-alih sekadar pemutasian dari profesi baktinya, otoritas gereja juga memaksa Suster Vassa yang juga aktif di saluran YouTube lewat kanal Coffee with Vassa itu untuk berhenti berjejaring via internet—sebuah ancaman terhadap hak berkomunikasi.
Praktik pemutasian sepihak yang Suster Vassa terima dan alami tak lain merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang (abuse of power) oleh segelintir elit. Van Dijk (2014) dalam analisis wacana kritisnya mengemukakan bila kuasa yang melekat pada segelintir elit memang acap berfungsi secara ilegitimatis.
Sang elit menunjukkan pengaruhnya untuk mengontrol, menundukkan, atau bahkan menyerang pihak lain. Ia akan menerapkan serangkaian mekanisme yang umumnya bersifat hegemonik lagi subtil (halus) lewat serangkaian pendekatan—juga sistem.
Tak disadari
Karenanya, tak mengherankan jika di banyak kasus lain, situasi penundukan oleh elit agama seperti yang menimpa Suster Vassa kerap berlangsung tanpa adanya kendali kesadaran dari jemaatnya.
Alhasil, alih-alih beroleh kritik akademis, fenomena yang menggejala justru mendapat aseptensi sebagai kelaziman normatif alias sesuatu yang b aja.
Patriark Kirill bukanlah figur satu-satunya yang menggunakan kuasa otoritatif untuk mendukung peperangan seperti yang kini berlangsung antara Ukraina dan Rusia. Sejak masa berkobarnya Perang Salib (1095), misalnya, otoritas agama telah mengemuka sebagai raja diraja buas sebagai bagian dari peperangan yang bersenjatakan kitab suci.
Mereka, sebagaimana Laura Pizzoferrato (2023) ungkap, memanfaatkan pengaruhnya yang signifikan untuk mendukung inisiasi kelompok bersenjata (non-state armed groups / NSAG’s). Sama seperti pada kasus Suster Vassa, para pemuka agama melakukan strategi persuasi lewat internalisasi norma, melegitimasi dan mensahihkan praktik kekerasan, serta praktik koersivitas.
Temuan Pizzoferrato ini dapat memberi jawaban atas pertanyaan mengapa di negara-negara yang cenderung religius, api kekerasan dan peperangan justru sering berkobar. Alih-alih bekerja sebagai embun penyejuk, agama justru berlaku selayaknya minyak tanah yang mengucur kedalam kobaran api.
Dua mata pisau
Derita yang menjerat Suster Vassa membuat kita sadar, bahwa agama pada prinsipnya memang serupa dua mata pisau yang kontradiktif dan bisa saling melukai (Tajfel, 1978). Pada satu sisi, agama dapat mewujud sebagai energi pemersatu dan perekat solidaritas di antara umat (in group).
Namun, pada sisi yang lain, agama juga punya wajah eksklusivisme yang menegasikan kelompok liyan (out group). Posisi ini membuat agama senantiasa berada di area rawan—atau berbahaya. Terlebih, dengan sistem kepemimpinan yang hierarkis lagi dogmatis, agama senantiasa tak pernah bebas dari kepentingan tertentu.
Di lingkup in group, para tokoh agama dapat memanfaatkan jemaatnya untuk kepentingannya atas nama loyalitas. Sementara, di ranah out group, agama sangat potensial menjadi penyulut konflik lewat diversitas nilai, sistem, serta tata sosial.
Praktik baik
Praktik baik tentang gerakan perdamaian lintas iman (inter faith peace) yang banyak muncul di Indonesia merupakan satu pengecualian menarik. Di hadapan wajah multikulturalisme dan diversitas yang sangat kompleks, para pemimpin agama secara sadar membangun keharmonisan progresif menuju umat berperadaban.
Hanya saja, dalam banyak situasi, keharmonisan itu masih bertindak pasif dan menunggu, ketimbang berdiri proaktif dan penuh inisiasi. Misalnya, dalam peristiwa demonstrasi di akhir Agustus lalu, para tokoh agama baru bersuara selepas dikumpulkan presiden.
Alih-alih sedari awal turut bersuara lantang menentang arogansi pejabat, para rohaniawan memilih “diam” dan akhirnya menyeru “tenang”. Tak berlebihan bila beberapa pihak menyayangkan sikap tersebut, terutama lantaran seruan tenang semacam itu agak terasa menyayat bagi upaya demokratisasi negeri.
Umat berdaya
Belajar dari kasus Suster Vassa, umat beragama sebenarnya memegang kunci perubahan. Kritik terhadap penyalahgunaan otoritas tidak akan berarti bila jemaat terus memelihara sikap pasif atau sekadar mengamini setiap seruan pemimpinnya.
Partisipasi kritis umat melalui literasi agama, solidaritas lintas iman, serta keterlibatan aktif dalam berbagai isu kemanusiaan dapat menjadi penyeimbang yang membatasi feodalisme religius.
Dengan kesadaran kolektif, agama dapat terbebas dari cengkeraman kepentingan politik dan dikembalikan pada fungsinya sebagai ruang pembebasan dan perdamaian (ad din al istihrariyyah). Berkaca dari peristiwa yang menimpa Suster Vassa, semangat moderasi beragama (wasathiyah) yang menggema dewasa ini beroleh tantangan nyatanya.
Kala hubungan antarumat beragama dapat saling berlaku secara dialogis dan kompromis, hubungan antara pemimpin agama dan jemaatnya justru masih dikelindani oleh feodalisme dan penyalahgunaan. Glorifikasi, fetisisasi (penjimatan), serta pengistimewaan berlebihan terhadap agamawan sudah semestinya berkesudahan.
Suster Vassa tentu bukan korban tunggal dari produk otoritarianisme tokoh agama. Di luar sana, berjuta-juta umat sekarat dalam belenggu mobilisasi, karitasisasi, serta indoktrinasi radikalisme. Lantas, apa kita hanya akan mendiamkannya saja? []