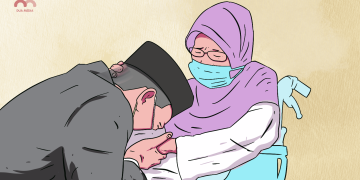Mubadalah.id – Aku sebenarnya bukan orang yang gugup. Itu hanya anggapan mereka yang belum mengerti tentang kehidupanku. “Apakah kau mau jadi temanku?” Aku akan bertanya kepada setiap anak yang aku temui. Mereka selalu menjawab ya, sampai suatu hari seorang gadis ingusan mengatakan tidak – dan menjulurkan lidahnya padaku. Aku terkejut. Aku tidak tahu bagaimana aku harus bersikap.
Aku kemudian bertanya pada gadis itu mengapa ia tidak suka padaku. Alih-alih menjawab, ia hanya mengangkat bahunya dan berjalan pergi kembali ke orang tuanya. Aku terus menatap gadis itu dan bertanya-tanya: “Mengapa dia tidak ingin berteman denganku?” Aku masih belum mengerti.
Orang tuaku kemudian menjelaskan bahwa mungkin, untuk pertama kalinya, aku bertemu dengan orang yang tidak menyukaiku.
“Itu normal,” kata ayahku.
“Karena kita tidak mungkin bisa memaksakan orang lain supaya mau menyukai kita,” sambung ibuku.
Aku tidak sepenuhnya mengaminkan perkataan mereka. Namun itu adalah hal baru bagiku. Sebagai anak sembilan tahun aku mencoba untuk menyukai setiap orang yang aku temui. Karena aku tahu benar rasanya ditolak itu sama sekali tidak menyenangkan. Mungkin begitulah cara dunia ini bekerja, pikirku.
Pandangan bahwa beberapa orang mungkin tidak menyukaiku sangat sulit untuk aku pahami. Bagaimana aku bisa tahu apakah si A atau si B menyukaiku atau tidak?
“Kau akan tahu dengan sendirinya, nak,” kata ayahku.
“Kau mungkin akan merasakan sesuatu – semacam sinyal atau sejenisnya. Intinya sesuatu seperti itu.” Ibuku menambahkan.
“Ibu, bisakah kau memberikanku penjelasan yang sesuai dengan usiaku? Itu sama sekali tidak menjelaskan apa-apa.”
Ibu mencoba berkelit, “Kau mau segelas susu?”
Aku pun mengangguk.
Sejak saat itu, aku berhenti meminta anak-anak lain untuk berteman denganku; bagaimana jika mereka adalah bagian dari kelompok orang yang tidak menyukaiku? Lebih baik aman daripada menyesal, bukan?
Jadi, aku pun berhenti untuk mencari teman. Sebaliknya, aku hanya menyapa mereka yang memang ingin berbicara denganku saja; mereka yang jelas menunjukkan bahwa mereka menyukaiku.
Ini tentu tidak mudah bagi anak sembilan tahun. Aku mungkin hanya akan melihat anak-anak lain yang sedang bermain. Meskipun aku sangat ingin bergabung, tetapi aku tidak bisa. Rasa gugup, ketakutan dan pikiran-pikiran negatifku spontan akan menahanku.
Dan kemudian, hidupku terus berlanjut.
***
Aku sekarang berusia 30-an dan nampaknya sifat naif masa kecilku itu masih terbawa sampai sekarang. Persis seperti pribahasa ‘kecil teranja-anja, besar terbawa-bawa’.
Meskipun secara pengalaman kini aku lebih mengerti bagaimana segala sesuatu itu bekerja, dan aku tahu kapan seorang menyukaiku atau tidak daripada ketika aku masih berusia sembilan tahun, aku terkadang masih berjuang untuk mencari cara bagaimana harus memulai percakapan yang baik agar orang lain tidak tersinggung atau merasa nyaman denganku.
Namun tak jarang juga aku masih merasa aneh dan tidak siap untuk itu.
Suatu hari aku pergi menemui kepala sekolah di sekolah putriku. Aku ingin dia memberikan teguran pada guru matematika di sana. Sebagai orang tua aku merasa adalah keharusan untuk menjaga dan membela anak sendiri.
Bagaimana pun aku tidak menyukai cara mengajar guru matematika itu yang aku nilai sudah terlalu kuno. Dia kerap memberikan hukuman fisik dengan alasan yang aku kira tidak jelas, bukan hanya pada putriku, tapi juga anak-anak lain.
Dari semua orang tua, mungkin hanya aku saja yang berani angkat suara mengkritik cara sekolah melayani dan memberi pengajaran kepada anak-anak.
Malam sebelumnya, aku sudah memberi tahu istriku tentang apa-apa saja yang akan aku sampaikan nanti – setiap detail yang akan aku tunjukkan kepada kepala sekolah.
Kepala sekolah adalah seorang pria besar dengan suara berat yang mungkin jika ia berbicara bisa Anda dengar sekalipun dari jauh. Pada hari itu, dia nampak sibuk dan kesal. Dia baru saja menutup telepon ketika aku berjalan di kantornya (aku mendengar dia berteriak cukup keras beberapa detik sebelumnya).
Kami pun bertemu. Dia menjabat tanganku dan memberi isyarat agar aku masuk ke ruangannya. Dia kemudian memeriksa komputernya kembali.
“Tunggu sebentar.” Ucapnya.
Aku mengangguk. Aku lalu melihat-lihat sekeliling ruangannya untuk mencari hal-hal menarik untuk dilihat sembari menunggu. Di sana ada banyak sekali foto dan piagam. Termasuk tentu saja, foto presiden dan wakil presiden dengan latar bendera di belakangnya.
“Aku dikabari bahwa bapak punya keluhan dengan guru matematika kami, bukan?” Dia bertanya setelah beberapa menit, membuka buku catatan besar dan mengambil pena.
“Ya… ya… aku ingin berbicara denganmu tentang dia… tentang beberapa kekhawatiran yang… aku kira alami dimiliki oleh semua orang tua,” seperti biasa, penyakit gugupku kembali lagi.
“Oke. Jadi, apa keluhan bapak? Aku harap itu bukan hal yang serius.”
Tentu saja ini serius sekali, pikirku. Namun sebaliknya aku berkata, “Tidak… tidak. Aku hanya ingin menyampaikan sesuatu….”
“Sesuatu?” ia mulai memperbaiki posisi duduknya, dan menurunkan sedikit kacamatanya hingga menunjukan tatapan serius.
“Hal-hal kecil yang dibicarakan anak-anak… aku kira.” Aku mulai merasa gerah dan tidak nyaman. Padahal jelas ruangan itu ber-AC.
Sial, kegugupanku meningkat.
“Oke. Silakan.”
“Tidakkah bapak berpikir kalau… mungkin… dia terlalu keras mengajar anak-anak? Maksudku, si guru matematika,”
“Bisa dijelaskan? Apa bapak punya contoh perilakunya yang menurut bapak keras pada anak-anak?”
Aku punya bukti! Aku sudah menyusun semuanya semalam, bahkan sudah menghapalkannya, pekikku dalam hati. Bagaimana mungkin insting orang tua bisa menafikan fakta bahwa setiap pulang sekolah anaknya terus mendapatkan bekas tamparan di pipinya?
Namun sekeras apapun aku berpikir, mulutku justru berkata lain, “Em, mungkin dia sudah mengajar dengan baik sebagai seorang guru… hanya saja anak-anak… Anda tahu… mereka suka berbicara….”
“Ya, anak-anak memang suka berbicara. Tapi apakah hanya itu yang ingin bapak sampaikan?”
“Tidak. Yah, ya … seperti … yang anak-anak bicarakan … tentang sikapnya … mungkin itu bukan apa-apa. Tapi aku ingin kau tahu….”
Dia diam menatapku selama beberapa detik. Aku mendapat getaran. Perasaan yang familiar; Apakah dia tidak menyukaiku? Apakah dia marah? Apakah dia tersinggung? Tanyaku dalam hati.
“Jadi, ada apa? Sebenarnya apa yang terjadi? Tolong jelaskan supaya saya bisa mengerti.”
“Tidak ada yang serius. Aku hanya ingin Anda tahu… tentang… tentang rumor ini.”
“Mohon maaf, pak. Kami tidak ingin berurusan dengan rumor apapun di sini. Apakah bapak punya bukti yang mungkin lebih spesifik? Selain rumor?”
Aku membeku. Aku sebenarnya tidak memiliki bukti kuat. Tidak. Tepatnya keberanian yang kuat. Hanya saja kegugupanku membuat semuanya kacau.
“Tidak. Tidak juga. Ah, mungkin ini bukan masalah yang besar.”
Dia mendesah lalu menutup kembali buku catatan itu – sama kosongnya dengan saat awal pertemuan kami.
“Terima kasih. Aku akan mengingat keluhan Anda. Terima kasih sudah merepotkan diri buat jauh-jauh datang ke sini…” Ujarnya sembari melipat tangannya.
Aku tidak tahu. Aku merasa ada sesuatu ‘lain’ di balik kalimatnya barusan. Dia kemudian berdiri lalu mengantarku keluar dari kantornya
Begitu aku keluar teleponku berdering. Itu istriku. Dia ingin tahu bagaimana hasil pertemuan itu.
“Jadi? Apa yang dia katakan?”
“Dia bilang dia akan mengingat keluhanku…”
“Mengingat keluhanmu? Guru itu seharusnya di penjara! Apa kau sudah memberitahunya bahwa kita tidak segan-segan akan melaporkan sekolah ke polisi jika mereka tidak menindaklanjutinya?”
Sebagai suami dan orang tua aku merasa malu. Tentang betapa sulitnya menumbuhkan keberanian untuk mengungkapkan kebenaran. Dan karena itu pula istriku menjadi semakin meledak. Belakangan aku sadar – adalah keputusan tepat untuk tidak membawanya kemari. Jika tidak, aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan di sini.
Memang benar, jika sudah berkenaan dengan anak, seorang ibu lah yang akan berdiri di garis depan untuk membela anaknya. Terlepas dari apakah anaknya salah atau tidak.
“Sudahlah… Aku yakin kepala sekolah pasti mengerti dan akan melakukan sesuatu…”
***
Sesampainya di rumah, aku lalu membuat catatan dari semua hal yang mungkin akan aku ceritakan kepada kepala sekolah ketika anakku bermasalah lagi dengan guru matematikanya.
Aku berjanji PASTI akan memberitahunya. Tanpa gugup, tentunya.
Aku lalu meminta putriku untuk menuliskan semua kejadian yang ia dan teman-temannya alami ketika guru itu mengajar.
Namun, keesokan harinya tiba-tiba kami menerima kabar bahwa guru matematika itu telah melukai seorang siswi di sekolah itu, yang membuat siswi tersebut mengalami patah tulang di salah satu jarinya. Tidak ada yang tahu apa yang kemudian terjadi pada guru matematika itu, karena dia sudah menghilang saat polisi datang. []