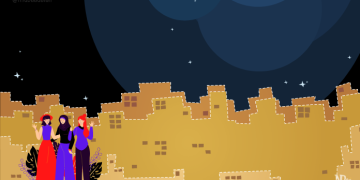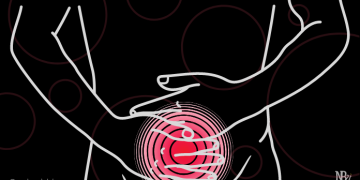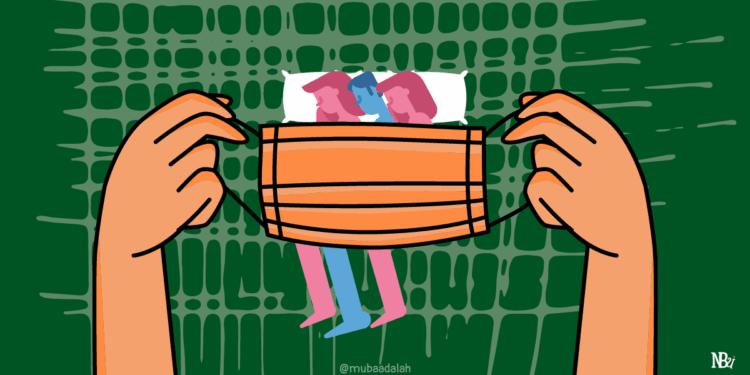Mubadalah.id – Sehari terakhir, jagat media sosial X kembali riuh oleh beredarnya potongan video dari sebuah podcast yang ramai warganet perbincangkan. Video tersebut menampilkan percakapan aktris senior Soimah dengan podcaster Raditya Dika, yang kemudian viral karena pernyataan Soimah mengenai sikapnya terhadap pasangan anak laki-lakinya.
Dalam tayangan tersebut, ia mengaku sengaja memperlakukan pasangan anak dengan cara keras, penuh sindiran, bahkan makian, sebagai bentuk “ospek” untuk menguji kesungguhan mereka. Ungkapan seperti “aku maki-maki,” “aku ospek,” hingga “kalau nggak betah ya putus saja” menjadi sorotan publik.
Potongan pernyataan tersebut cepat menyebar, memicu respons beragam mulai dari kritik tajam, candaan, hingga diskusi serius mengenai pola relasi orang tua, pasangan anak, dan budaya dalam masyarakat. Bahkan, tagar #Soimah sempat masuk trending topic di For Your Page X dengan lebih dari 8.700 unggahan.
Sisi Bermasalah dalam Pola Asuh Ibu terhadap Anak Laki-Laki
Ada cara pandang yang lain nggak dari pasangan yang dia bawa? Kaya calon mertua gua nih atau keluarganya mereka atau apa? Justru awal-awal aku ospek, maksudnya dengan mulutku ini pokoknya Aku ospek. Sempat awal-awal tuh dia nangis. Pokoknya aku maki-maki. Pokoknya Aku ini dengan caraku lah. Heeh lu nggak ada cowok lain? Nggak ada laki-laki lain? (Macarin anak SMA kan dari SMA kan). Pokoknya banyaklah kata-kataku yang ketus yang nggak bisa tak omongin disini, pokoknya banyak.
Oke, akhirnya dia nangis. Malem-malem aku tidur dibangunin sama anakku (habis nganterin pacarnya). Anakku tanya, “Bu Ibu tadi ngomong apa ke si A (pasangan anak), kenapa emang? Dia minta putus…” Soimah menjawab, “Ya putus aja, ngapain repot? Nyari lagi! Lu pacaran sama anakku harus nerima ini orang tuanya.
Jadi aku suka memperlihatkan hal terburukku di awal. Jadi kalau kalian menilaiku langsung buruk maksudnya langsung ngga betah ya nanti next kamu ngga akan jadi betah. Selanjutnya dia datang minta maaf. Dia yang mulai terima aku, tapi aku nggak menerima dia dan itu prosesnya masih berjalan. Yang aku srek itu masih berjalan sampai hari ini.
Jadi kadang-kadang aku akrab bercanda apa tapi satu sisi pas misalnya ada sesuatu yang misalnya memang Aku harus pemarah, aku bener-bener kenceng. Sama semua aku perlakukan sama (seluruh pasangan anaknya).
Fenomena yang melibatkan pernyataan Soimah dalam sebuah podcast bersama Raditya Dika menarik perhatian publik dan menimbulkan perdebatan luas di media sosial. Potongan video yang beredar menampilkan bagaimana Soimah mengisahkan sikapnya terhadap pasangan anak laki-lakinya.
Ia mengaku “mengospek” atau memperlakukan pasangan tersebut dengan cara keras, penuh sindiran, bahkan makian. Dengan alasan untuk menguji kesungguhan mereka dalam menjalin hubungan. Pernyataan tersebut menimbulkan respons negatif karena memperlihatkan bentuk relasi yang tidak sehat dalam ranah keluarga maupun sosial.
Apa yang Menjadi Akar Permasalahannya?
Jika kita analisis secara ilmiah, terdapat beberapa akar permasalahan (root cause) yang dapat kita identifikasi. Pertama, terdapat pola pikir otoritarianisme orang tua dalam konteks relasi anak dengan pasangan. Dalam budaya patriarkal Indonesia, orang tua sering merasa memiliki otoritas penuh atas pilihan dan kehidupan anak, termasuk urusan romantis.
Sikap tersebut berakar pada konstruksi sosial yang menempatkan anak, terutama dalam hubungan romansa, sebagai bagian dari “kepemilikan” keluarga”. Sehingga pasangan anak harus melewati “uji kelayakan” yang orang tua tentukan.
Kedua, muncul faktor normalisasi kekerasan verbal sebagai bentuk kasih sayang atau “pendidikan.” Dalam narasinya, Soimah menegaskan iasengaja menampilkan sisi terburuk agar pasangan anak terbiasa menghadapi hal-hal sulit.
Namun, praktik semacam ini mencerminkan bias budaya yang menganggap perilaku keras dapat dimaklumi sebagai cara mendidik atau menguji. Sejalan dengan fenomena di masyarakat di mana kata-kata kasar, sindiran, atau makian masih sering dianggap wajar. Padahal dampaknya dapat merusak kesehatan psikologis individu.
Ketiga, terdapat dimensi ketidaksetaraan relasi kuasa antara orang tua dan pasangan anak. Posisi orang tua memiliki anggapan yang lebih tinggi, sementara pasangan anak harus “menerima” tanpa syarat.
Justru yang terlihat hanyalah minimnya ruang untuk membangun relasi yang setara, padahal hubungan anak dengan pasangannya seharusnya melibatkan kesalingan, bukan dominasi salah satu pihak. Relasi kuasa yang timpang berpotensi menormalisasi praktik diskriminatif terhadap individu yang berada “di luar” struktur inti keluarga.
Bagaimana Mubadalah Memandang Pola Asuh dan Masalah Tersebut?
Dalam kitab Qiraah Mubadalah karya Kyai Faqih Abdul Kodir, dalam sub-bab Tauhid Anti-Patriarki (halaman 30), beliau menjelaskan bahwa setiap rasul mempunyai misi yang sama, yaitu tauhid atau hanya menuhankan Allah Swt., yang berarti tidak menuhankan apa dan siapa pun selain-Nya.
Ketaatan hamba hanya menyembah-Nya tidak membuat-Nya semakin berkuasa, dan pembangkangan mereka pun tidak mengurangi kekuasaan-Nya. Tauhid memberi manfaat secara langsung pada kehidupan manusia.
Sebab, dengan tidak menuhankan apa dan siapa pun selain Allah Swt., manusia terhindar dari ketundukan mutlak pada selain-Nya, seperti hasrat atas kekuasaan, harta benda, nafsu dan seksual, serta terhindar juga dari pengabdian mutlak pada sesama makhluk. Tauhid, dengan demikian mempunyai konsekuensi logis memperlakukan manusia secara proporsional sebagai manusia atau sikap memanusiakan manusia.
Peran memanusiakan manusia dalam tauhid yang oleh Nabi Muhammad Saw. ajarkan mempunyai arti khusus, yaitu memanusiakan perempuan. Perlakuan tidak manusiawi pada perempuan yang dilakukan masyarakat Arab dan lainnya pada masa itu sangat luar biasa.
Perempuan hidup di bawah kepemilikan mutlak laki-laki, seumur hidup, dan diperlakukan sewenang-wenang secara masif. Perempuan diragukan kemanusiannya sehingga kerap diperlakukan secara tidak manusiawi.
Islam mengubah cara pandang dikotomis antara laki-laki dan perempuan menjadi sinergis. Tauhid yang Nabi Muhammad Saw bawa menegaskan bahwa perempuan adalah manusia seutuhnya sebagaimana laki-laki (QS. al-Hujuraat [49]:13). Sehingga mereka juga harus kita perlakukan secara manusiawi.
Perbedaan keduanya tidak boleh menjadi alasan untuk melemahkan , melainkan harus dipandang sebagai kekuatan bersama dalam menjalani misi hidup. Karenanya, tauhid mempunyai cara pandang yang bertentangan dengan sistem patriarki.
Apa yang Perlu Kita Perbaiki dari Cara Pandang Tersebut?
Dalam perspektif Mubadalah, praktik pola asuh yang menormalisasi kekerasan verbal jelas bertentangan dengan prinsip tauhid yang menolak segala bentuk pengabdian mutlak kepada selain Allah Swt.
Tauhid meniscayakan sikap memanusiakan manusia, termasuk dalam relasi keluarga dan pola asuh. Jika orang tua menempatkan dirinya sebagai otoritas absolut yang harus diterima tanpa syarat, maka hal itu berpotensi menyerupai bentuk “penuhanan” manusia atas manusia lain, sebuah sikap yang berlawanan dengan tauhid.
Kiai Faqih menekankan bahwa Islam hadir untuk menghapus ketimpangan relasi, termasuk relasi patriarkal yang menempatkan pihak tertentu lebih rendah dari yang lain. Dalam kasus pernyataan Soimah, memperlakukan pasangan anak dengan makian atau ospek keras bukan menjadibentuk kasih sayang, melainkan hanya berupa kontrol yang melemahkan posisi orang lain sebagai manusia seutuhnya.
Refleksi Terhadap Cara Pandang Tersebut
Bagi saya, Soimah perlu meminta maaf kepada pasangan anaknya sebagai bentuk tanggung jawab moral sekaligus pengakuan atas kesalahan dalam memperlakukan manusia lain. Hal tersebut sejalan dengan prinsip memanusiakan manusia dalam perspektif Mubadalah. Setiap relasi, baik keluarga maupun sosial, harus kita bangun pada nilai kesalingan, penghargaan, dan penghormatan.
Lebih jauh, Soimah juga perlu melakukan perbaikan pola asuh agar tidak mengulangi kesalahan yang sama terhadap pasangan anak-anaknya yang lain. Pola asuh berbasis kekerasan verbal tidak dapat kita benarkan, meskipun latar belakangnya adalah niat untuk melindungi atau menguji keseriusan seseorang.
Justru, pola tersebut berpotensi menormalisasi relasi kuasa yang timpang dan menimbulkan luka psikologis, baik pada pasangan anak maupun pada anak itu sendiri.
Jika memang terdapat ketidaksetujuan atau ketidakrestuan terhadap hubungan anak dengan pasangannya, seharusnya hal tersebut disampaikan melalui komunikasi yang sehat, terbuka, dan penuh penghormatan. Orang tua tidak seharusnya menjadi pihak yang dominan secara mutlak. Justru orang tua lah yang harusnya menjadi mitra dialog yang memuliakan anak dan lingkar sosialnya.
Cara pandang yang demikianlah, yang menjadikan hakikat keluarga dapat berfungsi sebagai ruang aman dan sehat. Sesuai dengan prinsip kesalingan dalam Mubadalah, yang menekankan bahwa setiap manusia adalah subjek utuh yang layak kita hormati. []