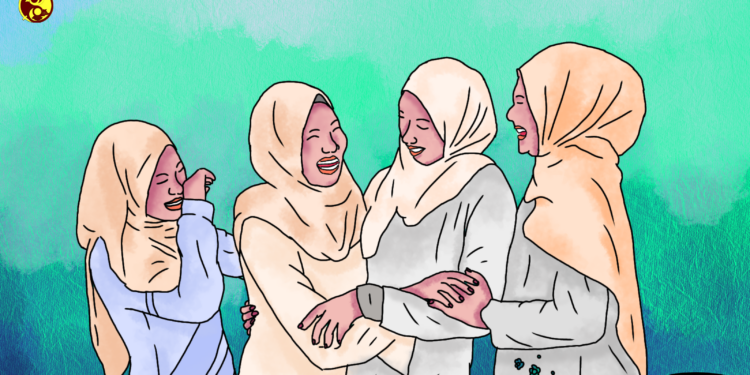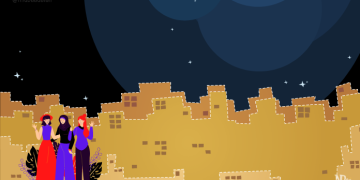Mubadalah.id – Banyak analisis menunjukkan bahwa pembedaan batas aurat dalam al-Qur’an lebih ditentukan oleh konteks sosial. Mereka yang dikecualikan dipahami sebagai pihak yang, dalam tradisi Arabia saat itu, tidak menimbulkan bahaya atau potensi hasrat seksual.
Faktor ini dalam bahasa yang lebih populer kita sebut tidak menimbulkan “fitnah”. Dengan kata lain mereka adalah orang-orang yang dapat menjamin keamanan atas tubuh perempuan.
Faktor lain adalah menghindari kerepotan atau kesulitan (raf’an li al haraj wa al masyaqqah) dalam bekerja, atau dengan kata lain untuk kemudahan gerak (li al hajah).
Dari sini menjadi jelas kiranya bahwa batasan-batasan aurat sangat tergantung pada konteks sosial, tradisi atau kebudayaan masyarakat. Bagian tertentu dari tubuh perempuan boleh jadi dipandang aurat oleh suatu masyarakat atau pada suatu zaman atau di suatu tempat. Tetapi tidak dipandang aurat oleh masyarakat lain dan pada zaman atau tempat yang lain.
Kasus ini agaknya sama dengan kasus “pornografi” atau “pornoaksi” yang memicu kontroversi hebat sampai hari ini. Terminologi “porno” amat sulit untuk dirumuskan secara pasti dan tunggal. Ia dapat kita tafsirkan secara ambigu atau relatif. Kepornoan padanya sendiri adalah sesuatu yang netral.
Tetapi ia menjadi problem serius ketika kita bawa ke ranah publik. Di sini sejumlah faktor kepentingan akan mendefinisikannya sesuai dengan kepentingannya masing-masing, baik yang bersifat politik, ekonomi, ideologi sosial, tradisi maupun aturan-aturan lain yang bersifat formal dan skriptual.
Terlepas dari perdebatan mengenainya, tetapi satu hal yang menjadi perhatian utama agama adalah bahwa tubuh perempuan (dan laki-laki) harus saling menghormati, tidak melecehkan dan merendahkan apalagi mengeksploitasi untuk sebuah kepentingan. []
Sumber: Buku Perempuan, Islam dan Negara karya KH. Husein Muhammad