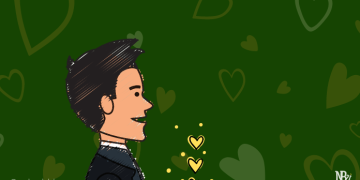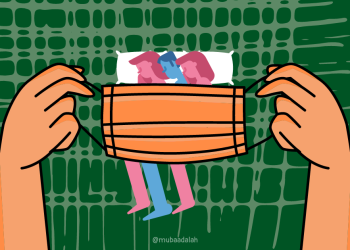Mubadalah.Id – Pondok pesantren sejak lama menjadi pilihan utama masyarakat untuk memperkuat spiritualitas sekaligus membentuk karakter santri yang berakhlak. Pesantren menarik minat masyarakat karena mampu menggabungkan tradisi keilmuan Islam dengan nilai-nilai kebersamaan. Sehingga tetap relevan sebagai tempat pendidikan yang baik.
Namun, ada pertanyaan besar yang menggelayuti dan selalu ada dalam fikiran. Apakah anak-anak yang difabel dapat hidup di pesantren sebagai seorang santri? Pertanyaan ini muncul setiapkali ada peringatan Hari Santri Nasional.
Pertanyaan ini muncul karena saya menyaksikan tetangga saya yang memiliki seorang anak difabel, seorang anak memiliki semangat penuh untuk merasakan kehidupan di Pesantren sebagaimana teman-temannya. Keinginan sederhana itu merefleksikan hak dasar setiap individu untuk memperoleh Pendidikan agama tanpa diskriminasi.
Dalam realitasnya, kita menyaksikan anak disabilitas tidak mendapatkan sambutan baik di ruang publik. Hal ini membuktikan bahwa inklusifitas di pesantren masih dalam bentuk wacana daripada realisasi nyata.
Data Disabilitas di Indonesia
Padahal, data dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2022) menunjukkan jumlah penyandang disabilitas di Indonesia terus meningkat hingga 22,5 juta dan perempuan menempati proporsi yang signifikan. Mengabaikan mereka sama halnya dengan mengabaikan potensi besar bangsa.
Setiap tahun kita memperingati Hari Santri dengan penuh semangat oleh jutaan santri di seluruh Indonesia. Peringatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan momentum untuk mengenang peran historis santri dalam perjuangan bangsa.
Hal ini sekaligus refleksi inklusif tentang peran pesantren dalam membangun peradaban Islam yang Rahmatan Lil ‘Alamin. Refleksi ini mengakui dan memberdayakan semua kelompok, termasuk perempuan penyandang disabilitas, sebagai bagian dari kekuatan bangsa dan umat.
Hal ini bukan untuk menyoroti kekurangan, melainkan sebagai ajakan reflektif agar Hari Santri semakin bermakna. Sebab tak jarang kita banyak menempatkan perempuan disabilitas masih di tepi ruang sosial. Padahal esensi dari Hari Santri harusnya meneguhkan pesan bahwa Islam merangkul seluruh umat manusia tanpa diskriminasi.
Faqihuddin Abdul Kodir mengungkapkan Qira’ah Mubadalah (2019) menekankan bahwa kesalingan antara laki-laki dan perempuan harus diwujudkan dalam setiap aspek kehidupan. Kesalingan itu tidak boleh berhenti pada batas gender semata, tetapi harus diperluas untuk merangkul mereka yang terpinggirkan.
Kita sering menempatkan mereka pada posisi marjinal sering membawa pengalaman spiritual yang jauh lebih besar. Mereka bukan objek belas kasihan, melainkan agen pengetahuan yang menghidupkan nilai-nilai keislaman dan mengingatkan bahwa kita beragam.
Menghadirkan Perempuan Disabilitas di Hari Santri
Iris Marion Young (1990) menegaskan dalam Justice and the Politics of Difference bahwa masyarakat harus mengakui kelompok-kelompok marjinal untuk mewujudkan keadilan sosial. Menghadirkan perempuan disabilitas dalam perayaan Hari Santri berarti mewujudkan keadilan sosial dalam wajah Islam Indonesia yang rahmatan lil alamin.
Dalam konteks inklusivitas, Al Qur’an memberikan legitimasi yang kuat tertuang dalam QS. Abasa (80): 1-11, misalnya, Allah menegur Nabi Muhammad SAW karena bermuka masam kepada seorang buta (Abdullah bin Ummi Maktum) yang datang untuk mencari ilmu. Ayat ini mengingatkan kita secara abadi untuk menghormati penyandang disabilitas dan memberi mereka ruang setara dalam kehidupan beragama.
Selain itu, pemikiran Amina Wadud dalam Qur’an and Woman (1999) sangat relevan untuk menegaskan prinsip kesetaraan yang inheren dalam Islam. Wadud menekankan bahwa Al-Qur’an tidak pernah membedakan nilai spiritual manusia berdasarkan gender maupun kondisi fisiknya, melainkan menilai berdasarkan ketakwaan dan amal saleh.
Dalam hal ini kehadiran perempuan disabilitas dalam perayaan Hari Santri bukan sekadar tuntutan sosial. Melainkan bagian dari misi keagamaan untuk menegakkan keadilan dan kesetaraan sebagaimana tertera dalam Al-Qur’an. Nancy Fraser (1995) mengonsep redistribution dan recognition, menegaskan keadilan sosial menuntut masyarakat mendistribusikan sumber daya secara adil dan mengakui identitas kelompok yang selama ini dipinggirkan.
Tantangan
Maftuhin (2023) menemukan bahwa organisasi Islam besar, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, sudah mulai bergerak ke arah memberikan afirmasi terhadap perempuan disabilitas. Meski demikian, ia menegaskan masih ada tantangan implementasi yang nyata di lapangan.
Selain itu, penelitian Dani dkk. (2022) dalam Islam Realitas meneliti kesiapan layanan ramah disabilitas di lembaga agama Yogyakarta. Hasilnya menunjukkan bahwa meski kebijakan sudah ada, implementasi masih lemah. Hal ini menegaskan perlunya aksi nyata di acara besar seperti Hari Santri.
Hari Santri yang inklusif bagi perempuan disabilitas dapat menjadi ruang pendidikan sosial bagi masyarakat. Pesantren yang selama ini menjadi pusat transformasi sosial, memiliki legitimasi moral. Hal itu untuk menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang merangkul semua, bukan mengecualikan.
Dalam hal ini banyak hal yang kita perlu siapkan untuk menunjang dan mendukung perempuan disabilitas agar hadir di ruang publik. Misalnya penyediaan aksesibilitas fisik di pesantren dan acara publik, pendampingan khusus, serta kebijakan yang menjamin partisipasi penuh tanpa diskriminasi.
Oleh karena itu, mewujudkan Hari Santri yang inklusif bagi perempuan penyandang disabilitas bukan sekadar tindakan simbolis. Melainkan langkah strategis untuk memperluas ruang pendidikan sosial dan memperkuat nilai keadilan dalam masyarakat.
Dengan legitimasi moral dan sejarahnya sebagai pusat transformasi sosial. Pesantren bertanggung jawab menyediakan sarana, akses, dan dukungan agar perempuan disabilitas dapat hadir dan berpartisipasi penuh dalam ruang publik. Dengan cara ini, Islam yang Rahmatan Lil ‘Alamin terwujud nyata, merangkul seluruh umat tanpa terkecuali. []