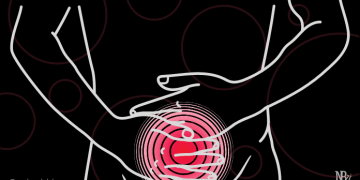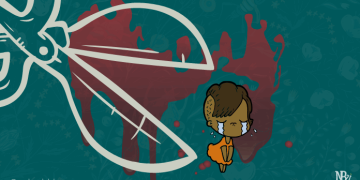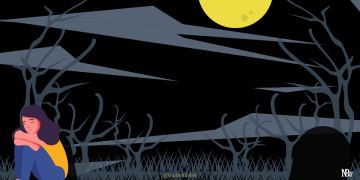Mubadalah.id – Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) telah menempati posisi penting dalam peta wacana Islam kontemporer di Indonesia. Ia bukan sekadar forum ulama perempuan, melainkan gerakan intelektual dan sosial yang mengusung tafsir keislaman berkeadilan gender, dengan metodologi khas yang tumbuh dari pengalaman panjang dan kerja kolektif antar lembaga, dan kelas sosial.
Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Siber Syekh Nurjati (SSC) Cirebon Wakhit Hasim, M.Hum menyebut KUPI sebagai gerakan pewacanaan yang unik dalam sejarah Islam Indonesia modern.
“KUPI adalah karya kolektif dari aktor-aktor yang datang dari latar belakang beragam baik secara individu, gender, agama, etnis, bahkan kelas sosial. Namun memiliki satu tujuan bersama yaitu menyebarkan gagasan dan praktik keadilan gender dalam kehidupan,” ujarnya.
Menurut Pendiri Yayasan Wangsakerta itu ada tiga prinsip utama menjadi pondasi epistemologis KUPI: resiprositas (mubadalah), kebaikan bersama (ma’ruf), dan keadilan (i’tidal).
Ketiganya merupakan hasil pergulatan intelektual tokoh-tokoh sentral KUPI seperti Dr. Faqihuddin Abdul Kodir, Nyai Hj. Badriyah Fayumi, dan Nyai Hj. Nur Rofiah, yang masing-masing datang dari tradisi dan konteks keulamaan yang berbeda.
“Prinsip ini menjadi fondasi cara berpikir yang membentuk bagaimana KUPI memahami, merespon, dan merumuskan solusi atas masalah-masalah sosial, politik, bahkan ekologi,” terang Wakhit.
Dari Reinterpretasi Teks ke Universal
Menurut Wakhit, ada dua sifat unik dalam metodologi KUPI. Pertama, pada aspek reinterpretasi ajaran Islam yang berangkat dari kesadaran bahwa banyak teks keagamaan memiliki potensi multitafsir. KUPI memilih jalan yang tidak konfrontatif dalam memahami teks. Tetapi menggunakan pendekatan apreciative inquiry sebuah cara pandang yang mencari titik temu etik, bukan memperlebar jurang perbedaan tafsir.
“Problem teks yang banyak pertentangan tafsir tidak dihadapi dengan benturan. Melainkan dicari arah moralnya, agar setiap pandangan menuju satu konsen etik yang sama,” jelasnya.
Pendekatan ini menggeser cara tradisional dalam berdebat teologis menjadi cara dialogis, yang tidak menonjolkan distingsi. Tetapi menegaskan kesamaan nilai kemanusiaan dan keadilan. “Meski metodologi tafsirnya berubah, KUPI membawa umat menuju satu kesadaran moral yang sama,” lanjutnya.
Wakhit menilai, untuk memperdalam aspek ini diperlukan kajian ulang terhadap metodologi klasik—khususnya dalam membaca tema-tema ketertindasan perempuan.
“Diperlukan pemisahan mana prinsip etik, mana instrumen tafsir, dan mana konteks sosial-historis yang mempengaruhi,” katanya. “Ini bisa jadi satu bab tersendiri dalam buku tentang metodologi KUPI.”
Gerakan yang Tidak Hanya Intelektual, Tapi Juga Praksis
Sifat unik kedua KUPI, lanjut Wakhit, adalah pada dimensi gerakan. Jika reinterpretasi ajaran merupakan ruang epistemologis, maka aspek gerakan adalah ruang praksisnya.
“Keduanya ibarat logika dan retorika. Logika adalah kemasukakalan argumen, sementara retorika adalah seni untuk mengomunikasikan logika itu kepada publik,” ungkapnya.
Melalui strategi ini, gagasan KUPI menyebar melintasi lapisan sosial yang luas. Di kalangan akademisi, konsep-konsep metodologis KUPI hadir dalam bentuk diskusi ilmiah, kajian tafsir, dan tulisan akademik.
Namun di sisi lain, narasi-narasi populer tentang keadilan gender dalam Islam juga digerakkan melalui media digital, menjangkau generasi muda, terutama Gen Z dan milenial.
“Banyak orang merasa menjadi bagian dari barisan KUPI tanpa harus ahli dalam metodologi tafsir. Cukup dengan menulis artikel populer, membuat konten edukatif di media sosial, atau aktif di jaringan digital KUPI—itu sudah kontribusi besar dalam menyebarkan nilai-nilai adil gender,” kata Wakhit
Menjangkau Akar Rumput: Dari Pesantren ke Desa
Namun, tantangan terbesar KUPI justru berada di lapisan akar rumput. Wakhit menjelaskan bahwa upaya memperluas jangkauan ke masyarakat desa, petani, buruh, dan nelayan masih membutuhkan strategi pengorganisasian yang lebih masif.
“Pengajian-pengajian di kampung yang diampu ustaz dan ustazah dari pesantren adalah langkah yang relevan. Tapi perlu strategi agar isu-isu keadilan gender, ekologi, dan kemanusiaan bisa dikaitkan dengan realitas sehari-hari masyarakat kecil,” tuturnya.
Menurutnya, potensi agensi sosial masyarakat bawah sangat besar, dan di situlah masa depan KUPI bisa tumbuh.
Termasuk, kolaborasi lintas gerakan antara jaringan ulama perempuan dengan kelompok tani, komunitas buruh, dan aktivis lingkungan akan memperkuat wajah KUPI sebagai gerakan Islam yang tidak hanya berbasis nalar. Tetapi juga praksis keadilan sosial.
Kerja Kolaboratif antara UIN SSC dan KUPI
Sebagai bagian dari upaya memperluas pemahaman metodologi ini, UIN SSC Cirebon melalui lembaga CILEM (Center for Islamic Law and Ethics of Mubadalah) akan berkolaborasi dengan KUPI dalam serangkaian forum akademik pada akhir Oktober 2025.
“Forum ini akan menjadi ruang perbincangan serius mengenai metodologi KUPI. Bagaimana gagasan mubadalah, ma’ruf, dan i’tidal diterjemahkan dalam konteks sosial hari ini baik dalam hukum, pendidikan, maupun gerakan masyarakat,” tegasnya.
Melalui forum-forum tersebut, diharapkan publik terutama kalangan pesantren dan kampus dapat melihat KUPI bukan sekadar gerakan perempuan. Melainkan arus intelektual Islam yang memadukan tafsir moral, praksis sosial, dan keadilan kemanusiaan.
Bahkan, dalam pandangan Wakhit Hasim, KUPI adalah simbol lahirnya kesadaran baru dalam Islam Indonesia yaitu Islam yang berani menafsirkan ulang teks, tapi tetap berpijak pada moral kemanusiaan dan Islam yang menyapa seluruh kelas sosial dengan pesan keadilan yang sama.
“Keunikan KUPI bukan hanya pada siapa yang berbicara. Tetapi pada bagaimana mereka mendengarkan dunia, lalu menjawabnya dengan kasih, ilmu, dan keberpihakan,” tukasnya. []