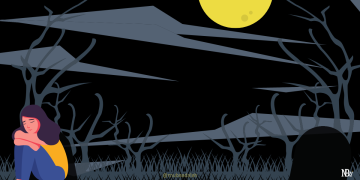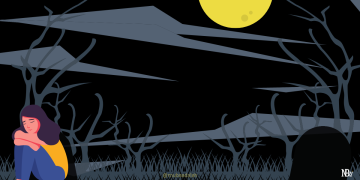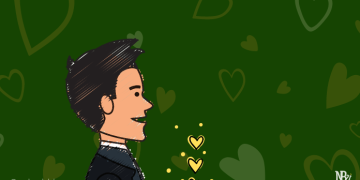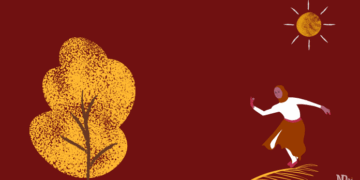Mubadalah.id – Ekofeminisme, topik yang menjadi titik temu antara feminisme dan ekologi, menjadi salah satu sudut pandang kritis yang berupaya mengungkapkan relasi kuasa patriarki, kolonialisme, dan kapitalisme yang merusak alam sekaligus marginalisasi perempuan. Kajian ekofeminisme di Indonesia menjadi relevan karena kerusakan lingkungan kerap berkelindan dengan marginalisasi perempuan—khususnya di pedesaan, pesisir, dan komunitas adat.
Namun, beberapa studi literatur ekofeminisme merujuk ke cara pandang Barat. Sehingga tulisan ini berupaya untuk memantik wacana ekofeminisme sebagai pendekatan dekolonisasi yang berkembang di Indonesia—sekaligus membangun basis teoritis dan praksis berakar pada sejarah, budaya dan perjuangan lokal.
Dekolonisasi dalam kajian ekofeminisme di Indonesia, berarti membangun kembali narasi, pengalaman, dan praktik lokal yang selama ini tersisihkan oleh wacana dominan global. Perjalanan ekofeminisme di Indonesia, bersinggungan dengan sejarah kelam Indonesia, dengan adanya praktik kolonialisme. Yakni berusaha untuk melakukan praktik dekolonisasi sebagai tandingan secara teori maupun gerakan sosial, serta prospek ke depan dalam membangun identitas ekofeminisme yang otentik dan kontekstual.
Ekofeminisme: Akar Global dan Konteks Indonesia
Ekofemisme, lahir kisaran akhir 1970-an dan awal 1980-an. Tokoh yang mempopulerkannya, seperti Françoise d’Eaubonne menghubungkan patriarki dengan kerusakan ekologi. Aliran ini yang kemudian berkembang dengan variasi perspektif: ekofeminisme spiritual (Vandana Shiva), materialis (Maria Mies), hingga post-strukturalis (Ariel Salleh). Meski berbeda, seluruhnya menegaskan bahwa krisis lingkungan tidak bisa dilepaskan dari dominasi patriarki dan kapitalisme yang menempatkan alam serta perempuan sebagai objek eksploitasi.
Namun, ekofeminisme global sering dikritik karena bias Eropa-sentris. Pandangan Vandana Shiva misalnya, meski berasal dari India, tetap dianggap menyederhanakan peran perempuan dalam menjaga alam dan berisiko mengekalkan streotip perempuan sebagai “penjaga alam”. Oleh karena itu, pentingnya dekolonisasi, menggeser pusat epistemologi dari Barat ke Global South, termasuk Indonesia.
Indonesia mempunyai konteks historis dan budaya yang kaya untuk mendukung kajian ekofeminisme. Pertama, warisan kolonialisme Belanda menunjukkan bagaimana kapitalisme ekstraktif menghancurkan ekosistem sekaligus menggeser peran perempuan dalam struktur sosial. Perkebunan kopi, tebu, dan kelapa sawit dikembangkan sejak abad ke-19 meminggirkan perempuan dari akses tanah dan menambah beban kerja domestik mereka.
Kedua, Indonesia mempunyai tradisi kosmologi lokal yang menempatkan manusia, alam, dan perempuan dalam relasi setara. Misalnya, dalam masyarakat Minangkabau,. Sistem matrilineal menjaga kepemilikan tanah ulayat oleh perempuan. Di Bali, konsep Tri Hita Karana menekankan keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Sayangnya, kosmologi lokal banyak terpinggirkan akibat modernisasi dan pembangunan yang bias patriarki.
Ketiga, gerakan perempuan di Indonesia sejak 1980-an mulai mengintegrasikan isu lingkungan. Gerakan anti-tambang di Kendeng, oleh Gunarti dan perempuan Kendeng merupakan contoh nyata bagaimana perempuan mengambil peran sentral dalam melawan kapitalisme ekstraktif. Ekofeminisme hadir sebagai teori sekaligus praksis perlawanan yang lahir dari realitas sehari-hari.
Dekolonisasi Kajian Ekofeminisme: Studi Kasus di Indonesia
Dekolonisasi dalam ekofeminisme Indonesia, tiga hal utama yang menjadi perhatian penting. Pertama, menggeser basis epistemologis. Poin ini menyoal teori Barat sebagai satu-satunya pijakan. Padahal, ekofeminisme di Indonesia perlu merujuk pada kearifan lokal, sejarah kolonial, dan pengalaman perempuan di Indonesia.
Misalnya, pengalaman petani perempuan Jawa dalam melawan monopoli benih atau praktik spiritual masyarakat adat di Kalimantan yang menjaga hutan. Semua ini merupakan pengetahuan ekofeminisme, meskipun tidak selalu memakai istilah akademik.
Kedua, kritik terhadap kapitalisme ekstraktif. Dekolonisasi berarti merespon dan mengkritik struktur global yang mewarisi kolonialisme, seperti industri tambang dan proyek pembangunan besar. Kritik terhadap oligarki ekonomi-politik di Indonesia merupakan bagian dari ekofeminisme.
Perempuan yang menolak pembangunan waduk dan tambang—tanpa memperhatikan aspek pelestarian lingkungan dan menjaga alam, menjadi arah juang untuk lingkungan sekaligus merespon dengan kritik terhadap kolonialisme baru dalam bentuk kapitalisme global.
Ketiga, menghidupkan praksis kolektif. Dekolonisasi menolak individualisme dalam feminisme liberal Barat. Ekofeminisme Indonesia menekankan pada kolektivitas. Seperti gotong royong, solidaritas komunitas, dan aksi bersama. Aksi ibu-ibu Kendeng yang menyemen kaki mereka di Istana Negara tahun 2016, mereka tidak berbicara tentang “hak individu” semata, melainkan keberlangsungan hidup komunitas.
Studi kasus di Indonesia, ekspansi gerakan ekofeminisme melalui pendekatan dekolonisasi. Misalnya: Pertama, Kartini Kendeng menandakan gerakan perempuan di Jawa menolak pendirian pabrik semen. Mereka menggunakan simbol tubuh perempuan dan kesuburan tanah sebagai basis perlawanan. Ini merupakan contoh dekolonisasi, karena narasi mereka berakar pada kearifan lokal tentang tanah sebagai “ibu” yang melahirkan kehidupan.
Kedua, gerakan perempuan adat di Kalimantan, menunjukkan perempuan Dayak terlibat aktif dalam menjaga hutan dari perampasan lahan oleh perusahaan sawit dan tambang. Mereka tidak hanya berperan sebagai “korban”, melainkan sebagai pemimpin dalam advokasi hukum dan aksi langsung.
Ketiga, solidaritas nelayan perempuan di Pesisir Utara Jawa, menghadapi dampak reklamasi dan industrialisasi laut. Mereka melawan, memperjuangkan kepentingan hak ekonomi serta melestarikan laut sebagai ruang hidup komunitas. Kasus tersebut menunjukkan bahwa ekofeminisme Indonesia tidak semata teori impor, melainkan ekspresi dekolonisasi berakar dari realitas lokal.
Tantangan dan Prospek
Meski mengalami perkembangan, ekspansi ekofeminisme di Indonesia menghadapi tantangan. Pertama, dominasi wacana pembangunan negara yang masih bias maskulin dan kapitalistik. Pembangunan infrastruktur besar seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) misalnya, mengabaikan suara perempuan dan masyarakat adat yang tergusur.
Kedua, resistensi interal dalam gerakan feminis sendiri. Tidak semua feminis di Indonesia sepakat dengan pendekatan ekofeminisme, karena dianggap terlalu “romantis” terhadap alam atau mengesampingkan isu kelas. Ketiga, keterbatasan akses perempuan lokal pada ruang akademik dan kebijakan. Banyak narasi perempuan dan akar rumput tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga terpinggirkan dalam kajian formal.
Namun, prospeknya tetap besar. Ekofeminisme di Indonesia menjadi perspektif global yang unik, karena menawarkan integrasi antara kosmologi lokal, gerakan sosial, dan kritik dekolonial. Jika dikembangkan serius, Indonesia menjadi pusat wacana ekofeminisme global yang lebih plural dan kontekstual.
Sehingga ekspansi kajian ekofeminisme di Indonesia dengan pendekatan dekolonisasi bukan hanya kebutuhan akademik, melainkan strategi politik dan kultural.
Dengan menggali pengalaman lokal, kritik terhadap kapitalisme ekstraktif, dan memperkuat solidaritas komunitas, ekofeminisme Indonesia tampil sebagai kekuatan transformatif. Bentuk dekolonisasi sejati adalah membangun pengetahuan dari bawah, untuk melawan penindasan, dan memperjuangkan kehidupan yang adil bagi manusia dan alam. []