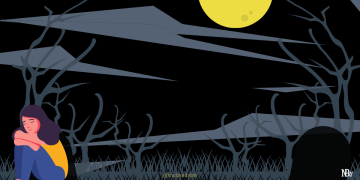Mubadalah.id – Saya dibuat kecewa oleh Fedi Nuril di film Pangku. Awal nya saya kira, dia akan mematahkan stigma spesialis aktor poligamis. Sebagai Hadi, sopir truk pengangkut ikan hasil laut melakonkan peran sebagai laki-laki tenang, penuh empatik, dan baik hati. Dia hadir sebagai penolong dalam kehidupan Sartika yang terpuruk. Tapi ujungnya, poligamis juga.
Fedi Nuril adalah Hadi yang ditinggal istri merantau menjadi pekerja migran, dan dia kawin lagi. Masih tentang Poligami yang terbungkus sangat halus dengan balutan, menolong atau kemanusiaan. ‘Aku mau punya anak, dan kamu pengen punya suami’. Makin kuat deh stigma media ke dia sebagai ‘Duta Poligami Layar Lebar’.
Beberapa review film dan iklan Pangku memaksa saya, sore-sore meluncur ke bioskop satu-satunya yang ada di Metro. Padahal lagi banyak list pekerjaan yang harus dituntaskan. Karena bingung mana dulu yang dikerjakan, pilihannya jatuh pada yang tidak ada dalam list, yaitu NONTON, dan sendirian lagi.
Mulanya, saya mengira Pangku, seperti film-film yang lain, akan menonjolkan isu ‘pasar seks’ sebagai daya tarik film. Tapi, saya salah. Reza Rahadian sang sutradara, dengan sangat halus meletakkan seks kelompok marginal untuk mengkritik struktur sosial tentang kemiskinan dengan setting warung kopi pinggir Pantura.
Warung kopi yang menjadi panggung tempat hidup para perempuan yang berusaha bertahan. Setting lokal realis yang sempit, tapi justru mampu menguatkan keterhimpitan perempuan di ruang-ruang sosial.
Kisah tentang Sartika
Pangku berkisah tentang Sartika, perempuan muda yang hamil dan pergi ke Pantura demi harapan, lalu menemukan dirinya bekerja di warung kopi pangku. (Saya masbuq 10-an menit jadi ga tau cerita awal kehamilannya).
Awalnya, bekerja di warung kopi pangku bukan pilihan, Tika sempat bekerja menjadi buruh sawah. Tapi karena desakan kebutuhan stok beras untuk menyambung hidup Bayu, anaknya, Tika menyerah pada takdir, membiarkan tubuhnya dipangku oleh pelanggan warung kopi.
Cerita sederhana yang membuka spektrum sosial yang komplek dan berkelindan, bagaimana ketubuhan perempuan terjalin dengan kemiskinan struktural. Dan bagaimana ketahanan Perempuan muncul dalam situasi yang mereduksi pilihannya. Tika terjatuh dan terpuruk bertubi-tubi, tapi di saat yang sama dia bangkit untuk melanjutkan hidup.
Film ini adalah potret realis yang alurnya saya rasakan begitu lambat. Ruang sempit, dialog yang hemat, tapi gestur tubuh para aktor yang berbicara banyak. Gaya pengisahan yang minim dialog dan lambat ini justru memperkuat bahwa tubuh itu sendiri menceritakan pengalaman kepayahan, bukan kata-kata yang selalu menjelaskan.
Penonton seperti harus bekerja keras memaknai setiap gestur pemain. Berjalan gontai, duduk bengong dengan tatapan kosong, tidur meringkuk untuk menggambarkan ketidaknyamanan hidup. Hening tanpa dialog menjadi medium untuk memperlihatkan tubuh yang lapar, lelah, tapi terus bergerak mencari ruang bertahan.
Komodifikasi Tubuh Perempuan
Bagian penting yang dibuka oleh Pangku adalah bagaimana tubuh menjadi alat reproduksi sosial-ekonomi. Komodifikasi tubuh Perempuan, bukan hanya melahirkan anak, tetapi juga berfungsi sebagai komoditas di pasar informal. Ketika perempuan duduk di pangkuan pelanggan, ada transaksi yang lebih dari sekadar secangkir kopi.
Yang menarik dari cara Reza Rahadian memperlihatkan Pangku, bukan pada moralitas individual semata, melainkan konsekuensi dari struktur ekonomi yang menyisakan sedikit pilihan bagi perempuan miskin. Ketika lapangan kerja formal tak tersedia, maka tubuh menjadi salah satu modal terakhir. Mangsedih sih.
Sosok Maya-Chistin Hakim aktor gaek yang tidak kita ragukan lagi performanya. Pemilik warung, perempuan yang tidak cukup baik juga secara ekonomi, tapi relatif lebih berdaya dan memiliki usaha kecil, untuk bertahan hidup.
Anggaplah dia pemimpin perempuan di komunitasnya, karena nasibnya lebih baik dari Tika dan Perempuan-perempuan lain yang muncul sebagai figuran. Dia seperti menjadi ibu yang punya bahu untuk sandaran Tika dan teman-temannya.
Pangku secara jujur menyatakan bahwa kepemimpinan perempuan tidak otomatis menghapus relasi subordinasi. Terkadang ia juga berfungsi di dalam ekosistem yang mempertahankan norma ketidakadilan demi kebutuhan pasar.
Di sini terlihat Maya begitu mengayomi Tika dan teman-temannya, tapi logika ekonomi memaksanya untuk meminta mereka rela “dipangku” demi keberlanjutan hidup dan masa depan anak. Pilihan yang bukan pilihan inilah yang menandai kemiskinan struktural.
Pilu yang Menyakitkan
Hal lain yang menarik dari Pangku adalah alurnya tidak menjual kepiluan sebagai tontonan. Film ini memilih nada humanis yang merayakan ketegaran tanpa melucuti kompleksitas penderitaan. Saya tidak menangis seperti biasanya saat nonton film-film drama, tapi saya merasakan pilu yang menyakitkan.
Reza Rahadian dengan sangat cerdik menampilkan bahwa film ini bukan untuk sekadar menggambarkan korban, melainkan memetakan kondisi yang membuat korban itu harus memilih. Kritik sosialnya halus tapi tajam: ia menempatkan penonton di posisi melihat struktur atau konteks yang bekerja, bukan hanya menilai moral individu.
Itu juga yang membuat saya penasaran ketika membaca beberapa pengamat menyebut film ini sebagai karya yang menghormati akar realitas para karakternya. Dan Saya menvalidasinya, tidak menonjolkan pengalaman aktor secara personal, tapi pada sistem yang berkelindan.
Jujurly, yang bikin saya penasaran dan bikin saya harus nonton film pangku ini adalah review kaka Kalis Mardiasih di IG nya. Dia mengapresiasi Reza bertubi-tubi bukan karena kegantengannya, tapi kelihaiannya memahami root cause ketidakadilan yang dialami para karakter.
Bahwa pesisir, kemiskinan, dan kultur lokal berperan sebagai latar yang bukan sekadar setting tetapi agen pembentuk takdir. Saya suka kata-kata kakak Kalis yang dibold “…..tapi bagaimana memartabatkan kelompok-kelompok marginal dalam film Pangku”. Terimakasih kaka kalis.
Akhirnya, Pangku mengajukan pesan etis yang penting, melihat perempuan dan ketubuhannya bukan sekadar melihat subjek individual, tetapi memandangnya dalam kelindan ketidakadilan sosial. Tubuh yang “dipangku” dalam film adalah alarm bagi kita, mengingatkan bahwa martabat manusia terancam bukan hanya oleh tindakan kriminal dan kejahatan semata, melainkan oleh struktur yang menutup akses dan kesempatan.
Balik ke Fedi Nuril, pengen liat dia ganti peran biar ga jadi cowok poligamis terus. []