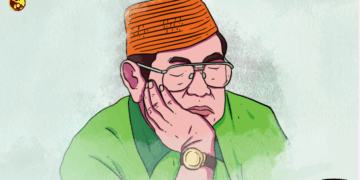Mubadalah.id — Pluralisme kerap jadi kata yang menakutkan, karena sebagian orang mengiranya sebagai upaya menyamakan semua agama.
Padahal, menurut Fahmina Institute, pluralisme tidak bicara soal penyamaan agama. Ia bicara soal pengakuan bahwa manusia memang hidup dalam dunia yang beragam, dan keberagaman itu bukan hal menakutkan, tapi realitas yang harus kita terima.
Cara pandang ini lahir dari pengalaman pahit yang berulang dalam sejarah Indonesia. Banyak konflik pecah karena perbedaan seringkali menjadi bahan bakar kebencian.
Bahkan, sentimen agama dan kelompok sering jadi alasan untuk memisahkan ikatan sosial yang seharusnya kokoh. Di titik ini, Fahmina menempatkan pluralisme sebagai jalan keluar, bahwa ia bukan teori besar, tapi sikap sosial—kesediaan membuka ruang temu, dialog, dan kerja bersama.
Fahmina memulainya dari tempat yang paling dekat dengan denyut masyarakat, yakni Cirebon. Sejak awal, para pegiatnya mendatangi pesantren dan komunitas keagamaan untuk menawarkan sudut pandang baru.
Pluralisme tahap pertama, bagi mereka, adalah upaya untuk saling bertemu, duduk satu meja dengan pemeluk agama lain, menyingkirkan prasangka, dan menegaskan bahwa dialog dengan mereka yang berbeda tidak akan membuat seseorang kehilangan imannya.
Forum Lintas Iman
Langkah dasar ini perlahan orang-orang terima. Sejumlah sepuh pesantren mulai mau hadir di forum lintas iman. Dari pertemuan-pertemuan itu, Fahmina belajar bahwa pluralisme adalah ruang perjumpaan yang bisa mereka terima dengan baik.
Meski begitu, ketika pluralisme masuk ke level aksi—yakni membela hak kelompok minoritas yang distigma atau dipersekusi—temboknya menjadi lebih tebal. Komunitas seperti Ahmadiyya Muslim Community atau penghayat lokal Dayak Bumi Segandu, masih sering dipandang sebelah mata.
Diskusi antariman mungkin mulai dibolehkan, tetapi bicara soal perlindungan hak mereka? Banyak pihak masih takut dan ragu untuk melindunginya.
Para kiai sepuh Cirebon yang pernah menyaksikan kerasnya konflik antaragama di daerah lain, justru bersuara lebih dulu. KH. Syarif Usman Yahya pernah mengucapkan pesan yang terus dikutip hingga hari ini: “Tolong, jangan sampai Cirebon dijadikan seperti Poso.”
Kalimat itu adalah pengingat bahwa percikan konflik bisa bermula dari hal kecil—stigma, pembubaran, pelarangan—yang dibiarkan tanpa pembelaan.
Karena itulah, Fahmina mulai menggeser strategi. Mereka sadar, perubahan sosial tak bisa berhenti di forum pertemuan. Ia harus masuk ke gerakan, agar pluralisme benar-benar bisa menjadi strategi untuk menerima semua perbedaan. []