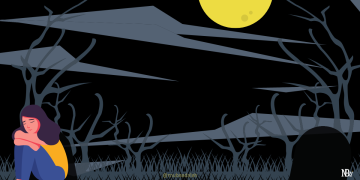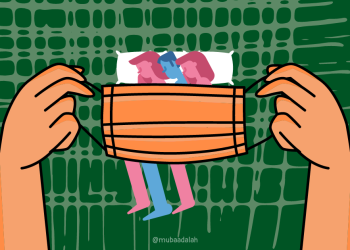Teks Hadits:
عَنْ أَبِي مُوسَى الأشعري رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ وَلِيدَةٌ فَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، وَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ. (صحيح البخاري، كتاب النكاح، رقم الحديث: 5139).
Terjemah:
Dari Abu Musa, dari Nabi Saw bersabda: “Barang siapa (seorang laki-laki) yang memiliki seorang budak perempuan, lalu ia mengajarinya dengan baik, mendidiknya dengan baik, kemudian memerdekakannya dan menikahinya, maka baginya dua pahala.” (HR. al-Bukhari, Kitāb an-Nikāḥ, no. 5139).
Pengantar Awal
Mubadalah.id – Hadits dalam Ṣaḥīḥ al-Bukhārī ini lazim menjadi dalil ulama tentang keutamaan memperlakukan budak—khususnya budak perempuan—secara manusiawi. Mengajarinya, membinanya secara etis, lalu memerdekakannya. Ia juga menjadi dasar kebolehan sekaligus kebaikan menikahi mantan budak setelah dimerdekakan.
Metode Mubadalah memaknai ulang teks ini. Berdialog dengan khazanah klasik dan pembacaan kontemporer—agar pelajarannya lebih berakar pada visi kerahmatan Islam dan misi akhlak mulia, sekaligus relevan bagi konteks kekinian. Judul yang mungkin bisa kita usulkan untuk makna dasar dari teks hadits ini adalah: “Mengajar dan Mendidik untuk Memerdekan Manusia dalam Perspektif Hadits”. Kaidah kunci pendekatan Mubadalah, dalam proses pemaknaan ini, adalah:
العِبْرَةُ بِعُمُومِ الرِّسَالَةِ لَا بِخُصُوصِ الْخِطَابِ وَالْمُخَاطَبِ
Yang dipegang ialah keumuman pesan, bukan kekhususan redaksi atau siapa yang disapa.
Dengan kaidah ini, pesan universal hadis harus kita identifikasi terlebih dahulu, lalu relasi subjek–objeknya kita kenali dan kita kembangkan. Sehingga seluruh pihak—terutama laki-laki dan perempuan—sama-sama tersapa untuk mewujudkan dan merasakan kemaslahatan yang dikandungnya. Selain itu terhindar dari kemudaratan yang dilarangnya, —baik di tingkat individu, keluarga, lembaga, organisasi, negara, maupun hubungan global.
Pesan Utama Hadits
Kerja pokok Metode Mubadalah ialah menemukan makna dasar (predikat etis) dari teks, yang selaras dengan visi kerahmatan dan misi akhlak mulia. Pada aras prinsip, seluruh nash (al-Qur’an dan hadits) berporos pada dua hal: mewujudkan kebaikan (ījād al-maṣāliḥ) dan menghapus keburukan (maḥw al-mafāsid).
Dalam hadits ini, pesan dasar terpetakan melalui empat tindakan:
- فَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا – mengajarinya dengan baik,
- وَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا – mendidiknya (membina adab) dengan baik,
- ثُمَّ أَعْتَقَهَا – kemudian memerdekakannya,
- فَتَزَوَّجَهَا – lalu menikahinya.
Keempatnya membentuk lintasan etik dari relasi kuasa menuju transformasi kemanusiaan. Dalam bingkai tiga nilai Mubādalah—karāmah (martabat), ‘adālah (keadilan relasional), dan maṣlaḥah (kebaikan bersama. Tindakan ketiga, memerdekakan, adalah inti yang mengikat seluruh rangkaian.
Karena itu, mengajar, mendidik, dan menikahi harus kita pahami sebagai instrumen yang melayani tujuan pemerdekaan. Menumbuhkan kemandirian, menjaga kehormatan, memberi perlindungan dari kezaliman, serta memenuhi kebutuhan dasar pihak yang dibina.
Konsekuensinya, menikahi mantan budak bukan kelanjutan dari pola kepemilikan, melainkan puncak pengakuan kemanusiaan. Yakni memasuki kemitraan (zawāj) yang setara. Maka, mengajar dengan baik dan mendidik dengan baik tidak boleh berorientasi pada penguasaan, pembatasan, atau hegemoni. Demikian pula pernikahan tidak boleh menjadi kanalisasi dominasi. Semua itu bertentangan dengan pesan pemerdekaan (i‘tiq) yang menjadi inti hadits.
Rujukan Qur’ani
Sejalan dengan itu, rujukan Qur’ani tentang tujuan pernikahan—sakinah, mawaddah, wa raḥmah (QS. al-Rūm 30:21)—menegaskan bahwa zawāj adalah kemitraan aktif yang dijalankan dengan mīthāqan ghalīẓan (perjanjian kokoh). Lalu mu‘āsyarah bi al-ma‘rūf (perlakuan yang baik), tashāwur (musyawarah), dan tarāḍī (kerelaan timbal balik).
Dengan menempatkan pemerdekaan sebagai poros, tiga nilai Mubādalah terwujud secara operasional. Karāmah (martabat manusia dijunjung), ‘adālah (yang kuat memberdayakan yang lemah), dan maṣlaḥah (kebaikan menjadi milik bersama, kedua belah pihak menjadi pelaku sekaligus penerima kebaikan). Hal ini selaras dengan misi Islam yang transformatif untuk melindungi dan memberdayakan al-mustaḍ‘afīn (QS. 4:75).
Dengan demikian, memerdekakan di sini bermakna kerja transformasi melalui pengajaran, pembinaan karakter, dan—bila dipilih sebagai istri. Pernikahan yang berlandaskan kemitraan, dari kondisi tak atau kurang bermartabat menjadi bermartabat, dari lemah menjadi kuat, dari tak atau kurang maslahat menjadi berdaya dan berkemaslahatan. Transformasi ini menyiapkan seseorang menjadi subjek yang kapabel mengemban amanah kekhalifahan. Aktif mewujudkan kebaikan (ījād al-maṣāliḥ) dan meniadakan keburukan (maḥw al-mafāsid).
Mengenali Subjek–objek pada Konteks Awal
Dalam teks hadits ini, subjek yang kita sebut adalah rajulun—seorang laki-laki merdeka—yang melakukan serangkaian tindakan etis dan transformatif: mengajar, mendidik karakter, memerdekakan, dan menikahi. Sementara objek dari tindakan tersebut adalah walīdah, budak perempuan, yang dalam konteks sosial Arab abad ke-7 berada dalam posisi sosial paling rentan. Tidak merdeka, terbatas akses pendidikannya, lemah secara ekonomi, dan tanpa jaminan perlindungan masa depan.
Pertanyaan muncul: mengapa yang disebut secara eksplisit adalah laki-laki?
Jawabannya terletak pada realitas sosial saat itu. Laki-laki merdeka memang memiliki otoritas ekonomi, sosial, dan hukum untuk melakukan tindakan-tindakan yang disebutkan hadits. Bahkan, dalam masyarakat tersebut, banyak laki-laki memiliki budak perempuan dan sebagian tertarik menikahinya.
Dalam konteks inilah, Nabi Saw menegaskan orientasi etis dari tindakan itu. Bahwa relasi tersebut harus bertransformasi dari hubungan kepemilikan menuju hubungan kemanusiaan, dari eksploitasi menuju pemberdayaan, dan dari subordinasi menuju kemitraan yang bermartabat.
Dengan demikian, penyebutan laki-laki (rajulun) bukan bentuk pengkhususan ajaran, tetapi strategi komunikatif yang sesuai dengan struktur sosial ketika hadits itu tersampaikan. Nabi Saw mengarahkan para laki-laki agar mempraktikkan prinsip-prinsip etik Islam dalam relasi yang penuh ketimpangan sosial. Yakni menjadikan relasi tersebut sarana pemerdekaan dan pemberdayaan, bukan penguasaan.
Selain itu, redaksi hadits ini juga dapat kita baca sebagai bentuk pendidikan sosial yang progresif. Mendorong transformasi dari tindakan sederhana menuju tindakan etis yang lebih tinggi. Bisa jadi pada masa itu sebagian laki-laki hanya mengajar atau mendidik budak perempuannya, sebagian lain hanya ingin menikahi tanpa memerdekakan.
Hadits ini menaikkan standar moral tersebut. Jangan berhenti di pendidikan atau pernikahan, tetapi wujudkan pemerdekaan sebagai puncak etika kemanusiaan. Dengan demikian, sabda Nabi Saw ini tidak hanya mendidik budak perempuan agar merdeka, tetapi juga mendidik laki-laki agar menjadi subjek etis yang bertanggung jawab terhadap transformasi sosial di sekitarnya.
Meluaskan Subjek–objek
Langkah penting setelah menemukan pesan utama teks dalam Metode Mubadalah adalah meluaskan cakupan subjek dan objek. Prinsip dasarnya, pesan universal dari suatu teks tidak berhenti pada siapa yang kita sebut secara literal, melainkan berlaku bagi semua pihak yang dapat merealisasikan nilai etis yang terkandungnya.
Dalam hadits ini, kata rajulun tidak harus kita pahami sebagai identitas biologis yang eksklusif. Tetapi sebagai simbol bagi siapa pun yang memiliki kapasitas dan posisi sosial untuk melakukan kerja-kerja etis transformatif.
Dengan demikian, rajulun dapat mencakup perempuan merdeka yang mengajarkan, mendidik, dan memberdayakan orang lain hingga merdeka. Fokusnya bukan pada jenis kelamin pelaku, melainkan pada tindakan etis yang dilakukannya. Karena pahala ganda dalam hadits ini diberikan kepada pelaku kebaikan, bukan kepada laki-laki sebagai jenis kelamin tertentu.
Begitu pula dengan walīdah, objek yang disebut dalam teks. Ia tidak harus kita maknai semata-mata sebagai budak perempuan, tetapi juga bisa melambangkan setiap pihak yang berada dalam posisi lemah, tertindas, atau belum berdaya—termasuk laki-laki budak pada masa itu.
Dengan demikian, makna hadits ini meluas menjadi seruan universal agar siapa pun yang memiliki kelebihan pengetahuan, status, atau sumber daya menggunakan kelebihannya untuk mendidik, melindungi, dan memerdekakan pihak lain dari segala bentuk ketergantungan dan penindasan.
Perluasan makna ini tidak hanya menjaga relevansi hadits, tetapi juga menjaga ruh Islam sebagai ajaran yang terus menumbuhkan keadilan dan kemaslahatan dalam setiap ruang dan waktu. Fokusnya bukan pada siapa yang kita sebut, tetapi pada nilai yang diperintahkan untuk diwujudkan.
Kontekstualisasi Makna
Apabila pesan utama hadits ini adalah memerdekakan manusia dalam pengertian sosial, intelektual, dan moral, maka ketika sistem perbudakan telah terhapus secara historis, makna pemerdekaan harus kita terapkan dalam berbagai bentuk relasi sosial kontemporer.
Relasi antara majikan dan buruh, guru dan murid, penguasa dan rakyat, suami dan istri, lembaga dan masyarakat, hingga negara kaya dan negara miskin. Seluruhnya dapat menjadi medan aktualisasi pesan etis hadits ini. Dalam setiap bentuk relasi tersebut, nilai yang harus kita wujudkan adalah pemberdayaan, bukan dominasi; perlindungan, bukan eksploitasi; kemitraan, bukan ketergantungan.
Hadis ini juga dapat kita baca sebagai kritik terhadap struktur sosial modern yang masih menyisakan bentuk-bentuk “perbudakan baru”—seperti eksploitasi ekonomi, ketidakadilan pendidikan, diskriminasi gender, atau ketimpangan global. Dalam semua konteks ini, pihak yang memiliki kekuatan atau sumber daya—baik individu, lembaga, maupun negara—dituntut untuk berperan sebagai subjek etis yang berkomitmen pada pemerdekaan pihak lain.
Dengan demikian, pesan hadis ini dapat kita aplikasikan pada tataran kelembagaan dan global. Lembaga pendidikan yang memberdayakan kelompok marginal, organisasi sosial yang mendidik masyarakat rentan, atau negara yang membantu negara lain mencapai kemandirian dan kesejahteraan. Semua bentuk tindakan tersebut merupakan aktualisasi dari kerja etis “mengajar, mendidik, memerdekakan, dan menikahkan” dalam makna moralnya. Membentuk hubungan yang manusiawi, adil, dan saling menumbuhkan.
Kesimpulan
Hadis tentang laki-laki yang mengajar, mendidik, memerdekakan, dan menikahi budak perempuan bukan semata teks hukum mengenai status perbudakan dan pernikahan, melainkan sebuah teks etis tentang transformasi kemanusiaan. Dengan pembacaan melalui Metode Mubādalah, makna literal hadits ini berkembang menjadi pesan universal tentang pembebasan, pemberdayaan, dan kemitraan yang berkeadilan.
Dalam konteks awal, hadits ini berfungsi sebagai pendidikan moral bagi laki-laki agar menggunakan kekuasaan dan otoritas sosialnya untuk membebaskan. Bukan mengeksploitasi perempuan yang berada dalam posisi lemah. Pada tahap perluasan, pesan etis ini menjangkau seluruh manusia—laki-laki maupun perempuan. Yakni untuk berperan sebagai subjek moral yang memerdekakan sesama dan menumbuhkan kemaslahatan bersama.
Dalam konteks kekinian, makna pemerdekaan dalam hadits ini relevan untuk seluruh bentuk relasi sosial yang menuntut keadilan dan kesalingan. Baik di tingkat individu, keluarga, lembaga, organisasi, negara, maupun hubungan global. Prinsip yang kita tekankan adalah bahwa segala bentuk kelebihan. Baik berupa pengetahuan, kekayaan, kedudukan, maupun otoritas—harus berfungsi untuk memerdekakan, bukan menindas; membangun kemitraan, bukan menciptakan hierarki.
Dengan demikian, hadits ini menegaskan salah satu prinsip mendasar Islam. Bahwa rahmat dan akhlak mulia harus terwujud dalam relasi sosial yang memuliakan manusia. Metode Mubadalah menghidupkan kembali pesan tersebut dengan cara menempatkan setiap relasi manusia sebagai ruang pemerdekaan, kesalingan, dan kemaslahatan bersama. Baik dalam lingkup pribadi, keluarga, kelembagaan, kenegaraan, maupun kemanusiaan global. []