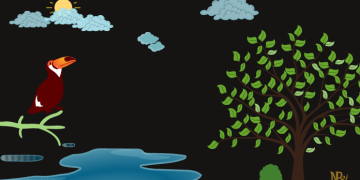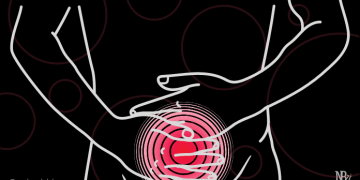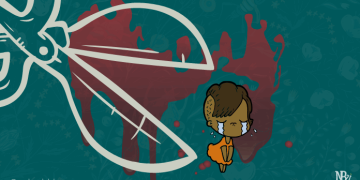Mubadalah.id – Dalam drakor When Life Gives You Tangerines, fenomena eldest daughter syndrome diangkat dengan apik. Tokoh utama, Aesun, adalah putri sulung perempuan penyelam atau Hanyeo. Saat Aesun kecil kembali hidup dengan ibunya, ia membantu hampir semua pekerjaan rumah.
Begitu pula saat ibunya meninggal. Aesun kecil berkali-kali berniat keluar dari rumah ayah tirinya untuk mengejar mimpi. Tapi rasa ketidaktegaan melihat adik-adiknya yang masih kecil serta bujukan dari ayah tirinya menggagalkan niat baiknya.
Aesun kecil memasakkan makanan untuk keluarga itu. Menyuapi kedua adiknya sebelum atau bersamaan dengan waktu makannya. Ia juga merawat kebun kubis sebagai sumber penghasilan keluarga. Ia tumbuh remaja hingga dewasa dengan beban yang selalu ada di pundaknya.
Setelah menikah, anak pertama perempuan Aesun, Yang Geum Young, juga tumbuh dengan melihat ibunya yang selalu mengalahkan dirinya sendiri demi orang lain. Geum Young menuangkan kuah sisa soup yang tersisa ke dalam mangkoknya setelah membaginya kepada calon suami, mertua, dan orang tuanya. Persis seperti yang dilakukan Aesun muda ketika ia hanya mendapat kuah sop setelah membagikan isinya kepada seluruh anggota keluarga.
Lelah Menjadi Anak Pertama
Suatu kali ketika orang tua Geum Young tertimpa masalah keuangan, ia berinisiatif mencari pinjaman untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sebagai anak pertama, Geum Myoung merasa punya beban lebih untuk membantu keluarganya. Namun, bukannya merasa lega setelah membantu, Geum Myoung justru mengeluarkan tumpukan gunung es emosi yang selama ini ia pendam.
Ia merasa lelah menjadi anak pertama. Ia merasa terbeban dengan sebutan pilar keluarga dan naga dari sungai. Ia muak dengan semua sebutan tersebut. Ia menyadari ibunya tulus memberi apapun yang ia inginkan, namun diam-diam ia memendam rasa bersalah sebab telah membuat orang tuanya kehilangan rumah demi keinginannya kuliah di luar negeri.
Scene tersebut tentu amat mudah dipahami oleh kita yang berstatus anak sulung perempuan. Ketika ada hal sulit yang dihadapi keluarga, segera kita memutar otak, mencari cara untuk menyelamatkan keluarga. Kita mengerahkan segala yang kita miliki asal keluarga kita selamat. Namun, begitu masalah terlewati, tiba-tiba kita merasa lelah dan sedih.
Apa itu Eldest Daughter Syndrome?
Melansir dari artikel Eldest Daughter Syndrome: The Invisible Load No One Talks About, Eldest Daughter Sindrome merujuk pada beban tak kasat mata yang tertanggung oleh anak pertama perempuan. Meski terasa tak adil, memang kebanyakan anak sulung perempuan menanggung beban yang lebih berat dari adik-adiknya yang lain.
Hal ini salah satunya penyebabnya karena pola pengasuhan di masa kanak-kanak. Umumnya anak sulung perempuan mendapat tugas lebih dari orang tuanya. Ia diminta menjaga adik-adiknya dan berupaya membantu ibunya mengerjakan tugas domestik.
Anak sulung perempuan tumbuh dengan keyakinan bahwa dia memiliki tanggung jawab lebih besar terhadap adik-adiknya. Ia merasa harus jadi contoh yang baik, tidak boleh gagal, dan harus mencapai cita-citanya. Ia juga selalu memaksa diri sendiri untuk mengalah dalam perdebatan kecil maupun pertengkaran besar sebab ia lebih tua. Dan memang itulah yang dunia ajarkankepadanya.
Pada keluarga yang mengalami disfungsi fisik atau psikis, seringkali seorang ibu membagi bebannya kepada anak sulung perempuan. Ibu menganggap putri sulungnya sebagai teman dekat yang bisa jadi tempat berbagi beban domestik yang ia tanggung.
Kondisi lingkungan yang ia hadapi mendidiknya menjadi pribadi yang selalu menuntut diri sendiri untuk melakukan sesuatu untuk orang lain. Bahkan jika itu mengorbankan kepentingannya sendiri.
Pengalaman Serupa sebagai Anak Sulung Perempuan
Saya pun pernah mengalami pengalaman serupa. Saat keluarga mengalami masalah finansial, sebagai kakak perempuan pertama yang saat itu sudah bekerja, spontan saya merasa perlu mengambil alih tanggung jawab biaya sekolah adik-adik saya.
Tentu ini tidak menjadi masalah besar sebab saya hanya perlu mengorbankan sedikit tabungan demi pendidikan adik saya. Namun, pola mengambil tanggung jawab lebih ini terbawa hingga saya menjalani hidup dan kegagalan di fase berikutnya.
Saat relasi romantis gagal dan kucing kesayangan mati, saya sibuk menyalahkan diri sendiri. Suara-suara di kepala saya berandai-andai, jika saja saya tak memilih langkah kemarin mungkin kucing saya masih selamat. Jika saya berusaha lebih keras mungkin hasilnya akan berbeda.
Karena berlangsung amat lama dan menganggu aktivitas sehari-hari, saya memutuskan mengunjungi psikolog. Setelah ngobrol panjang lebar termasuk riwayat dan latar belakang keluarga, psikolog menemukan pola yang sama pada diri saya.
Saya memiliki kecenderungan untuk menyalahkan diri sendiri saat semuanya tidak terjadi sesuai yang diharapkan. Hal ini salah satunya berdasarkan karena peran saya sebagai anak sulung perempuan di keluarga. Saya terbiasa memiliki tanggung jawab lebih banyak daripada saudara yang lain.
Padahal ada banyak sekali hal di luar kendali kita. Merawat hubungan pun juga butuh tanggung jawab kedua belah pihak. Dan jika semuanya berakhir berbeda dengan yang kita harapkan, itu tidak berarti bahwa kita gagal.
Meskipun benang merahnya ketemu, tak lantas saya benar-benar bisa mentas dari pergumulan batin yang saya alami. Perlu latihan kesadaran lebih banyak sembari belajar melepas sesuatu yang di luar kendali kita. Serta menyadari bahwa tidak semua masalah itu menjadi tanggung jawab kita.
Intergenerational Trauma
Selain berpotensi menanggung beban yang lebih berat, anak sulung perempuan yang memiliki ibu sebagai anak pertama juga rentan menanggung beban trauma antar generasi.
Trauma dari ibu sebagai anak pertama perempuan yang memiliki luka pengasuhan dapat dengan mudahnya terwariskan kepada anak pertama perempuan. Jika ibu pernah mengalami kekerasan verbal, fisik, maupun pengabaian emosi secara tidak sadar ia akan mengulang pola yang sama saat mengasuh anaknya.
Selain itu, ibu yang tumbuh dalam keluarga patriarki dan selalu meminggirkan perempuan juga cenderung menjadi contoh utama bagi anak perempuannya. Bagaimana tidak, dengan mata kepalanya sendiri, anak perempuan merekam bagaimana cara ibunya memprioritaskan orang lain dan menomorduakan diri dia sendiri.
Akhirnya ia akan tumbuh dengan keyakinan untuk bisa diterima ia harus siap kehilangan diri sendiri. Baginya menjadi perempuan dewasa artinya selalu mengorbankan diri demi orang lain.
Memiliki trauma yang terwariskan dari ibu sebagai anak pertama perempuan tentu bukan salah kita. Namun, mengelola trauma dan menyembuhkan diri dari pengulangan rasa yang sama adalah tanggung jawab kita. []