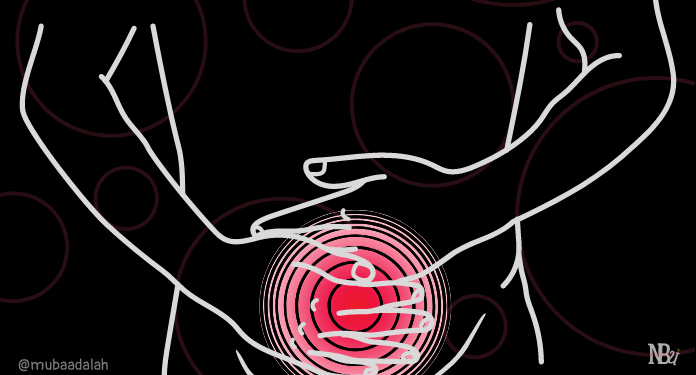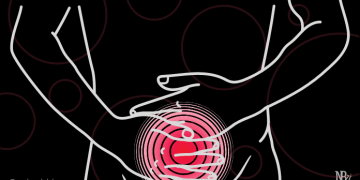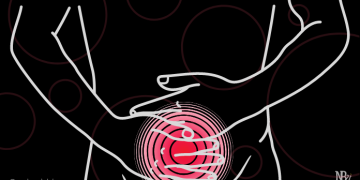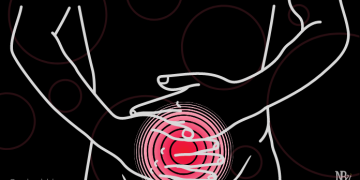Mubadalah.id – Masalah haid, nifas, dan istihadhah dalam fiqh memperoleh perhatian yang begitu luar biasa dari para fuqaha. Banyak kitab yang khusus ditulis untuk membahas masalah ini. Di antara ulama yang menghasilkan satu jilid besar tentang masalah haid, nifas, dan istihadhah ini adalah Imam Haramain dan Abu al-Faraj al-Darimi.
Secara umum dapat kita katakan bahwa paradigma dasar fiqh tentang haid, nifas, dan istihadhah merupakan kelanjutan dari ajaran yang terdapat dalam al-Qur’an dan al-hadits. Artinya fiqh Islam tidak memposisikan perempuan yang sedang haid, nifas dan istihadhah sebagai kelompok manusia yang kotor dan perlu diisolasi.
Fiqh memandang status mereka sama dengan orang yang sedang mengalami hadats besar (suatu kondisi yang mewajibkan seseorang untuk mandi wajib sebelum melakukan ibadah tertentu) seperti orang yang habis bersetubuh dan laki-laki yang mengeluarkan sperma.
Dalam perspektif fiqh, hadats baik besar maupun kecil (suatu kondisi yang mewajibkan seseorang untuk berwudhu sebelum melakukan ibadah tertentu seperti habis kencing, buang air besar, tidur) dianggap sebagai sesuatu yang alamiah, temporer dan aksidental dan dialami oleh setiap manusia, sehingga hadats sama sekali bukan hal yang dipandang negatif.
Dengan menempatkan haid, nifas, dan istihadhah sejajar dengan kondisi-kondisi hadats yang lain. Maka fiqh sesungguhnya telah meletakkan proses reproduksi perempuan ini sebagai bagian dari kodrat perempuan yang perlu kita berikan solusi hukumnya.
Pandangan Negatif
Meskipun secara umum fiqh memandang haid, nifas dan istihadhah secara proporsional. Masih ada pandangan negatif terhadap perempuan yang haid dan nifas.
Dalam kitab al-Hayawan karya al-Jahidz, misalnya, mengatakan bahwa ada empat binatang yang mengalami haid. Empat binatang tersebut yakni perempuan, kelinci, kelelawar dan anjing hutan.
Pernyataan ini terasa kurang memanusiakan perempuan, sebab sekalipun memang ada binatang yang mengalami menstruasi, memasukkan perempuan dalam kelompok mereka seperti mempersamakan perempuan dengan binatang.
Dalam al-Hawi terdapat keterangan bahwa haid itu sebagai kotoran karena warna darah itu jelek, baunya tidak enak, najis, dan membahayakan. Alasan yang ia kemukakan ini menyiratkan kesan nyinyir sekaligus tidak proporsional karena tidak memuat hal yang lebih penting yakni alasan kesehatan reproduksi perempuan.
Hal ini seperti jika darah haid tidak perempuan keluarkan, ia akan menjadi kotoran yang membawa penyakit bagi perempuan. Untunglah, pendapat ini bukan merepresentasikan pendapat mayoritas ulama.
Terlepas dari cara pandang ahli fiqh mayoritas dan minoritas tersebut. Ketika kita masuk ke belantara fiqh haid, nifas dan istihadhah lebih dalam lagi. Maka kita akan dapatkan produk-produk hukum yang rumit dan bahkan sangat menyulitkan perempuan.
Tanpa mengurangi penghargaan terhadap hasil ijtihad para ulama yang telah demikian serius mencurahkan perhatiannya dalam masalah ini, dapat dikatakan bahwa sebagian besar hukum tentang haid, nifas dan istihadhah sulit dikatakan membumi dan mengakomodir kemampuan perempuan untuk melaksanakan hukum tersebut. []