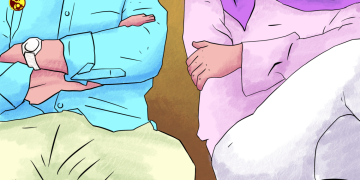Mubadalah.id – Kemandirian disabilitas di Indonesia masih dipandang sebelah mata, terutama dalam dunia kerja yang belum sepenuhnya inklusif. Meskipun sudah tertuang dalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, masih banyak penyandang disabilitas tetap kesulitan memperoleh pekerjaan layak karena hambatan sistemik yang diskriminatif: batas usia, upah yang tidak adil, hingga pandangan bahwa difabel lebih lambat beradaptasi dengan teknologi (takyif).
Namun di tengah keterbatasan dan ketimpangan tersebut, sejumlah penyandang disabilitas mulai menemukan cara untuk membuktikan kemandirian mereka lewat jalur alternatif. Salah satunya melalui pertanian inklusif. Di Cimahi, Jawa Barat, sekelompok petani disabilitas yang tergabung dalam Kelompok Tani Tumbuh Mandiri (TUMAN) menunjukkan bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk berkarya dan berdaya.
Aksesibilitas Sebagai Modal Kemandirian Disabilitas
Kemandirian tidak tumbuh begitu saja. Dibutuhkan lingkungan yang mendukung dan memberikan ruang untuk berkembang. Di sinilah peran aksesibilitas menjadi penting bagi penyandang disabilitas.
Berawal dari seorang profesor yang percaya bahwa penyandang disabilitas memiliki potensi besar untuk hidup mandiri. Ia membina para difabel agar berani mencoba bertani—bukan hanya sebagai sumber ekonomi, tetapi juga sebagai ruang untuk membuktikan bahwa mereka “berdaya”.
“Pak profesor mengajarkan kami cara berkebun. Dari situ kami tergerak untuk bertani dan membuktikan bahwa disabilitas mampu beraktivitas seperti masyarakat umum,” ujar Permana Dwicahya, Ketua Kelompok Tani Tumbuh Mandiri.
Selain memberikkan motivasi, profesor tersebut juga memberikan tanahnya untuk mereka garap. Inilah bentuk aksesibilitas sosial (tamkin) bagi penyandang difabel, tidak hanya memberikan akses materi tapi juga pengakuan-menerima dan mendukung individu atau kelompok agar dapat tumbuh dan berdaya.
Dan buah dari aksesibilitas itu, sejak berdiri pada 2020, kelompok ini berkembang menjadi komunitas yang solid. Hingga kini ada 26 penyandang disabilitas yang tergabung, terdiri atas tunadaksa, tunarungu, dan tunagrahita. Semuanya belajar secara otodidak dengan modal tani seadanya hasil swadaya bersama. Inilah wujud nyata bagaimana aksesibilitas dapat menumbuhkan kemandirian disabilitas melalui pertanian inklusif.
“Kalau modal ya dari kas kelompok, disisihkan dari rezeki anggota yang kerja di luar. Alhamdulillah, kami sudah pernah panen timun, kacang, dan jagung,” ungkap Permana.
Belajar Bersama, Tumbuh dari Kendala
Namun, dalam prosesnya mereka juga menghadapi banyak kendala—mulai dari sulitnya komunikasi dengan anggota tunarungu hingga keterbatasan alat pertanian. Namun, dengan kesabaran dan kebersamaan, hambatan itu perlahan teratasi. Setiap anggota beradaptasi sesuai kemampuan: ada yang bertugas membersihkan gulma, mengairi tanaman, hingga memanen hasil kebun bersama.
Perjalanan mereka tidak selalu mudah. Pada awal 2020, kelompok ini mengalami jatuh bangun: kesulitan air, harga pupuk yang tinggi, dan hasil panen yang belum menentu. Namun semangat mereka tak pernah padam. “Setelah dua tahun, kami mendapat bantuan sumur bor dari NGO. Dari pengalaman-pengalaman itu, kami belajar banyak hal di sektor pertanian,” kenang Permana.
Tantangan demi tantangan justru menguatkan keyakinan mereka bahwa disabilitas dapat tumbuh mandiri ketika ada ruang, dukungan, dan tekad untuk terus belajar bersama.
Pertanian Inklusif dan Solidaritas
Dukungan aksesibilitas itu menjadi pijakan awal. Namun, yang membuat kelompok TUMAN terus bertahan bukan hanya akomodasi, melainkan juga kekuatan kolektif di antara para anggotanya.
Pertanian inklusif tidak hanya berbicara tentang akses pekerjaan bagi penyandang disabilitas, tetapi juga tentang sistem sosial yang mendukung. Kelompok TUMAN menjadi contoh nyata bagaimana mereka bisa menghapus sekat perbedaan dan menghapus stigma. Di sektor ini, mereka mampu melakukan proses produksi (hulu), dan mulai menjual hasil panen secara mandiri tanpa bergantung pada tengkulak (hilir).
“Kami jual langsung ke konsumen. Keuntungannya lebih terasa, minimal ada uang jajan untuk anggota,” ujar Permana. Cara ini juga menumbuhkan ekonomi inklusif yang memberi ruang bagi semua untuk berpartisipasi.
Meski dukungan dari pemerintah daerah belum sepenuhnya maksimal, hal itu tidak menyurutkan langkah kelompok Tani Tumbuh Mandiri untuk terus berkembang. Mereka memilih menapaki jalan kemandirian dengan sumber daya yang ada, mengandalkan swadaya anggota dan bantuan dari lembaga sosial yang peduli. Dari modal kecil yang dikumpulkan bersama, mereka mampu mengelola lahan, membeli bibit, menyediakan alat pertanian, hingga pemasaran.
Sikap mandiri ini justru menjadi cerminan semangat sejati pertanian inklusif—bahwa pemberdayaan tidak selalu menunggu uluran tangan, tetapi tumbuh dari kerja sama dan tekad untuk bangkit. Inilah makna sesungguhnya dari nama kelompok mereka: Tumbuh Mandiri.
Martabat dan Nilai Kemanusiaan
Melalui pertanian, kelompok ini menunjukkan bahwa kemandirian disabilitas bukan sekadar wacana. Mereka menanam bukan hanya hasil bumi, tetapi juga martabat manusia.
Pemberdayaan difabel dalam pertanian inklusif menegaskan bahwa inklusi bukanlah belas kasihan, melainkan pengakuan atas potensi. Setiap manusia, dengan segala perbedaan dan keterbatasannya, memiliki peran dalam membangun masyarakat yang adil dan setara.
Ketika warga sekitar membeli hasil panen kelompok ini, mereka tidak sekadar membeli sayuran—mereka membeli nilai solidaritas. Setiap transaksi menjadi wujud dukungan bagi keberlanjutan ekonomi inklusif sekaligus pengakuan terhadap kemampuan penyandang disabilitas.
Kisah petani disabilitas ini mengajarkan bahwa perubahan sosial bisa berawal dari langkah kecil. Melalui pertanian inklusif, mereka bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga penggerak perubahan (karomah insaniah). Mereka menanam harapan, memanen kepercayaan diri, dan menginspirasi masyarakat untuk melihat disabilitas bukan sebagai batas, melainkan sebagai bagian dari keberagaman manusia. []