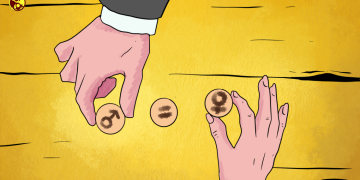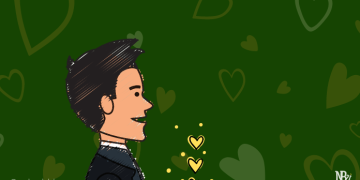Mubadalah.id – Di era TikTok dan Instagram, guru bukan lagi sekadar pengajar. Banyak yang juga tampil sebagai content creator. Videonya beragam: tebak-tebakan di kelas, murid dihukum, atau adegan-adegan lucu lainnya. Konten tersebut memang kadang menghibur, tapi mari kita jujur bahwa ada yang salah ketika wajah polos murid di bawah umur terpajang tanpa perlindungan yang layak.
Di kelas, murid belajar tata krama. Tapi ironisnya, guru yang seharusnya menjadi teladan justru kadang lebih sibuk mengincar view ketimbang menjaga martabat murid. Bisa jadi guru tersebut tidak sadar akan kesalahannya karena terlanjur mendapat banyak dukungan dari followers. Menyangka bahwa pendidikan yang ia laksanakan fine-fine saja.
Tahun lalu, viral seorang guru SMP di Sorong, Papua Barat bernama Saiful Anwar yang menyebarkan video muridnya tanpa izin. Video itu merekam siswa sedang menggambar alis pakai spidol. Orang tua siswa keberatan video anaknya viral di media sosial, berujung menuntut guru tersebut dengan denda Rp100 juta.
Media Sosial dan Mental Anak
Banyak riset sudah bicara tentang betapa rumitnya hubungan media sosial dengan kesehatan mental remaja. Studi Khalaf dkk menemukan penggunaan berlebihan bisa memicu depresi, kecemasan, sampai gangguan tidur. Artinya, anak-anak tidak sekadar “main medsos”, mereka juga sedang mempertaruhkan kondisi psikologisnya.
Ketika guru ikut-ikutan menjadikan mereka bahan tontonan, risiko itu dobel. Anak bukan cuma konsumen konten, tapi juga objek konten. Bayangkan seorang siswa yang terekam melakukan kesalahan kecil di kelas lalu videonya viral. Itu bukan sekadar “konten hiburan”, tapi bisa jadi sumber malu berkepanjangan.
Ada penelitian terbaru yang dilakukan oleh Lanfang Sun dkk tentang fenomena edu-influencers (guru yang aktif di media sosial). Penelitian kualitatif menunjukkan bahwa sebagian guru memanfaatkan platform untuk menyebarkan praktik baik pengajaran, tetapi ada juga praktik yang mengekspos murid tanpa persetujuan memadai. Studi terbaru tentang praktik edu-influencers merekomendasikan standar etika yang jelas untuk menjaga keselamatan siswa.
Bentuk-bentuk pelanggaran yang sering terjadi dalam kontenisasi murid ialah perekaman interaksi kelas tanpa izin, menampilkan hasil kerja atau wajah siswa, prank dan tantangan yang melibatkan murid, serta editing yang mengubah konteks percakapan anak.
Praktik semacam ini dapat melanggar hak privasi anak, kebijakan perlindungan data, dan prinsip pedagogis. Kasus-kasus serupa di luar negeri telah memicu teguran terhadap guru dan sekolah, menunjukkan preseden etis dan legal yang relevan dengan Indonesia.
Murid Jadi Korban
Ada beberapa alasan kenapa banyak guru terjun ke dunia konten. Pertama, insentif sosial dan ekonomi. Umumnya media sosial bisa dimonetisasi, utamanya jika menjaring banyak viewers. Kedua, budaya digital sekarang memang menilai keberhasilan dari like dan share, bukan dari kualitas interaksi tatap muka. Ketiga, belum ada aturan jelas di sekolah tentang batas penggunaan medsos oleh guru. Akhirnya, semua berjalan tanpa pagar.
Kita sering lupa bahwa murid bukan orang dewasa yang siap tampil. Mereka masih mencari identitas. Ditarik ke arena publik tanpa persetujuan yang matang bisa melahirkan banyak dampak buruk. Mulai dari rasa malu, kecemasan sosial, sampai jadi bahan ejekan di dunia maya. Paparan berlebihan terhadap konten publik bisa menurunkan kesejahteraan mental remaja, apalagi kalau mereka tidak punya kontrol atas cara mereka ditampilkan.
Dari sisi pendidikan, kontenisasi ini juga bikin suasana kelas berubah. Murid yang tahu dirinya terekam cenderung main peran: jadi lebih “lebay”, cari perhatian, atau malah takut salah. Jadi yang rugi siapa? Ya proses belajar itu sendiri.
Aturan yang Tegas
Guru perlu dibekali literasi digital dengan pemahaman bahwa medsos bukan sekadar ruang hiburan, tapi juga ruang yang penuh jebakan. Di dalamnya ada algoritma, sensor, dan monetisasi. Guru juga harus menyadari bahwa banyaknya like bukan berarti perbuatan menjadi benar.
Sudah saatnya kebijakan sekolah membuat aturan perekaman di kelas. Baik sekolah maupun guru tidak berhak mempublikasikan video murid tanpa persetujuan orang tua. Persetujuan harus dilaksanakan dengan gamblang, bukan hanya formalitas. Murid dan orang tua harus tahu konten terpakai untuk apa, berapa lama akan tersimpan, dan bagaimana cara mencabut izin kalau mereka berubah pikiran.
Tulisan ini tidak berusaha melarang guru untuk menjadi content creator, melainkan mengingatkan mereka akan tujuan utama pendidikan. Guru sebagai pembimbing dan pengasuh murid selayaknya memberikan perlindungan, bukan malah mengeksploitasi mereka. Perlunya kesadaran dalam berkonten bahwa ada konsekuensi jika masih melakukannya dengan cara-cara yang melanggar privasi murid. []