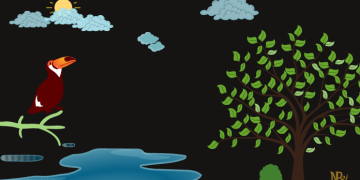Mubadalah.id – Merayakan hari ibu berarti mengingat kembali salah satu sosok yang sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Sosok yang selalu memberi tanpa mengharap imbalan. Yang selalu menyayangi, meski kadang terlupakan. Begitu pula dengan sosok yang menjadi tempat bernaung kita selama ini: Ibu Pertiwi.
Indonesia mengenal ibu bukan hanya sebagai sosok biologis, tetapi juga sebagai simbol. Ibu adalah sumber, tempat kembali, dan penopang kehidupan. Dalam bahasa kebudayaan, bumi pun dipanggil dengan nama yang sama: Ibu Pertiwi. Sebuah istilah yang merujuk pada bahasa Sanskerta “Prthvi” yang berarti Ibu bumi atau Dewi yang menguasai bumi.
Ibu Pertiwi (motherland) sendiri merupakan sebuah personifikasi dari tanah air Indonesia. Layaknya seorang ibu, tanah air atau bumi juga memberi sesuatu tanpa syarat. Air untuk minum, tanah untuk bercocok tanam, dan hutan untuk menjaga keseimbangan. Bumi juga bekerja dalam diam. Seperti ibu pula, ia baru diingat ketika sudah mulai kelelahan.
Ibu Pertiwi Kita Terluka
Saat ibu sakit, mungkin kita baru menyadari betapa sulitnya menjadi seorang ibu. Meski, saat sakit pun ibu kerap menyembunyikan rasa sakitnya. Menahan deritanya seorang diri, supaya anak-anaknya masih bisa tertawa haha-hihi.
Sama seperti ibu Pertiwi kita. Ia menyediakan alam supaya bisa manusia gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, karena ketamakan dan egonya, manusia sering abai bahwa ibu Pertiwi kita sebenarnya sedang terluka.
Mereka menebang hutan atas nama pembangunan, mempersempit sungai demi efisiensi, mengeruk tanah demi pertumbuhan ekonomi, katanya. Padahal, semua mereka lakukan hanya untuk memenuhi kepentingan segelintir kelompoknya sendiri. Mereka mengira bahwa bumi selalu mampu menanggungnya. Padahal, layaknya seorang ibu, bumi juga punya batas kemampuan.
Lalu sampai di titik ketika bumi sudah tak sanggup, manusia yang tidak berdosa pun harus ikut menanggungnya. Bencana yang berulang di berbagai wilayah Indonesia bukan peristiwa yang jatuh dari langit. Ia muncul perlahan seiring hilangnya kawasan resapan, rusaknya hutan, dan rapuhnya tata kelola ruang.
Sementara itu, kerap kali manusia melempar batu sembunyi tangan. Mereka yang mengeksploitasi malah menyalahkan alam itu sendiri. Cuaca disalahkan, takdir dijadikan alasan. Bahkan ada pula yang mengatakan bahwa rakyat di sana sudah kebanyakan dosa sehingga itu adalah azab bagi mereka. Ironisnya, jauh di belahan bumi sana, ada manusia yang tak punya malu. Duduk santai sambil menikmati keuntungan dari bumi yang mereka keruk. Damn!
Padahal, alam tidak pernah berubah tabiat. Air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Tanah akan runtuh ketika tak lagi memiliki penyangga. Sungai akan meluap ketika sudah sempit dan terpaksa menampung lebih dari kadar kemampuannya. Yang berubah hanyalah cara manusia memperlakukan ruang hidupnya. Dalam relasi ini, bumi sebenarnya tidak marah, ia juga korban dari kerakusan para manusia bedebah itu.
Ibu dan Ibu Pertiwi Sama-sama Memikul Beban Ganda
Dalam berbagai bencana, kita melihat sosok ibu yang berdiri di garis terdepan. Mereka yang pertama menyelamatkan anak-anaknya, meski harus mengorbankan dirinya sendiri. Ibu pasti akan sangat sakit ketika melihat anak-anaknya belum makan karena tiadanya bahan makanan. Pun ketika bahan makanan sudah tersedia, ia harus mengatur sedemikian rupa supaya bisa bertahan sampai waktu yang ia pun tak mengetahuinya.
Belum lagi ketika ibu sedang kedatangan tamu yang sama sekali tidak pernah laki-laki rasakan: menstruasi. Entah bagaimana nyerinya, ketidaknyamanannya, dan ketidakstabilan emosinya. Apalagi dengan tekanan psikologis yang ia rasakan pasca bencana.
Menstruasi sendiri merupakan proses biologi alami yang tidak bisa perempuan hindari, termasuk ketika berada di pengungsian. Dalam hal ini tidak hanya makanan yang menjadi kebutuhan dasar, adanya pembalut yang jumlahnya terbatas menjadi kebutuhan penting bagi penyintas perempuan.
Akan tetapi, hingga saat ini masih banyak yang menganggap bahwa donasi pembalut itu tidak penting. Padahal, darah yang keluar terus-menerus ketika menstruasi perlu penanganan yang layak. Jika tidak, hal itu bisa memicu infeksi, iritasi, dan mengganggu organ reproduksi dalam jangka panjang.
Saat ini ibu manusia dan Ibu Pertiwi bertemu dalam satu titik yang sama. Yakni sama-sama memikul beban ganda akibat keputusan yang sering diambil tanpa suara mereka. Mereka sama-sama memendam luka yang tak kunjung sembuh. Luka akibat objektifikasi terhadap tubuh-tubuh ibu hanya untuk kepentingan para oligarki.
Merayakan Hari Ibu, Mari Merawat Ibu Pertiwi
Dalam momen hari ibu ini, seharusnya kita lebih menyadari bahwa mencintai ibu bukanlah peristiwa seremonial yang berhenti dalam unggahan media sosial. Ini adalah praktik sehari-hari dengan selalu mendengar, menjaga, dan tidak melukai. Jika prinsip ini diterapkan pada relasi kita dengan bumi, barangkali banyak keputusan akan diambil dengan cara berbeda, yang tidak merugikan satu sama lainnya.
Merawat Ibu Pertiwi berarti mengakui bahwa pembangunan memiliki batas ekologis. Bahwa pertumbuhan tidak bisa terus-menerus mengorbankan ruang hidup. Bahwa sungai bukan saluran pembuangan, hutan bukan cadangan lahan semata, dan tanah bukan objek yang boleh diperas tanpa henti.
Tentu, merawat bumi tidak cukup dengan imbauan moral. Ini membutuhkan keberanian politik, kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan, dan penegakan hukum yang konsisten. Namun, hal ini juga membutuhkan kesadaran kolektif. Bagaimana cara kita memilih, mengonsumsi, dan bersikap terhadap ruang hidup.
Melalui momentum Hari Ibu ini seharusnya kita bisa bercermin. Bukan hanya tentang seberapa sering kita mengucapkan terima kasih, tetapi tentang bagaimana kita hidup. Apakah cara hidup kita memperpanjang usia bumi, atau justru mempercepat kelelahan ibu pertiwi yang kita miliki.
Ibu Pertiwi kita memang tidak menuntut balasan. Ia hanya butuh keseimbangan. Agar bisa memberi kehidupan yang lebih lama. Memenuhi kebutuhan manusia tanpa mengorbankan manusia lainnya.
Momen Hari Ibu ini mengingatkan kita bahwa merawat bumi adalah salah satu bentuk bakti yang paling nyata. Sebab ketika air surut dan lumpur mengering, ingatan sering ikut tenggelam. Dan negeri ini berulang kali membuktikan bahwa melupakan luka ibu selalu berujung pada luka yang lebih dalam. Lekas pulih ibu pertiwiku! []