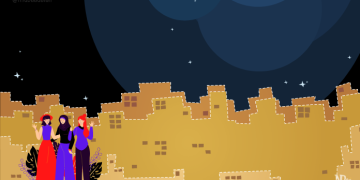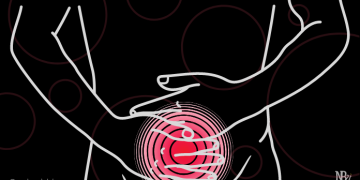“Dulu negara-negara maju juga membangun dengan kekayaan alamnya, dengan pertambangan, tapi mereka tidak dikritik oleh masyarakatnya seperti Indonesia sekarang.”
Mubadalah.id – Kalimat ini bukan sekadar opini publik di media sosial, tetapi disampaikan langsung oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, dalam sambutan resminya di sebuah acara formal. Sebagai mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Australia—negara yang juga memiliki sejarah panjang sebagai ekonomi ekstraktif—saya merasa perlu menanggapi pernyataan ini secara jujur dan historis.
Benarkah negara maju seperti Australia membangun tanpa kritik terhadap eksploitasi sumber daya? Dan apakah kritik tambang di Indonesia hari ini merupakan bentuk penghambat pembangunan?
Sejarah Penuh Resistensi dan Evolusi Hukum Lingkungan Australia
Australia terkenal sebagai negara dengan kekayaan sumber daya mineral yang luar biasa. Sejak lama, pertambangan menjadi tulang punggung ekonominya. Namun, di balik cerita sukses itu, tersembunyi sejarah panjang resistensi publik, konflik antarpemerintah, serta gesekan antara negara dan warga—terutama masyarakat adat—yang menuntut keadilan ekologis.
Pada awalnya, isu lingkungan berada di bawah kewenangan negara bagian, sesuai sistem federalisme Australia. Titik balik terjadi dalam kasus Commonwealth v Tasmania (1983), ketika pemerintah federal menggagalkan proyek bendungan yang mengancam kawasan Warisan Dunia.
Mahkamah Agung memutuskan bahwa pemerintah pusat berwenang bertindak untuk memenuhi kewajiban internasional di bidang lingkungan. Sejak itu, hukum lingkungan federal mulai berkembang.
Salah satu regulasi penting yang lahir kemudian adalah Environment Protection and Biodiversity Conservation (EPBC) Act 1999, yang menjadi payung hukum perlindungan spesies dan habitat. Meski sudah dua dekade berjalan, UU ini terus menuai kritik karena prosedur yang lamban dan lemahnya perlindungan substantif.
Puncaknya terjadi saat perusahaan Rio Tinto menghancurkan gua Juukan Gorge pada 2020—situs sakral dan arkeologis bagi masyarakat Puutu Kunti Kurrama dan Pinikura (PKKP). Tragedi ini memicu kemarahan nasional dan mendorong lahirnya Samuel Review, yang merekomendasikan pembentukan standar lingkungan nasional yang mengikat dan lembaga pengawasan independen.
Kritik terhadap EPBC juga mencerminkan pola lebih luas: proyek tambang besar kerap dilakukan di atas tanah adat tanpa persetujuan yang layak, menggusur komunitas Aborigin dan merusak situs budaya mereka. Industri ekstraktif di Australia, terutama batu bara dan uranium, meninggalkan jejak ekologis dan sosial yang mendalam.
Pengesahan Climate Change Act 2022
Sementara itu, tonggak penting lainnya adalah pengesahan Climate Change Act 2022. Prosesnya tidak instan, tetapi melewati dekade tarik-ulur antara sains, aktivisme, dan kepentingan politik. Setelah lama dicap sebagai “laggard” dalam kebijakan iklim, Pemilu 2022 menjadi titik balik.
Isu lingkungan mendominasi perdebatan publik dan mendorong terpilihnya Teal Independents—kandidat nonpartai yang menuntut aksi iklim tegas. Mereka berhasil mengalahkan petahana dari partai besar yang dianggap terlalu akomodatif terhadap industri bahan bakar fosil.
Kemenangan ini mencerminkan bahwa kebijakan lingkungan bukan lagi isu pinggiran, tetapi agenda elektoral utama yang didorong oleh kesadaran publik. Meski Climate Change Act masih menghadapi kritik, pengesahannya menjadi bukti kekuatan tekanan masyarakat sipil yang terorganisir dan konsisten.
Sebagai warga Indonesia, saya dulu melihat Australia sebagai negara dengan tata kelola lingkungan yang ideal. Namun, pengalaman belajar di sini membuka mata saya. Di balik kemajuan hukum dan kebijakan, terdapat pertarungan panjang yang belum selesai. Australia pun masih bergulat dengan kelemahan hukum, ketimpangan perlindungan, dan kuatnya pengaruh industri ekstraktif.
Dari sanalah saya menyadari, kemajuan bukan berarti tanpa cacat. Ia justru lahir dari keberanian untuk terus dikritik dan diperbaiki. Maka ketika warga Indonesia hari ini mengkritik proyek tambang dan kerusakan lingkungan, saya melihatnya bukan sebagai penghambat, tapi sebagai bagian penting dari pembangunan yang benar.
Kritik Tambang Bukan Penghambat, Tapi Penyeimbang
Salah satu momen penting dalam sejarah hukum lingkungan Australia adalah putusan Rocky Hill (Gloucester Resources Ltd v Minister for Planning, 2019). Dalam kasus ini, pengadilan menolak izin tambang batu bara karena pertentangannya dengan prinsip Ecologically Sustainable Development (ESD). Prinsip ini berakar dari kesepakatan lintas level pemerintahan dalam Inter-Governmental Agreement on the Environment (IGAE) 1992.
Dalam Rocky Hill, Hakim Preston menyatakan bahwa proyek ini tidak sejalan dengan arah masa depan rendah karbon dan tidak sesuai dengan tanggung jawab terhadap generasi mendatang. Putusan ini menyelamatkan masyarakat lokal dari polusi dan dampak sosial, serta memperlihatkan bahwa keberlanjutan bukan sekadar ideal, tapi dapat menjadi dasar hukum yang melindungi hak warga.
Putusan Rocky Hill menunjukkan bahwa kritik publik memiliki kekuatan hukum jika terbingkai dalam prinsip keberlanjutan. Ia menjadi bukti bahwa perlawanan terhadap eksploitasi dapat menang, dan bahwa masyarakat dapat memperjuangkan hak atas ruang hidup yang sehat dan adil, dengan tetap mempertahankan sumber ekonomi mereka.
Dunia yang Berubah dan Tantangan Keadilan Ekologis Global
Argumen seperti “negara maju sudah duluan menambang, kenapa kita dilarang?” sering kali muncul. Benar, negara maju membangun dengan biaya ekologis tinggi. Namun, jawaban terhadap ketidakadilan bukanlah mengulang kesalahan mereka. Jika semua negara berkembang menempuh jalan yang sama, kerusakan akan menjadi tak terpulihkan.
Ketidakadilan ekologis global nyata: negara berkembang mewarisi krisis akibat industrialisasi negara maju, tapi diminta ikut menanggung solusinya tanpa dukungan memadai. Namun, itu tidak bisa menjadi alasan untuk abai. Negara-negara berkembang harus lebih berani mengambil peran dalam membentuk hukum dan kebijakan internasional.
Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement dan Convention on Biological Diversity (CBD). Tapi komitmen ini harus kita jalankan dengan konsisten, bukan hanya simbolis. Kita perlu menata ulang pengelolaan sumber daya alam dari hulu ke hilir, serta menagih tanggung jawab negara maju secara strategis dan terukur.
Kritik terhadap mekanisme pasar karbon, yang kerap kita nilai tidak adil dan membiarkan pencemar membeli “hak mencemari”, harus kita imbangi dengan tawaran alternatif. Yakni sistem pemantauan karbon yang transparan, perlindungan hak masyarakat adat, dan proyek yang berbasis keadilan iklim.
Keadilan ekologis tidak akan tercapai hanya dengan protes. Ia lahir dari keberanian menetapkan standar baru dan mengajak dunia menghormatinya.
Membangun dengan Arah yang Benar
Jika belajar dari Australia, kita tahu bahwa pembangunan yang baik bukan tanpa kritik. Justru kritik tambang menunjukkan kematangan publik dan demokrasi yang sehat. Alih-alih membungkam suara kritis, Indonesia seharusnya beraliansi dengan masyarakat adat, ilmuwan, dan aktivis lingkungan sebagai sekutu strategis.
Langkah ini penting bukan hanya untuk menata sumber daya alam secara adil, tapi juga untuk menekan negara maju memenuhi tanggung jawab mereka. Dana iklim yang adil, teknologi hijau, dan pengakuan terhadap komunitas penjaga alam.
Kita tidak perlu meniru jejak merusak negara maju. Indonesia dan negara Global South punya peluang jadi pelopor pembangunan yang adil dan inovatif jika berpihak pada rakyat dan alam. Membangun bukan soal menggali mineral saja, tapi juga soal transparansi, visi ekonomi beragam, dan keberanian moral untuk memilih masa depan yang tidak merusak. []