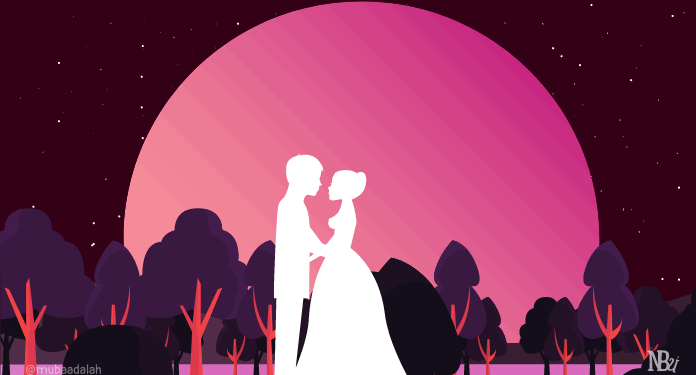Mubadalah.id – Stigma untuk anak di luar nikah di Indonesia masih sangat buruk. Padahal kesalahan ada pada orang tuanya, bukan anaknya. Meskipun Indonesia bukan negara Islam, tetapi penduduknya mayoritas beragama Islam sehingga perilaku seks bebas dan hamil di luar nikah adalah hal tabu dan dianggap aib.
Beginilah ketika manusia tidak memiliki batasan dalam pergaulan, sehingga terjadi seks bebas yang menyebabkan kerugian di kemudian hari. Perempuan dan anak adalah yang paling rentan mendapat kerugian.
Adanya syariat pernikahan sah dalam Islam salah satunya adalah untuk menjaga keturunan. Pentingnya melakukan pernikahan sah dan tidak seks beresiko adalah untuk kejelasan nasab. Sehingga tidak ada kemungkinan melakukan pernikahan dengan saudara sendiri. Dalam medis pun pernikahan sedarah sangat berbahaya untuk keturunannya.
Dalam istilah perundang-undangan, terdapat istilah anak sah dan anak tidak sah. Anak yang lahir dengan ada pernikahan sah secara agama dan negara kita sebut anak sah, sedangkan anak yang lahir dari pernikahan tidak resmi (nikah sirri) atau bahkan tanpa pernikahan kita sebut anak tidak sah. Tetapi sebutan anak di luar nikah di Indonesia pada umumnya merujuk pada anak yang lahir tanpa pernikahan.
Simpang Siur Hukum Indonesia dan Hukum Islam
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anak tidak sah adalah anak yang terlahir tanpa keterikatan perkawinan yang resmi. Kemudian pada pasal 43 Ayat (1) menyatakan bahwa; “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.
Bedanya, dalam hukum Islam anak yang lahir dalam pernikahan sirri, masih bernasab pada bapaknya meskipun akan terdapat kesulitan administrasi kependudukan.
Berdasarkan hukum Islam, anak yang lahir dari perzinahan atau tanpa pernikahan menanggung konsekuensi terputus 3 hal dari bapak kandungnya. Yaitu perwalian, nafkah, dan waris. Hadis yang sebagai sandaran terkait kasus ini adalah :
الولد للفراش وللعاهر الحجر
“Anak itu (nasabnya) milik pemilik ranjang (suami), dan bagi pezina adalah batu (kerugian/tidak ada hak).” (HR. Bukhari dan Muslim)
Jika menilik perkembangan hukum dan kasus-kasus kontemporer, terdapat satu kejadian yang melatarbelakangi munculnya Putusan MK RI No. 46/PUU-VIII/2010. Putusan ini berdampak pada adanya hak perdata untuk anak di luar nikah jika terdapat bukti yang kuat adanya hubungan biologis.
Pihak perempuan bisa mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama untuk masyarakat beragama Islam dan ke Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam.
Fatwa MUI
Namun sayangnya, putusan MK ini memberikan kekhawatiran adanya kesimpangsiuran nasab yang dilarang dalam Islam. Oleh sebab itu Majelis Ulama Indonesia memberi respon dalam fatwa no. 11 Tahun 2012, bahwa :
Pertama, anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
Kedua, anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
Ketiga, anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinahan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
Keempat, pezina dikenakan hukuman hadd oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (hifzh an nasl).
Kelima, pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta’zir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk : a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut; b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.
Keenam, hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
Ta’zir dan Wasiat Wajibah
Anak yang lahir tanpa pernikahan memang terputus hak wali, nafkah, dan warisnya dari bapak kandung. Terkait terputusnya nafkah, hal ini pasti sangat bertentangan dengan asas kemanusiaan dan berpotensi menyulitkan kehidupan anak kedepannya. Terlebih kalau pihak ibu masih belum berdaya secara ekonomi dan pendidikan. Singkatnya, bapak kandung seperti lari dari tanggung jawab.
Nah, fatwa MUI yang merekomendasikan memberikan hukuman (ta’zir) bisa jadi solusi yang mengikat hubungan tanggung jawab bapak kandung terhadap anaknya, baik akhirnya terjadi pernikahan atau tidak. Di negara yang mayoritas beragama Islam, konsep ta’zir bisa menjadi dasar moral pertanggung jawaban laki-laki atas perbuatannya.
Ta’zir bisa berupa memberikan biaya saat kehamilan, persalinan, hingga biaya hidup anak. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 sebenarnya mendekati fungsi ta’zir, yaitu negara menjamin hak anak tanpa menormalisasi perbuatan perzinahan.
Terputusnya hak waris dari bapak kandung juga bisa berdampak kurangnya ekonomi anak di masa mendatang. Hukum waris Islam tidak berlaku, tetapi hukum positif Indonesia mempertimbangkan asas keadilan bagi anak tersebut. Pasal 209 ayat (2) KHI menyebutkan: “Terhadap anak angkat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.”
Meskipun konteks utamanya adalah anak angkat, tetapi para ahli hukum Indonesia menafsirkan anak di luar nikah masuk dalam kategori ini. Ulama kontemporer seperti Syekh Wahbah Zuhaili juga berpendapat bahwa anak di luar nikah tetap berhak mendapat perlindungan dan nafkah melalui wasiat wajibah.
Anak Adalah Korban yang Wajib Terjamin Haknya
Hal ini mencerminkan bahwa Islam tidak menghukum anak yang lahir dari perbuatan zina atau tanpa pernikahan, tetapi juga tidak membenarkan perbuatan perzinahannya. Laki-laki dan perempuan senantiasa harus menjaga pergaulan dan aktivitas seksualnya sebelum ada pernikahan agar tidak ada anak yang menjadi korban perbuatan buruknya. []