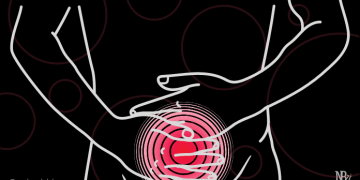Mubadalah.id – Fatwa adalah pandangan hukum Islam yang dikeluarkan individu maupun lembaga yang dianggap memiliki otoritas mengenai hal ini. Biasanya diawali oleh pertanyaan atas apa yang dialami seseorang. Jika yang mengajukan perempuan, berarti fatwa yang dikeluarkan adalah yang didasarkan pada pengalaman mereka.
Pertanyaannya: sejauhmana seseorang atau lembaga memahami pengalaman perempuan, sehingga jawaban yang dikeluarkannya, lalu, adalah benar-benar relevan? Di artikel ini, saya akan menjelaskan soal pentingnya fatwa yang merujuk pengalaman perempuan.
Dalam disiplin fiqh dan ushul fiqh kita mengenal metode istiqra, penelitian berbasis pengalaman. Dalam Mazhab Syafi’i, dipopulerkan kisah bahwa Imam Syafi’i sendiri, sebagai peletak dasar-dasar Mazhab ini, telah menggunakan metode istiqra untuk fiqh terkait haid atau menstruasi.
Dalam merumuskan fiqh ini, beliau bertanya terlebih dahulu kepada para perempuan, tentang pengalaman mereka terkait menstruasi ini. Sayangnya, metode ini tidak ada yang mengembangkan lebih lanjut. Jangankan untuk masalah-masalah kehidupan yang lebih luas yang dihadapi perempuan, bahkan untuk masalah menstruasipun, fiqh kita tidak lagi diverifikasi kembali dengan merujuk pada pengalaman perempuan yang terus berkembang dan beragam.
Kita tahu, ilmu pengetahuan terkait anatomi tubuh dan temuan-temuan medis terkait reproduksi perempuan berkembang begitu pesat. Tetapi, fiqh haid kita masih merujuk pada detail pandangan ulama yang begitu kompleks, yang entah masih valid kah jika dirujukan pada ilmu biologi anatomi tubuh, temuan medis, dan terutama pengalaman nyata para perempuan. Dampak dari penggunaan alat kontrasepsi hormonal misalnya, banyak perempuan yang mengalami kekacauan daur menstruasi.
Jika pengalaman-pengalaman ini dijawab dengan pandangan fiqh Mazhab Syafi’i –misalnya yang tertulis dalam Risalah al-Mahidh- justru akan membingungkan dan menyulitkan para perempuan. Alih-alih meringankan dan memudahkan, karena perempuan sedang sakit menstruasi, sebagaimana itu prinsip syari’at Islam, fiqh haid yang ada malah memberi beban berat, yang sulit ditanggung kebanyakan perempuan. Dan kesulitan ini akan dialami perempuan setiap bulan dan sepanjang hidup mereka.
Untuk itu, kita perlu menghidupkan kembali metode istiqra ini, yang telah diawali Imam Syafi’i rahimahullah. Tidak hanya urusan menstruasi, tetapi seluruh kehidupan yang dialami perempuan harus menjadi basis perumusan fatwa-fatwa yang dikeluarkan individu maupun lembaga pada konteks kita sekarang ini.
Kita bisa belajar, bahkan dari semangat Nabi Muhammad Saw ketika mendengar para perempuan, dan mengeluarkan fatwa dan pandangan hukum yang relevan dengan pengalaman mereka. Keputusan Nabi Saw, dalam hal ini, yang disebut sebagai Hadits, tentu saja lebih tinggi dan menjadi rujukan yang otoritatif bagi semua produk fiqh dan fatwa yang lahir kemudian hari.
Sebagaimana dicatat Imam Bukhari dalam Sahihnya, juga kitab-kitab hadits lain, ada keputusan Nabi Saw yang begitu empatik dan suportif terhadap pengalaman perempuan. Adalah seorang perempuan bernama Habibah bint Sahl radhiallahu ‘anha. Dia adalah istri seorang sahabat terpandang, tokoh panutan, dan orator ulung penduduk Madinah, Tsabit bin Qays bin Syammas al-Anshari al-Khazraji. Habibah tiba-tiba datang ke rumah Rasulullah Saw.
Saat Nabi Saw membuka pintu rumah, dijumpai ada seorang perempuan. “Siapa ini? Kata Nabi Saw. “Habibah bint Sahl”, jawab sang perempuan. “Ada keperluan apakah gerangan?. “Aku istri Tsabit bin Qays ra. Ya Rasul, aku tidak sanggup lagi menjadi istri dia. Sekalipun akhlak dia baik dan ibadah dia juga bagus, tetapi aku tidak sanggup serumah dengannya”. “Mau kamu apa? Tanya Nabi Saw. “Aku tidak menyalahkannya, tetapi aku sendiri yang ingin bercerai darinya, karena tidak sanggup hidup bersama. Khawatir malah aku berperangai buruk kepadanya”, jawab tegas Habibah.
Lalu Nabi Saw memanggil suaminya, Tsabit bin Qays ra, dan menyarankannya untuk menceraikan istrinya tersebut. Perceraianpun terjadi dengan tebusan sebidang tanah yang awalnya diterima Habibah sebagai mahar, yang dikembalikan kepada Tsabit. Inilah kisah cerai tebus pertama dalam Islam, yang dalam fiqh disebut sebagai khulu’. Kisah lengkap ini dari berbagai versi hadits yang dicatat Imam Ibn Hajar dalam Fath al-Bari (juz 10, halaman 500-501).
Dalam kisah ini jelas sekali Nabi Saw mendengar dan merujuk pada apa yang dialami dan dirasakan perempuan dalam kehidupan pernikahannya. Karena prinsip pernikahan itu untuk mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dan ketika seorang perempuan menemukan yang sebaliknya, Nabi Saw memutuskan hukum yang merujuk pada pengalamannya yang nyata itu.
Lebih dramatis lagi yang disampaikan Barirah ra istri dari Mughits ra (Lihat Sahih Bukhari, no. 5338 dan Sunan Abu Dawud, no. 2233). Semua sahabat tahu betapa besar cinta Mughith kepada istrinya. Tetapi sang istri, Barirah, bersikeras minta cerai, karena alasan dia tidak sanggup menjadi istrinya. Sang suami menangis dan memohon-mohon kepada istrinya untuk mengurungkan niat cerainya. Barirah tetap tidak bergeming. Akhirnya, Mughits menghadap Nabi Saw dan memohon pertolongan untuk menasihati Barirah.
“Bartakwalah kepada Allah, wahai Barirah, dia itu suamimu dan ayah dari anakmu, kembalilah kepadanya”, kata Nabi Saw. “Apakah ini perintah panjenengan wahai Rasul, atau saran saja”, tanya Barirah. “Bukan perintah, ini ingin membantu Mughits agar diterima kembali oleh kamu”, jawab Nabi Saw. “Kalau begitu, maaf, aku tidak bisa memenuhi kebutuhanku jika bersamanya, ya Rasul”, jawab tegas Barirah. Dan Nabi Saw membiarkan perceraian itu terjadi atas inisiatif perempuan, yang justru sangat dicintai dan digandrungi suaminya.
Tentu saja masih banyak keputusan-keputusan Nabi Saw, dalam berbagai hadits, yang didasarkan pada pengalaman nyata yang dialami perempuan. Ke depan, kita perlu fatwa-fatwa, terutama yang menyangkut perempuan, dengan benar-benar merujuk dan mempertimbangkan pengalaman nyata yang dialami dan dirasakan perempuan. Berfatwa dengan cara ini adalah teladan Nabi Muhammad Saw. Wallahu a’lam. []