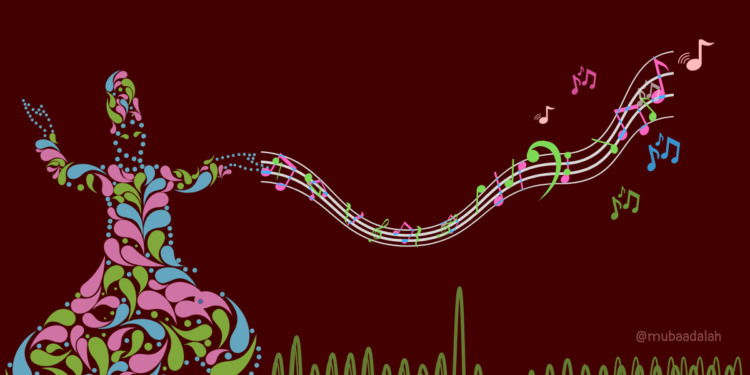Mubadalah.id – Moderasi beragama melalui sufisme adalah sebuah tawaran yang penting untuk dibicarakan. Telah banyak disuguhkan pada kita berita-berita mengenai keterlibatan anak muda di Indonesia dalam arus konservatisme, radikalisme sampai violent-extremisme. Survey lampau dari BNPT (2017) mengutarakan bahwa 39% mahasiswa Indonesia di 15 provinsi tertarik pada paham radikal.
Di tahun yang sama, PPIM UIN Jakarta merilis laporan peninjauan mereka terhadap 2.181 responden (guru, siswa, dan mahasiswa) dari 34 provinsi tentang agama, negara, dan intoleransi. Hasilnya cukup menggiriskan; 37,71% setuju bahwa jihad sama dengan perang dan membunuh (qitāl). Kemudian 23,35% sepakat kalau bom bunuh diri adalah jihad Islam. Responden riset ini, ironisnya, didominasi oleh anak muda.
Ini menegaskan bukti bahwa, pada dasarnya, gairah keagamaan generasi muda Indonesia cukup besar. Hanya saja, itu tidak dibarengi oleh pemahaman lengkap mereka dan rasa kasih sayang antarsesama. Sebagai konsekuensi, tidak sedikit dari kalangan muda yang terjerumus ke kelompok ekstremisme keagamaan.
Munculnya Inisiatif P/CVE
Tidak aneh jika kemudian banyak narasi dominan dan inisiatif sipil yang mengarusutamakan moderasi beragama untuk mencegah peningkatan gejala tersebut. Salah satu di antaranya dikemas secara strategis dan berkelanjutan dalam format gerakan internasional bertema “preventing & countering violent extremism” (disingkat P/CVE).
Respons tersebut tentu beririsan dekat dengan multi-istilah seperti xenophobia (perasaan takut dan benci terhadap orang asing atau yang belum dikenal) dan radikalisme—yang menuai cukup banyak sawala diskursif. Mengenai penggunaan term terakhir ini, di sejumlah forum akademik dan non-akademik banyak dibahas dan diperdebatkan.
Di Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI dengan BNPT 11 November 2019 ada poin ketidaksepakatan dengan diksi “radikalisme” dan menyarankan agar menggantinya dengan violent extremism. Berkaca dari sini, tampak ada kesinambungan wacana internasional mengenai kewaspadaan pada masalah ekstremisme kekerasan.
Otomatis, isu tersebut memang menagih keseriusan banyak pihak dalam memproduksi strategi (preventif dan kuratif) yang jitu dan berdampak. Terlebih dalam menyasar dan melibatkan generasi muda selaku aktor sekaligus golongan yang rawan menjadi ‘target market’ dari kelompok ekstrem.
Anak Muda dan Perilaku Keagamaan yang Narsis
Salah satu faktor yang menimbulkan anak muda tertarik kepada paham ekstremisme kekerasan yang berbasis doktrin keagamaan adalah tendensi narsisisme. Dengan adanya atmosfer sosial dan infrastruktur teknologi digital masa kini, semua itu ikut mewadahi kecenderungan narsisisme dalam diri mereka. Dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia belaka, melainkan di penjuru bumi.
Kata narsisisme sebagai term psikologi, sebelum terdistorsi makna dan menjadi peyoratif sebagai aktivitas gemar selfie dan posting, bukan sekadar perilaku mencintai diri sendiri semata. Lebih dari itu, narsisisme merupakan gejala permulaan dari gangguan kepribadian yang membuat individu merasa superior, egois, kagum akan diri sendiri, dan kurang rasa empatinya.
Secara dramatis, gejala ini merebak di abad digital sampai bahkan bisa memuai dan membengkak menjadi narsisisme kolektif. Agnieszka Golec de Zavala menamainya “collective narcissism” yang dapat merambah ke multisektor mulai dari nasionalisme, etnosentrisme, hingga keagamaan.
Dengan begitu, narsisisme religius kolektif dapat dipandang sebagai sebuah kecenderungan sosial-psikologis kelompok yang merasa superior, istimewa, paling benar, kagum akan kelompok sendiri, dan menegasikan kelompok liyan hingga mendiskriminasi. Secara garis besar, karakteristik utamanya: asserting superiority, devaluing others, egoistically motivated, higher in rivalry, over admiration of themselves, dan lack of empathy.
Imbas dari ini tentu saja dapat memicu sikap dan perlakuan yang menghinakan sesama manusia. Sebagaimana kita amati sendiri, banyak kelompok terkini yang berlaku senewen dengan menuduh orang-orang di luar kelompoknya sebagai kaum bid’ah, sesat, layak dinistakan, bahkan dibunuh—contoh ekstremnya: kasus ISIS. Dan tidak sedikit anak muda yang tersurupi kecenderungan semacam ini dan sudah tampak di jagat maya.
Berebut Klaim Kebenaran Hingga di Jagat Maya
Dalam praktiknya di ruang publik, narsisisme religius kolektif ini dapat mengambil beragam wujud. Ada yang secara sikap sosial sudah menutup diri (eksklusif), ada juga yang masih terbuka namun mendiskriminasi orang lain (intoleran) hingga terpantau di medsos.
Faktor-faktor yang menyebabkannya cukup variatif. Dalam ranah keagamaan, beberapa hal yang melatarinya antara lain: beban historis yang serupa, common enemy, aspek sosial politik, penafsiran doktrin teologis, dan logika kelompok yang sempit.
Sebagai contoh ilustratif mengenai penafsiran eksklusif dan logika parsial-eksklusif di atas, dalam dunia Muslim terdapat hadis tentang firqah. Bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, 72 akan celaka, yang 1 selamat.
Ada beberapa kelompok ekstrem yang memaknainya secara ‘egois’ dengan logika in-group yang parsial dan merasa ge-er bahwa mereka-lah yang satu itu, sehingga layak selamat. Jarang ada yang mengafiliasikan ke dalam 72 golongan yang akan celaka dan dengan begitu mereka akan memiliki semangat besar untuk membenahi diri dan kelompok agar kelak selamat dan terpilih sebagai golongan yang selamat itu.
Tawaran Nilai-nilai Ajaran Sufistik
Ada beberapa catatan atas tawaran moderasi beragama melalui sufisme. Menengarai serangkaian konflik keagamaan dan tantangan sosial di atas, memang sudah banyak upaya moderasi beragama dalam aneka format, namun baru sedikit yang mendayagunakan nilai-nilai tasawuf sebagai strategi implementatif. Padahal sebagai suatu ‘jalan spiritual menuju Tuhan’, ajaran sufi dalam tasawuf menawarkan metode penyucian diri dari multipotensi destruktif dan anasir buruk dalam internal individu.
Beberapa di antara tawaran moderasi beragama melalui sufisme atau nilai-nilai sufistik yang potensial dijadikan instrumen P/CVE sekaligus strategi moderasi beragama—minimal dalam internal umat Islam sendiri, antara lain:
- Muḥāsabah : Upaya instrospeksi, menghitung diri sendiri atau evaluasi personal mengenai baik dan buruk dalam semua aspek kehidupan yang telah dijalani. Melalui ini, individu atau kelompok akan lebih optimal dalam meredam sifat ‘ujub dan rasa superior mereka.
- Al-ḥazm : Sebuah tekad, keteguhan, atau juga kehati-hatian (circumspection) dalam menghukumi sesuatu. Ini potensial untuk mencegah over-generalization dan misjudgement yang keliru. Dengan kualitas ini pula kita tidak akan tergesa-gesa menjatuhi hukuman sesat atau bid’ah ke kalangan di luar kelompok kita (out-group).
- Tawāḍu’ : Sikap rendah hati yang akan menekan kecenderungan psikologis (individu maupun kelompok) yang gemar memaksakan klaim mereka dan mendevaluasi yang lainnya.
- Maḥabbah : Cinta, sebuah hal yang disepakati universal sebagai sesuatu yang mulia dan luhur. Dengannya, seseorang atau kelompok lebih bersifat empatik, altruis, dan tidak ringan hati untuk mendiskriminasi orang lain.
Apabila keempat tawaran moderasi beragama melalui sufisme atau nilai sufistik di atas diberdayakan sebagai langkah gradual, disisipkan ke modul P/CVE dengan penyesuaian model pelatihan, tidak menutup kemungkinan hal-hal tersebut dapat menepis potensi ekstremisme dan menanamkan nilai-nilai moderasi beragama. Dampaknya boleh jadi akan terasa dengan minimnya kecenderungan menuding sesat dan bersikap intoleran.
Demikian tulisan tentang tawaran moderasi beragama melalui sufisme. Semoga bermanfaat.[]