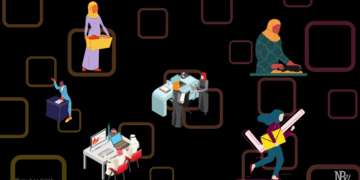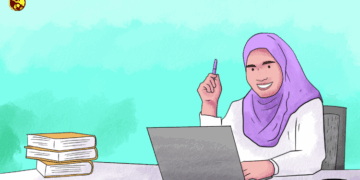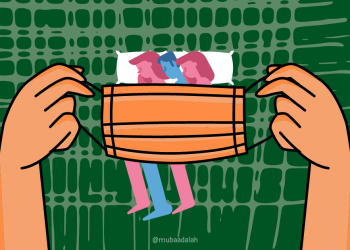Mubadalah.id – Tiga atau empat tahun lalu, ketika istri saya, Rizqa, memutuskan untuk berhenti bekerja dari profesinya sebagai seorang interior designer untuk menjadi ibu penuh waktu saja, saya katakan kepadanya, “Aku tidak memintamu berhenti. Ini sepenuhnya keputusanmu…”
Ia mengangguk. “Aku ingin di rumah, waktuku untukmu dan anak-anak saja.” Katanya. Sambil tersenyum.
Saya membalas senyumnya. Sambil memegang tangannya saya katakan, “Terima kasih. Tapi kamu bisa kembali kapan saja kamu mau,” ujar saya.
Rizqa mengangguk.
Sebagai seorang suami, saya sangat menghormati keputusan istri saya. Bagi saya, itu keputusan yang luar biasa—keputusan yang barangkali hampir semua suami mendambakannya. Tetapi, sebagai seorang pekerja di bidang kreatif, saya tahu betapa sulit melepaskan kerja kreatif yang sudah terlanjur kita cinta. Sebagai seorang penulis yang sudah menganggap aktivitas menulis sebagai bagian dari diri saya, saya mengerti sekali bahwa saya akan selalu merasa ada yang kurang jika saya tak bisa menulis.
Rizqa adalah seorang desainer. Dalam dirinya mengalir bakat yang luar biasa. Ia mencintai dunia seni dan desain, barangkali sebesar saya mencintai dunia sastra. Maka saya mengerti sekali betapa keputusan yang ia buat untuk berhenti dari dunia desain yang dicintainya bukan semata keputusan sederhana. Saya bisa merasakan bahwa suatu hari ia akan sangat merindukannya.
“Aku tetep bisa berkesenian dan nge-desain, kok.” Ujarnya, menghibur diri sendiri, ketika suatu hari saya tanya apakah ia kangen pekerjaannya lagi? Waktu itu saya memergokinya sedang asyik memerhatikan akun instagram temannya—dengan karya-karya terbaru yang ia unggah ke sana.
Saya tersenyum. “Mau nge-desain lagi?”
“Sering, kok.” Jawabnya. “Aku kan ikut bantuin ngasih pendapat untuk barbershop kamu, café dan kantor juga.” Sambungnya, “Sering juga nemenin Kalky ngegambar. Seru!” Katanya.
Saya tahu ia masih bersentuhan dengan dunia seni dan desain. Tetapi saya juga tahu bukan itu yang sebenarnya ia bayangkan. Setiap seniman dan pekerja kreatif selalu punya rasa ingin mewujudkan sesuatu, sebuah karya, sesuatu yang bisa ia banggakan karena keterlibatannya di dalam proses panjang pengerjaan ‘masterpiece’ itu.
***
Dengan rasa empati semacam itulah malam itu saya katakan kepadanya, “Bagaimana kalau sesekali kamu mengerjakan project interior lagi. Aku siapkan timnya?”
Ia melonjak mendengar tawaran saya. “Wah?” Matanya berbinar-binar.
“Kamu tetap bisa terlibat sebagai seorang desainer, mengerjakan project-project interior lagi. Dengan cara mengepalai sebuah tim. Tugas kamu mengelola project-project aja, biar tim yang mengerjakan urusan teknisnya. Bisa, kan?”
“Jadi aku akan tetap punya banyak waktu di rumah?”
Saya mengangguk. “Kamu perlu set up di awal aja. Siapkan tim ini. Meeting-meeting dengan kliennya. And let the magic happen!”
“Seru!” Ia melonjak. “Sekarang Alhamdulillah Kalky dan Kemi juga udah gede, Pi. Kalky sekolah seharian. Kemi juga bisa aku ajak-ajak, kok…”
Saya mengangguk. “Menurutku, anak-anak aman. Kamu tetap bisa jadi full time mother, kok… But also part-time designer.” Ujar saya, nyengir.
Rizqa mengangguk. “Aku mau update lagi biar tahu perkembangan desain interior sekarang.” Katanya.
“Sambil jalan aja…” Ujar saya.
Rizqa mengernyitkan dahi, “Maksudnya?”
“Ya, mulai segera?” Saya mengangkat dua bahu saya.
“Kapan?” Tanya Rizqa.
“Besok.” Ujar saya.
“Hah?” Rizqa tampak kaget.
Saya tersenyum. “Ini ada klien bagus. Temenku yang minta. Aku juga udah kontak dan set up tim desainer yang bakal bantu kamu untuk teknisnya. Kamu project manager-nya aja.”
Rizqa melongo.
“Besok meeting pertama, ya.” Ujar saya.
“Besok?” Rizqa masih tak percaya.
Saya mengangguk.
“Terus Kemi dibawa?”
Saya berpikir sejenak. “Jangan dulu lah. Nggak enak meeting pertama bawa anak. Mungkin kliennya akan kurang nyaman. Biar kamu nyaman dulu juga. Besok Kemi sama aku aja.”
Rizqa tersenyum. Lalu memeluk saya.
***
Hari ini, saya membawa Kemi ke kantor untuk menemani saya menjalankan aktivitas seharian. Mulai dari meeting sampai briefing pekerjaan bersama tim saya di kantor.
Sejak pagi Rizqa sudah bersiap untuk melakukan meeting pertamanya lagi setelah cukup lama. Saya bisa merasakan kegembiraannya. Saya bisa menangkap antusiasme dan semangat yang menyala di matanya.
Bagi saya, ini sederhana. Ini bukan tentang boleh atau tidak seorang istri bekerja. Bukan soal ‘bukankah lebih baik menjadi ibu penuh waktu yang mengurus anak-anak di rumah?’. Juga bukan soal ‘kan harusnya suami yang cari nafkah?’. Bukan.
Pertama, bagi saya ini bukan tentang pekerjaan. Ini tentang memberi kesempatan untuk Rizqa agar dia bisa bahagia dengan berkarya di bidang yang ia sukai. Kedua, Rizqa juga tetap bisa menjadi ibu penuh waktu untuk anak-anak kami—tidak salah kan kalau ia menekuni sesuatu yang ia cintai di waktu-waktu yang bisa ia sisihkan? Ketiga, ini juga bukan semata soal mencari nafkah. Saya sama sekali tak membebaninya dengan itu… Dia bahagia saja sudah istimewa. Dan kalau ada rejeki di tengah kebahagiaan itu, tentu itu lebih istimewa lagi.
Sebagai seorang suami, saya bahagia melihat istri saya bahagia. Jika dengan berkarya ia bisa menemukan dirinya seutuhnya, saya akan mendukungnya. Lagi pula, mengurus rumah bukan tanggung jawabnya sendirian kok… Saya juga harus terlibat. Mengurus anak-anak juga bukan sesuatu yang harus ia tanggung sendirian, saya pun harus berperan di sana. Dan saya? Untungnya saya bukan tipe suami yang minta ‘dilayani’ oleh istrinya, karena saya tak pernah sekalipun memandang istri saya sebagai seorang ‘pelayan’.
Selamat ‘bekerja’, Mami. Tapi jangan dibikin beban, jangan stress, anggap saja ini proses berkarya. Jika capek atau bosan, istirahat saja… Dan bisa mulai lagi kapan saja. Apapun yang penting membuatmu bahagia.
Jakarta, 7 Agustus 2017
FAHD PAHDEPIE