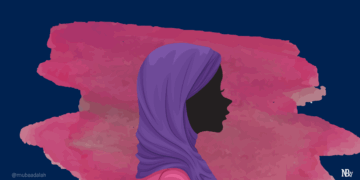Mubadalah.id – “Mak, besok Nok gak sekolah ya!” ucap Wasni setengah berteriak memastikan neneknya mendengar apa yang ia katakan, suaranya nyaris tenggelam oleh gemerisik angin yang mengayun-ayunkan batang padi di petak sebelah. Wasni masih sulit untuk mengatakan pada neneknya, bagaimana ia bisa meniru jejak Kartini tanpa kebaya?
Kedua tangannya trampil memilah padi basah, memisahkan dari sisa-sisa daun dan batang yang ikut terbawa. Karung usang milik neneknya menjadi alas sementara di atas pematang kecil yang lembab.
Sinar matahari menggantung tinggi di langit, memantul di permukaan air sawah yang tenang dan berkilauan. Udara lembab dan panas menyelimuti, bercampur dengan aroma khas tanah basah, lumpur, dan sisa batang padi yang basah dan mulai membususk. Sesekali terdengar lenguhan mesin perontok dari kejauhan, berpadu dengan suara deru sepeda motor atau mobil yang berlalu Lalang.
Neneknya, perempuan renta yang tubuhnya mulai bongkok itu, menoleh penasaran, keriput wajahnya mengerut.
“Loh… loh… Tumben, Nok. Kenapa?”
Ia beranjak dari petakan sawah yang masih tergenang air setinggi mata kaki. Saat kakinya terangkat dari tanah yang kehitaman, muncul bunyi kecipak lembut,bercampur bau khas yang tajam. Ujung celana panjangnya yang hitam sudah berubah warna menjadi kuning kecoklatan, penuh noda bekas tanah sawah. Ia mengelap tangan dengan ujung kaos berlambang obat semprot hama, yang sudah usang dan robek di beberapa bagian.
Perlahan ia menanjak ke tepian sawah yang berbatas langsung dengan jalan besar. Di sana, Wasni telah membersihkan padi, hasilnya mengais sisa-sisa butiran emas yang tercecer di antara jerami bekas mesin perontokan.
“Mataharinya terik sekali, Nok. Ayo kita istirahat dulu,” ajaknya, sambil menyeka peluh di dahi.
Kebaya dan Hari Kartini
Ia pun membuka cangkingan mengambil botol minum dari anyaman plastik bekas tempat berkat tahlilan. Caping ia lepas dari kepala dan diletakkan di sampingnya. Mereka berdua duduk bersandar di bawah pohon mahoni yang menjulang tinggi di pinggir jalan besar itu.
“Waktu hari Sabtu kemarin, ibu guru bilang hari Senin besok anak-anak harus pakai kebaya, Mak… Tapi Nok kan nggak punya kebaya…” ucap Wasni lirih. Ia menyambut botol minum yang disodorkan neneknya, meneguknya pelan di bawah pohon mahoni yang rindang.
Neneknya hanya diam mendengarkan, sembari menatap wajah cucunya yang tertunduk lesu. Ada rasa kasihan yang menyelusup di hatinya. Ia paham betul perasaan Wasni, sekaligus menyadari betapa sulit keadaan mereka.
“Yang lain pakai kebaya, Nok Wasni pakai baju muslim baru aja yang dibeli pas Lebaran kemarin. kan masih bagus?” ucap nenek mencoba menghibur, membuka kantong plastik yang berisi bekal mereka siang itu.
“Bukan baju muslim, Mak… Ibu guru bilang harus kebaya.” suara Wasni tetap pelan, tapi tegas.
“Memangnya kenapa harus kebaya, Nok? Yang penting bajunya bersih dan rapi, ya kan?” sangkal neneknya, mencoba menyembunyikan kecemasan akan perasaan cucunya. Tangannya sibuk membagikan nasi dilengkapi sambal terasi dan satu bungkus kecil kerupuk.
“Kata ibu guru, sekolah mau mengadakan karnaval hari Kartini, Mak. Semua anak perempuan satu sekolah harus pakai kebaya. Nok malu kalau pakai baju yang beda sendiri… Takut di olok-olok lagi kaya tahun kemarin. Masak hari Kartini tanpa kebaya”
Ia menggenggam botol minum dengan erat, suaranya mengecil dan parau.
“Bukan cuma baju, Mak… Mereka juga rias wajah di salon. Nok nggak sanggup kalau harus jalan bareng mereka tapi beda sendiri…”
Sejenak neneknya terdiam. Lalu dengan lembut ia menyodorkan plastik berisi nasi itu ke pangkuan cucunya.
“Ya sudah… Besok nggak usah berangkat sekolah. Sekarang Nok Wasni makan dulu ya.”
Karnaval Hari Kartini
Sambil mengunyah perlahan, Wasni menunduk, matanya menatap nasi di pangkuannya. Udara terasa makin panas, meski mereka berteduh di bawah pohon mahoni yang lebat.
Neneknya memandang sejenak, lalu bertanya dengan suara lirih, “Nok… Karnaval itu maksudnya apa, sih? Maju di atas panggung gitu, ya?”
Wasni menggeleng pelan, lalu menjawab sambil mengelap peluh di pelipisnya. “Enggak, Mak. Tahun lalu tuh, dari kelas satu sampai kelas enam baris memanjang sambil jalan kaki, keliling gang kampung deket sekolah.”
“Oh gitu…” sahut neneknya, tersenyum simpul. “Emak kira tadi kayak nembang atau jogged atau drama di atas panggung.”
Ia terkekeh kecil, namun ada nada getir yang tersembunyi di ujung tawanya. Matanya kembali menatap cucunya, gadis kecil kelas tiga sekolah dasar yang sejak balita telah ia besarkan sendiri. Orang tua Wasni meninggal dunia saat pandemi COVID-19 melanda beberapa tahun silam.
Ia tahu betul, keinginan cucunya itu bukan semata soal kebaya, tapi cerminan dari penerimaan atas kenyataan hidup mereka. Kehidupan yang tak memberi ruang untuk sekadar membeli, bahkan menyewa. Tahun ini seperti tahun-tahun sebelumnya, hari Kartini tanpa kebaya, apalagi jika harus membayar rias wajah. Tapi di lubuk hatinya yang paling dalam, emak bersyukur.
Wasni tumbuh jadi pribadi periang yang kuat, tidak manja, dan tahu diri. Ia tahu kapan harus meminta, dan tahu pula kapan harus diam dan menerima. “Sing gede milik rejekine, Nok,” gumam nenek itu pelan, nyaris seperti doa yang ia layangkan pada langit.
Sementara itu, suara bising kendaraan berlalu-lalang memecah kesunyian hutan yang beralih fungsi menjadi tanah garapan pesawahan. Di musim panen seperti ini, jalan jadi ramai seperti jalan pantura saat musim mudik. Sepeda motor berlalu kencang, kebanyakan dikendarai para buruh tani yang menawarkan jasa derep (memanen padi).
Es Dawet dan Buruh Tani
Truk-truk besar bermuatan gabah menjulang lalu-lalang, suaranya bising mengerang keberatan. Di sepanjang jalan, para pedagang keliling membuka lapak dadakan, ada yang menjajakan es, kopi, gorengan, hingga makanan berat di bawah tenda seadanya.
“Mang, tuku!” seru emak sambil melambaikan tangan, memanggil tukang es dawet yang melintas.
“Satu, ya, Mang!” lanjutnya sambil tersenyum lelah.
Penjual es dawet itu menepikan sepeda motornya dekat mereka beristirahat. “Sudah dapat reminya, Mak?” tanyanya sambil menuang es ke dalam gelas plastik.
“Ya, alhamdulillah, dapat mungkin sekitar dua ember.” sahut emak sambil menunjuk tumpukan biji padi yang tadi sudah dibersihkan Wasni.
“Berapa, Mang?” tanyanya lagi, tangan keriputnya mulai membuka lipatan tali kain di pinggang, benting setia yang sehari-hari ia pakai untuk menyimpan uang receh. Ia keluarkan selembar uang lima ribuan yang sudah agak kusut, lalu menyodorkannya pelan.
“Udah, Mak. Simpan saja uangnya.” tukas si penjual sambil tersenyum.
“Eh, Mang… saya mau beli.,” jawab emak memastikan.
“Gratis, Buat emak sama cucu. Alhamdulillah, hari ini rezeki saya banyak. Es nya sudah hampir habis, dan ini yang penghabisan.”
“Alhamdulillah kalau begitu. Makasih, ya, Mang…” ujar emak tulus. Uang lima ribu itu ia lipat kembali, lalu ia selipkan di lipatan tali kain dan diikatkan lagi erat-erat di pinggang.
“Ini, Nok… diminum esnya. Seger, biar semangat. Nanti kalau udah habis, kita pulang aja ya. Kayaknya ini udah masuk waktu duhur. Emak juga udah capek,” katanya sambil menyerahkan es ke tangan cucunya.
Wasni mengangguk pelan. Ia terima es itu, lalu meminumnya perlahan kemudian menyodorkan gelas itu ke neneknya,memastikan neneknya juga menikmati nikmatnya es dawet di Tengah Lelah dan panasnya cuaca.
Pulang
Setelah tukang es berlalu, nenek itu segera merapikan biji padi yang tadi telah ia pilah dan dibersihkan. Tangannya yang cekatan memasukkan butir-butir padi itu ke dalam sebuah karung kecil bekas beras bulog yang ia terima dari pemerintah desa.
Sementara itu, Wasni membereskan bekas makan mereka, melipat plastik alas nasi, dan memasukkan botol minum yang airnya tinggal setengah ke dalam cangkingan anyaman plastik. Cangkingan itu kemudian ia gantungkan di setang sepeda jengki neneknya, di bagian kiri. Sementara ember tempat memuat padi sisa panen, ia letakkan di sisi kanan.
Neneknya mengikat karung kecil berisi padi itu dengan tali rafia, lalu mengangkatnya ke boncengan. Wasni duduk di bagian belakang sambil memangku karung tersebut. Di bawah sengatan terik matahari, sang nenek yang usianya sudah menginjak kepala enam, tetap kuat mengayuh sepeda di jalanan yang berdebu dan panas.
Jarak tempuh menuju rumah mereka sekitar dua belas kilometer. Tapi bukan soal jaraknya yang berat, melainkan arah tujuan yang tak pasti. Mereka tak pernah benar-benar tahu akan berhenti di mana, karena sejak pagi berangkat dari rumah, yang mereka tuju hanyalah sawah-sawah bekas panenan. Di sanalah mereka mengais sisa-sisa biji padi yang jatuh dari mesin perontok dan tidak diambil pemiliknya.
Bermimpi Menjadi Seperti Kartini
Dengan stelan baju dan celana panjang yang sudah lusuh, serta kerudung tipis yang membalut kepala, Wasni tak terlalu merasa panas. Semilir angin yang menerpa wajahnya saat sepeda terus melaju, sedikit banyak membantu mengusir gerah yang menempel.
“Mak,” ucap Wasni pelan di tengah perjalanan, “Kata Bu Guru, ibu Kartini itu pahlawan negara kita. Beliau pejuang. Bu Guru bilang, berkat perjuangannya membela perempuan, sekarang Wasni dan teman-teman perempuan lainnya bisa bersekolah.”
Neneknya hanya mengangguk pelan, mendengarkan sambil sesekali menarik napas panjang untuk mengatur tenaga di sela kayuhan sepedanya.
“Ibu kita Kartini… putri sejati… putri Indonesia, harum namanya…”
Lagu itu Wasni nyanyikan lirih namun penuh semangat. Sepanjang jalan pulang, ia terus mengulang bait-bait lagu yang diajarkan gurunya saat Sabtu kemarin, seperti sebuah penghiburan sekaligus pengingat bahwa meski hidup mereka sederhana, dan ia tak memiliki kebaya, ia masih bisa bermimpi dan belajar seperti yang dulu diperjuangkan oleh Ibu Kartini. []
Jatimunggul, 21 April 2025.