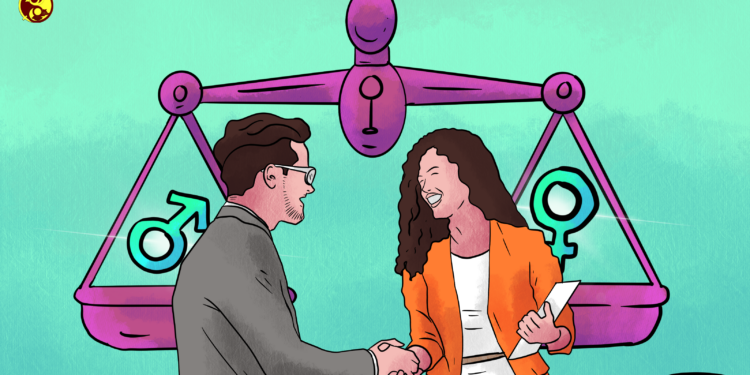Mubadalah.id – Empat tahun lalu, tepat setelah perayaan Idulfitri pasca kelahiran anak pertama, seorang kerabat menanyakan kepada istri saya mengenai rencana menambah anak.
Pertanyaan tersebut belum sempat dijawab oleh istri saya, karena kerabat lain langsung menimpali dengan pernyataan bahwa perempuan yang berkarier tidak mungkin memikirkan untuk memiliki anak lagi.
Pernyataan tersebut membuat istri saya menunjukkan ekspresi tidak setuju. Saya kemudian memahami respons tersebut sebagai bentuk ketidaknyamanan.
Kerabat tersebut selanjutnya menyampaikan pandangan mengenai peran perempuan yang dinilai seharusnya terbatas pada mengurus anak, rumah tangga, serta kewajiban untuk taat kepada suami.
Menanggapi pernyataan tersebut, saya hanya tersenyum dan menyampaikan ketidaksetujuannya secara singkat. Saya mengibaratkan rumah tangga seperti kendaraan yang memiliki dua penggerak roda, sehingga beban yang kita bawa akan terasa lebih ringan.
Menurut saya, jika suami dan istri sama-sama bekerja, maka beban rumah tangga dapat kita topang secara bersama.
Namun, pernyataan tersebut ditolak oleh kerabat yang bersangkutan tanpa disertai argumentasi yang jelas. Penolakan tersebut mencerminkan pandangan yang masih banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
Pandangan semacam itu, menurut saya, berangkat dari anggapan bahwa pekerjaan domestik bukanlah pekerjaan. Aktivitas seperti mencuci, mengurus anak, dan mengelola rumah tangga sering kali tidak mereka pandang sebagai bentuk kerja, melainkan sebagai kewajiban istri dalam rangka ketaatan kepada suami.
Saya kemudian mengutip buku Dari Aborsi sampai Childfree: Bagaimana Mubadalah Berbicara? yang menyebutkan bahwa hukum perempuan bekerja dalam Islam adalah boleh.
Namun, dalam praktiknya, kebolehan tersebut sering dengan syarat tidak menimbulkan fitnah atau gangguan, terutama bagi laki-laki. Pandangan ini menunjukkan kecenderungan bahwa perempuan lebih berpotensi menimbulkan fitnah di ruang publik daripada laki-laki.
Secara prinsip, perempuan bekerja untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga. Bekerja dipandang sebagai hak dasar setiap orang yang beriman, tanpa membedakan jenis kelamin.
Bekerja
Masih dalam buku yang ditulis oleh Faqihuddin Abdul Kodir, disebutkan bahwa bekerja tidak hanya penting dalam Islam, tetapi juga merupakan perwujudan langsung dari keimanan kepada Allah Swt. dan Nabi Muhammad Saw.
Dalam Al-Qur’an, kata yang bermakna bekerja, seperti ‘amal, kerap beriringan dengan kata iman. Kedua kata tersebut tercatat di lebih dari 56 tempat dalam Al-Qur’an, yang menunjukkan bahwa bekerja merupakan karakter seorang Muslim dan Muslimah.
Hal tersebut seperti dalam firman Allah Swt.:
مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ
“Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka Kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan” (QS. An-Nahl: 97).
Ayat tersebut secara tegas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama untuk bekerja dan berbuat kebaikan, dengan janji balasan kebaikan dari Allah Swt. tanpa pembedaan.
Saya mempertanyakan pandangan yang masih kuat di masyarakat yang cenderung mendomestikasi perempuan. Perempuan sering kali kita posisikan bukan sebagai subjek penuh, melainkan sebagai pelayan laki-laki. Saya mempertanyakan asal-usul pengetahuan dan pandangan tersebut.
Padahal, perempuan yang bekerja di ruang publik pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan diri, anak, dan keluarga. Sebab, keluarga bukan hanya milik suami, tetapi juga milik istri.
Ketika keluarga kita topang secara bersama, maka urusan rumah tangga akan terasa lebih ringan. Prinsip saling menopang antara suami dan istri dipandang sebagai cara untuk membangun keluarga yang bahagia dan berkeadilan. []