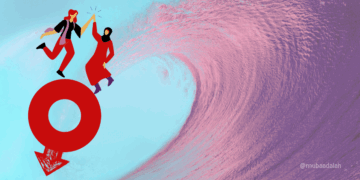Mubadalah.id – Dalam adab al-mu‘āsharah, ada relasi yang di permukaan tampak baik-baik saja. Kita tidak melihat pertengkaran besar dan tidak menemukan pelanggaran yang tampak jelas. Banyak orang bahkan sering menyebutnya sebagai relasi yang “sudah sesuai ajaran”. Dalam kondisi seperti ini, orang jarang meluapkan konflik, tetapi secara perlahan kehilangan ketenangan batin.
Keadaan ini terasa semakin sulit karena rasa tersebut sering tidak menemukan bahasa untuk diungkapkan. Banyak orang menganggap hal itu wajar, karena meniatkan sebagai bentuk kebaikan dan kepatuhan. Akibatnya, orang memilih diam, bukan karena tidak sakit tetapi karena tidak tahu harus menyebutnya sebagai apa. Sebab secara aturan, semuanya tampak benar.
Di titik inilah kita perlu berhenti sejenak dan kembali pada adab al-mu‘āsharah sebagai etika relasi gender dalam Islam. Bukan untuk menyalahkan siapa pun, melainkan untuk bertanya dengan jujur. Apakah relasi yang sah secara hukum selalu berarti adil bagi manusia yang menjalaninya?
Adab al-Mu‘āsharah: Relasi sebagai Cara Hidup Bersama
Dalam khazanah Islam klasik, para ulama tidak memahami relasi antar manusia sebagai urusan teknis semata. Ia merupakan bagian dari cara hidup. Karena itu, para ulama tidak cukup berbicara tentang apa yang boleh dan tidak boleh, tetapi juga tentang bagaimana manusia seharusnya hadir dalam hubungan dengan orang lain.
Konsep adab al-mu‘āsharah lahir dari kesadaran ini. Mereka mengajarkan bahwa hidup bersama menuntut kepekaan. Dalam relasi, kita menilai tindakan bukan hanya dari sisi hukum, tetapi juga dari dampaknya. Apakah kehadiran seseorang menghadirkan rasa aman, penghargaan, dan pengakuan bagi orang lain.
Para ulama klasik menyadari bahwa relasi, terutama relasi lintas gender adalah ruang yang sangat rawan. Sehingga adab al-mu‘āsharah menjadi penyangga utama dalam etika relasi gender. Oleh karenanya, para ulama tidak berhenti pada pembahasan hak dan kewajiban. Mereka juga mengarahkan perhatian pada bagaimana keadilan benar-benar dirasakan dalam keseharian. Dalam relasi suami–istri, misalnya, mereka tidak hanya menanyakan siapa yang memimpin, tetapi juga menilai apakah kebersamaan itu menghadirkan ketenteraman atau justru menumbuhkan ketakutan yang sunyi.
Keadilan sebagai Ruh Syariat
Ibn Qayyim al-Jawziyyah menegaskan kesadaran ini dengan sangat jernih. Dalam salah satu karyanya, beliau menulis:
إِنَّ الشَّرِيعَةَ مَبْنَاهَا وَأَسَاسُهَا عَلَى الْحِكْمَةِ وَمَصَالِحِ الْعِبَادِ، فِي الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ، وَهِيَ عَدْلٌ كُلُّهَا، وَرَحْمَةٌ كُلُّهَا، وَمَصَالِحُ كُلُّهَا، وَحِكْمَةٌ كُلُّهَا
“Syariat dibangun di atas hikmah dan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Ia seluruhnya adalah keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah.”
(I‘lam al-Muwaqqi‘in, Juz 3, hlm. 3)
Melalui kalimat tersebut, Ibn Qayyim tidak sedang memuji syariat secara abstrak. Akan tetapi justru memberi ukuran, bahwa hukum Islam tidak mempunyai tujuan untuk mengasingkan relasi. Ketika keadilan dan rahmah tidak lagi terasa, maka yang hilang bukan sekadar kenyamanan, melainkan ruh dari ajaran itu sendiri.
Gagasan adab al-mu‘āsharah ini sejalan dengan prinsip kesalingan yang selama ini menjadi perhatian dalam pembahasan relasi gender di Mubadalah.
Ibn Qayyim bahkan melangkah lebih jauh ketika mengatakan:
فَأَيُّ طَرِيقٍ أُخْرِجَتْ مِنَ الْعَدْلِ إِلَى الْجَوْرِ… فَلَيْسَتْ مِنَ الشَّرِيعَةِ
“Setiap jalan yang keluar dari keadilan menuju kezaliman, maka ia bukan bagian dari syariat, meskipun dimasukkan ke dalamnya dengan berbagai penafsiran.”
(I‘lam al-Muwaqqi‘in, Juz 3, hlm. 11)
Ketika Relasi Tampak Benar, tetapi Melelahkan
Pandangan Ibn Qayyim ini terasa dekat dengan kehidupan kita. Ada relasi yang tampak tenang di luar, tetapi di dalamnya satu pihak selalu harus menyesuaikan diri. Misalnya, seseorang berhati-hati dalam berbicara, memilih diam agar tidak memicu tudingan melawan, dan mengalah supaya konflik tidak terjadi.
Di sinilah pesan Ibn Qayyim tentang adab al-mu‘āsharah dan keadilan relasi menjadi terang. Menurut Ibn Qayyim, agama hadir untuk menjaga manusia tetap utuh dalam relasi, bukan untuk mengecilkannya. Ketika sebuah hubungan berjalan tanpa keadilan dan rahmah—meskipun orang membungkusnya dengan penafsiran dan dalil—kita bukan hanya kehilangan kenyamanan, tetapi juga kehilangan ruh syariat itu sendiri.
Membaca adab al-mu‘āsharah melalui lensa keadilan Ibn Qayyim membuka jalan pulang. Keadilan gender bukanlah agenda asing yang dipaksakan ke dalam Islam, melainkan nilai inti yang sejak lama hidup dalam tradisi keilmuan Islam sendiri.
Ibn Qayyim menegaskan, bahwa keadilan bukan sekadar konsep hukum, tetapi ruh yang menghidupkan relasi. Ketika kita benar-benar merasakan keadilan dan rahmah, agama tidak lagi kita jalani sebagai beban yang harus kita pikul sendirian, melainkan jalan pulang bagi siapa pun yang sedang belajar hidup bersama.
Barangkali persoalan terbesar dalam relasi hari ini bukan karena kita kekurangan ajaran, tetapi karena kita terlalu jarang bertanya tentang “rasa” yang ditinggalkan oleh sebuah hubungan: apakah ia membuat manusia bertumbuh, atau justru mengecil perlahan demi menjaga semuanya tetap tampak baik-baik saja?