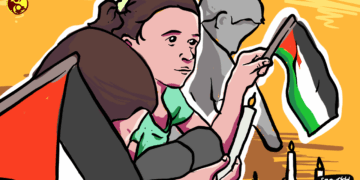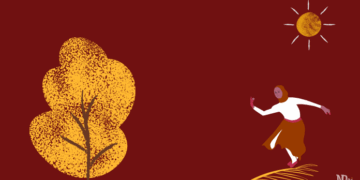Mubadalah.id – 7 April kemarin adalah tepat 100 tahun usia Annemarie Schimmel, seandainya ia masih hidup. Perempuan kelahiran Erfurt, Jerman pada 1922 ini adalah sosok perempuan cemerlang pada masanya. Baru berusia 21 tahun, di saat gadis seusianya sibuk bersolek, shopping, atau healing dan khataman drakor (drama korea), Annemarie Schimmel sudah meraih gelar doktor bidang Bahasa dan Peradaban Islam dari Universitas Berlin.
Selang 2 tahun, di usia 23 Annemarie Schimmel telah didapuk sebagai profesor bidang Kajian Islam dan Arab di Universitas Marburg, Jerman—yang sekaligus merupakan almamater tempat ia menapaki studi doktor keduanya dalam konsentrasi Sejarah Agama.
Entah jika ia hidup di abad terkini, dengan medsos dan industri hiburan yang begitu merampok waktu, tidak jelas apakah Annemarie Schimmel akan tergoda untuk hedon ataukah tidak. Yang pasti, ia menjadi teladan bagi perempuan di mana pun agar teguh dan tekun bertungkus-lumus dalam belajar sepanjang hidup sambil menyelami samudera keilmuan.
Hingga tiba pada titik periode yang krusial dalam hidupnya, 1954, titik zaman tatkala Uni Indonesia-Belanda menjelang dihapuskan, berlangsung konflik di Suriah (25 Februari), penangkapan Khomeini, awal perang kemerdekaan di Aljazair, sampai kelahiran Hugo Chavez. Pada peta waktu itu pula ia diamanahi mengajar selaku profesor Sejarah Agama di Universitas Ankara, Turki. Di tahun inilah Annemarie Schimmel menelaah secara intensif mulai dari kebudayaan religius spiritual sampai praktik sufisme yang ada di Turki.
Bagai seorang manusia pada umumnya yang lagi disambar jatuh cinta, Annemarie Schimmel keranjingan Rumi—sufi cum penyair besar yang sedang diperingati hari lahirnya 17 Desember 1954. Denyar nafas kota Konya masa itu, desir angin, gemerisik dan suara tapak kaki puitis para peziarah Rumi, membawa batin profesor perempuan muda itu seolah menari khusyuk di semesta bisu. Rumi kadung menyelusup ke relung pedalamannya dan menjadi inspirasi sekaligus penenang hatinya sampai ajal menjemput.
Walau terlahir di keluarga Protestan dengan budaya famili kelas menengah Erfurt, ia hampir bisa dikatakan begitu obsesif mendalami tasawuf, sampai bahkan menulis banyak karya tentangnya. Bukan cuma itu, biografi tebal mengenai Nabi Muhammad pun, And Muhammad Is His Messenger (1985) ia gubah secara mengalun, ritmis, dan menyihir. Sebuah karya yang melibatkan sisi emosional pembaca, hingga tak jarang yang menangis.
Lewat karya biografi tersebut, ia mengilustrasikan ulang karya Sir Muhammad Iqbal dalam Javidnama dengan jitu bagaimana kekesalan Abu Jahal kepada Nabi Muhammad:
“Sungguh sakit sekali hati kami ini karena Muhammad!
Ajarannya telah memadamkan cahaya-cahaya Ka’bah.
Ajarannya menghapus perbedaan-perbedaan ras dan darah.
Walau ia sendiri Quraisy, dia mengingkari superioritas Arab.
Dalam agamanya, yang tinggi dan rendah satu saja.
Dia makan bersama budaknya dari piring yang sama!”
Dalam pengembaraan intelektual bin spiritual itu pula, Annemarie Schimmel mendadak seperti munsyi dan juru cerita yang piawai, lantas menulis:
“Di Konya, di sana, kita dapat melihat sebuah sungai kecil, di tepi sungai itulah Maulana sering bertamasya bersama murid-muridnya; suara kincir air dan gemuruhnya air sungai sering mengilhaminya untuk berputar-putar atau membawakan syair-syair yang menunjukkan bahwa suara kincir dan gemuruhnya sungai menjadi lambang kehidupan.” (dalam Akulah Angin Engkaulah Api, hlm. 23)
Secara puitis ia melanjutkan ceritera: “Dan Maulana akan menyanyikan lagu tentang bunga-bunga dan semak-semak yang tumbuh di tepi sungai. Dia dapat memahami suara bunga-bunga dan semak-semak itu.”
Disiplin, Puitis, dan Penuh Dedikasi
Berkaca pada sepak terjang hidup Annemarie Schimmel yang gemilang, pada tahun 1967-1992 ia menjadi professor di Harvard University dan mengampu program studi Indo-Muslim. Ingatannya begitu kuat, hingga tidak sedikit yang menyebutnya hampir seperti photographic memory, terutama jika menyangkut kaligrafi. Dari situ, dan di zaman kebak perang dan krisis tersebut, dia akhirnya disematkan sebagai the first woman and the first non-Muslim yang mengajar teologi di universitas.
Akan sangat rugi jika sebagai kaum internal Muslim kita tidak meneladani Annemarie Schimmel. Sosoknya penuh dedikasi, kecintaan yang jujur, disiplin riset dan gairah positif dalam produksi pengetahuan. Karya-karyanya tercatat lebih dari 50 judul dan sangat berpengaruh dalam peta akademik studi Islam. Ia adalah ‘raksasa’ di bidang sufisme dan studi Islam.
Namun, terlepas dari pencapaian kemilau itu, sebagai akademisi Annemarie Schimmel tidak berhenti pada analisis dan telaah intelektual kognitif an sich. Lebih dari itu, ia menapaki jalanan Konya, dari masa sebelum Metropolit, sampai megah dan semakin modern. Ia menyesapi habis sari-sari rohani yang terkandung dalam sajak gubahan para sufi terdahulu. Terhuyung dalam gelombang cinta dan dendam rindu yang turun temurun dari generasi ke generasi.
Pada usianya yang sepuh pun ia masih bersuntuk-suntuk dengan aksara, teks-teks keagamaan, dan karya tradisi spiritual mulai dari bahasa Ibrani, Arab, Turki, Persia, Urdu, hingga Sindikh. Mengenai dedikasi yang tak kenal lelah tersebut, ia pernah menulis dalam A Life of Learning, “Setiap pengalaman mesti dimasukkan ke dalam kehidupan untuk memperkaya kehidupan itu sendiri. Sebab tak ada kata selesai dalam belajar, seperti juga tak ada akhir dalam kehidupan.”
Dan tidak disangka, di tahun 2001 Annemarie Schimmel diundang Gus Dur (saat menjabat Presiden) ke istana dan esoknya foto beliau berdua muncul di Headline Kompas. Sebuah pertemuan yang sayangnya kurang mendapat perhatian.
Tiba ketika wafat pada 2003, banyak sarjana yang berduka, meskipun tidak sedikit juga yang mengkritiknya saat meraih banyak penghargaan—salah satunya Jürgen Habermas. Apakah mungkin karena dia perempuan di dunia yang dipenuhi patriarki? Ataukah karena bagi banyak pihak karyanya terlalu sentimental dan kurang akademis? Di luar itu semua, Stephen Kinzer menulis sebuah obituari untuk Schimmel dengan penuh hormat dan menyebutnya sebagai the 20th century’s most influential scholars of Islam.
Dan diam-diam, Annemarie Schimmel sudah merancang wasiat agar batu nisannya—di Bonn, Jerman—diukirkan sebuah kutipan syahdu dengan aksara Arab berbunyi: “an-nāsu niyāmun, fa idzā mātū intabahū.” Manusia itu tidur. Ketika mati barulah mereka bangun.
Sanggupkah kita, baik perempuan maupun laki-laki, meneladani beliau dalam hal dedikasi dan produktivitas yang tak kenal lelah di zaman yang penuh godaan hedon ini? []