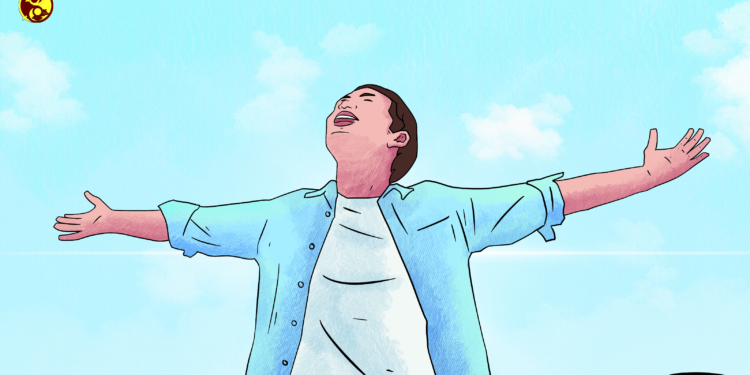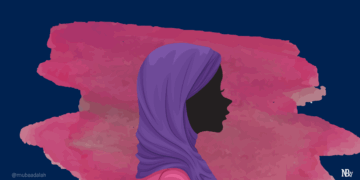Mubadalah.id – Hujan atau tak hujan sama saja. Aku tetap berjalan sendirian. Juga hujan kali ini, musim ini, dan saat ini. Aku tetap berdiri sendirian, berjalan dengan payungku yang tetap sama seperti sejak dulu. Berwarna pink dan bermotif bunga krisan abu-abu.
Masih sendiri. Itu benar, dalam hari-hari. Tapi musim hujan kali ini, jiwaku diajari sebuah hal. Hal itu yang sedang kurasakan saat ini juga. Berdiri di depan ruang F1, menatap ke samping, menatap gerimis deras yang membasahi rumput-rumput, melihat pertunjukan angin yang bergerak menggugurkan daun-daun beringin. Dan menatap satu jiwa yang sama sekali aku belum mengenalnya.
Dan meski demikian, hati tak bisa berbohong saat sosok itu melewatiku begitu saja. Ada yang berdebar, berdesir, berbisik, dan tersentuh.
“Ikuti sebelah jiwamu yang berjalan.” Sebuah suara memasuki telingaku.
Suara Hujan
Dan aku mengikuti dia yang berkemeja hitam. Aku berjalan di belakangnya dan ternyata langkahnya sangat cepat, membuatku semakin berdebar. Ya, aku serasa mengejar bintang jatuh. Yang mungkin jatuhnya di sebuah bukit asing, atau padang rumput yang tak terjangkau, atau bahkan sebuah lahan antah berantah.
Tak perduli apa aku bisa menggapainya atau tidak, aku hanya ingin mengikutinya. Melihat sampai mana bintang jatuh itu menjauh, pergi, dan menghilang.
Dia menaiki motor, pada akhirnya. Aku berhenti, melihat bagaimana dia mengenakan jaketnya, mantel hujannya, dan mulai menstarter motornya.
“Tolong jangan pergi dulu, berpalinglah sebentar, aku di belakangmu!”
Hatiku berkata padanya. Tapi hati yang sangat peka terhadap bebunyian itu ternyata tak punya suara, ah sebenarnya aku tak menyuruh kepada yang seharusnya saja.
Diapun akhirnya melaju, menjauh, menuju gerbang. Tiba-tiba hujan semakin deras dan terus berlanjut. Sementara aku tak bisa berbuat.
Tik-tik. Selalu saja rintik hujan. Satu tetes menetes ke hatiku, memberitahuku bahwa hujan akan bertambah deras hingga malam hari, sampai besok, atau besoknya lagi.
“Tidakkah kau ingin melihat dia lagi sebelum hujan lusa? Dan aku yakin kau menjawab iya, menginginkannya.” Ucap hujan yang makin deras merintik. “Sekarang, ayolah berlari. Aku akan menuntunmu.” Demikian hujan kembali berkata padaku dan akupun langsung berlari. Mengejarnya, mengejar sebagian jiwaku.
Aku terus berlari, menyusuri jalan raya, dengan mata tetap menatap padanya yang semakin kencang saja. Lama-lama nafasku tersengal, terpotong-potong. Perlahan, dia mulai jauh dan akhirnya tak terlihat. Aku masih berlari… tapi pandanganku semakin kabur.
Jatuh Cinta Kepada Hujan
Aku jatuh cinta. Ya, karena aku selalu melakukan ini, berlari-lari, selama satu tahun. Akhirnya tiga kata itu aku temukan, setelah sekian lama aku penasaran: kini aku merasakannya! Dan perasaan itu, aku mencoba mengartikannya, emm… dengan kata yang sedikit berlebihan misalnya kata-kata seperti cintanya awan kepada langit, samudera kepada daratan, atau hidup kepada mati.
Tapi hari ini, bagiku, cinta lebih sederhana dari semua itu.
Aku tak butuh berjumpa dengannya untuk bisa mengenalnya. Tak butuh bersama untuk saling mengerti. Tak butuh bergenggaman tangan untuk sebuah kekuatan. Dan tak butuh alasan apapun untuk mencintainya. Terjadi begitu saja, mengalir seperti air dan indah sampai aku tak bisa memahaminya. Luar biasa.
“Kamu bilang akan menuntunku, nyatanya tidak!”. Aku protes pada hujan.
Hujan tidak menjawab, ia hanya reda, menghentikan rintiknya. Lalu hening. Dan aku tak bisa melakukan apapun kecuali kulangkahkan kakiku ke arah yang berlawanan dengannya, aku kembali.
Pertemuan di Boulevard
Saat aku sedang berada di antara halaman-halaman kisah hujan, sebuah kertas terjuntai dari balik buku catatan bercover hitamku.
Kamu akan menuntun dirimu sendiri padaku dan itu bukan urusan hujan, jadi keluarlah sekarang!
Kertas itu ku genggam. Aku berlari menuruni tangga, dan keluar dari perpustakaan. Dan… aku melihatmu lagi. Bukan di tempat parkiran, tapi di jalanan yang hujan itu, kamu sedang melangkah di tengah Boulevard, aku segera mengejarmu. Namun setelah aku sampai tepat di belakangmu, aku berhenti. Aku tak berani menyapamu. Diam dan hanya ada suara detak jantungku yang seirama dengan rintik hujan.
“Jadi, kamu yang selama ini selalu mengejarku dalam hujan? Diam namun hatimu penuh pertanyaan.” Kamu berkata demikian, namun tidak menoleh, tubuhmu masih menghadap ke depan. Menyadari bahwa aku berjalan di belakangmu padahal langkahku tak berbunyi.
Aku diam, menunduk. Tik-tik hanya suara hujan.
“Masih tidak berani menatapku?” Ucapmu sambil menghela nafas, lalu kamu menghentikan langkah dan berbalik menatapku, “Aku sudah mengenalmu dan kamu juga sudah mengenalku. Bukankah kamu tahu siapa hujan itu? Hujan adalah aku. Dan kamu mendapatkannya”. Aku tidak bisa berkata, detak jantungku menghalangi suaraku. Namun kini aku tahu bahwa permasalahanku pada hujan telah selesai.
Kau menggenggam tanganku dan membawaku berjalan bersamamu, hujan-hujanan. Kita mengelilingi Boulevard dua kali lalu melaju ke arah lain. Dan di jalan raya itu, aku melihat lagi masa-masa yang telah lalu.
Masa-masa di mana saat aku melihati jari-jemarimu di podium dengan berdebar, kamu juga ternyata menatapku dengan berdebar. Saat-saat di mana aku mencuri fotomu di album kenangan, kamu juga ternyata mencuri fotoku di album lain. Saat kita saling mencuri informasi tentang nama, ruang kelas, buku kesukaan, aktivitas harian. Namun dengan nama yang berbeda, di tempat yang berbeda; Aku menamai kau misteri, kau menamaiku perempuan fiksi.
Kau di kampus, aku di sekolah dasar. Lalu kau di perpustakaan besar, aku di taman baca kecil pojok sekolahan. Kau dengan bendera berlogo ‘bintang dan gerigi’ di jalanan, aku dengan es krim rasa stroberi yang melumuri pipi. Kau dengan payung perjuangan, aku dengan krayon warna-warni kehidupan.
Aku Menamaimu dengan Sebutan Hujan
Lalu setahun belakangan, aku menamai kau dengan sebutan hujan. Sebab sejak tragedi itu, yang menyandera senyummu dan kemampuan berjalan cepatmu, kau terlihat lelah dan sorot matamu bergerimis. Aku membaca; melihat dari kejauhan, bagaimana kau goyah dan hampir runtuh.
Lalu aku berkata “kuatlah”, namun suaraku terlalu lirih. Aku berkata “tak apa kau punya aku”, namun kata itu tak pernah terdengar olehmu. Karena hidupku sendiri terlalu gelap untuk bisa menjangkaumu dalam raga.
Lalu suatu hari kuputuskan untuk mencuri malam dan membuka cadar siang. Meminjam kekuatan dewa hujan untuk menjumpaimu dalam kenyataan. Tak kusangka; seketika langit kunyalakan, semesta kita langsung berciuman. Aku membuka pintu dengan kunci bergambar matahari dan ternyata pemilik pintu itu benar, hatimu. Kau menyambutku dengan hal yang tak terduga; cinta.
Belahan Jiwa Sejak Zaman Azali
Kita berkenalan sebentar, namun seolah kau dan aku sudah kenal lama. Kau dengan cepat memahamiku, aku memahamimu; kau bisa membacaku, aku mampu menyelami kedalaman samudera jiwamu. Aristoteles berkata: Sahabat adalah satu jiwa yang tinggal dalam dua tubuh.
Konon, belahan jiwa sudah ditentukan sejak zaman azali. Belahan jiwa akan memiliki kemiripan ciri. Setelah berpisah, terpencar, di bumi kita saling mencari. Saat bertemu, kita akan langsung mengenalinya, bahwa akulah kampung halamanmu, separuhmu, rumahmu.
Belahan jiwa sejati, kelak, akan bersatu mengabadi di kampung halaman asli.
Alasan Mencintai
Kemarin aku masih mencoba mengartikan cinta, masih dengan kata yang sedikit berlebihan misalnya kata-kata seperti cintanya awan kepada langit, samudera kepada daratan, atau hidup kepada mati.
Namun sekarang, aku telah tahu bahwa cinta lebih hebat dari semua itu.
Aku berjumpa dengannya dan aku bisa mengenalnya. Lalu aku bersama dengannya kemudian saling mengerti. Aku bergenggaman tangan dengannya dan merasakan sebuah kekuatan.
Dan jika dulu tidak ada alasan untuk mencintainya, kini alasan itu ada. Alasanya hanya satu, yaitu: tak ada alasan. Terjadi begitu saja, mengalir seperti air, dan indah sampai aku tak bisa memahaminya. Luar biasa. []