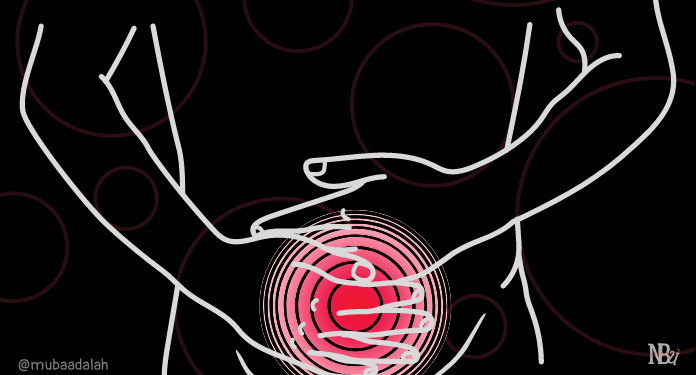Mubadalah.id – Ajaran agama Islam tidak berpihak pada perempuan. Demikianlah klaim Barat atas realita umum yang para perempuan Muslim alami dalam berbagai budaya masyarakat Muslim di berbagai belahan dunia. Klaim tersebut dapat disanggah oleh para intelektual Muslim kontemporer dengan pendekatan-pendekatan yang menjadi keahliannya, seperti tafsir, sosio-historis, tasawuf, dan lain sebagainya.
Realita diskriminasi yang terpotret oleh Barat tidak sepenuhnya keliru, karena masih terdapat dominasi budaya patriarki dalam pemaknaan teks syariat. Selain itu juga implementasinya dalam konteks kehidupan sebagian besar masyarakat Muslim.
Perempuan dalam budaya patriarki ditempatkan sebagai subjek kedua, objek seksual, pelengkap kehidupan laki-laki, dan tidak memiliki ruang kemerdekaan sebagaimana laki-laki. Perspektif adil gender yang tidak para pembaca literatur keagamaan (mubaligh, dai, penceramah) miliki, juga menjadi salah satu faktor pelanggengan budaya patriarki tersebut.
Sebut saja bagaimana isu poligami, domestikasi perempuan, sunat perempuan, atau intervensi pakaian masih merajalela dengan segala dampak buruknya bagi perempuan, baik secara fisik dan juga mental.
Selama isu-isu tersebut masih kita baca secara tekstual, rigid, dan tidak kita sesuaikan dengan kondisi kontemporer, maka teks-teks keagamaan akan selamanya menjadi donatur utama diskriminasi terhadap perempuan. Alih-alih menjadi alternatif jawaban kehidupan yang rahmatan.
Isu Haid
Di antara banyak isu yang dapat kita kaji dalam ruang agama dan perempuan, isu kodrat haid adalah isu yang menarik perhatian penulis. Perlu penulis tegaskan, diksi haid dalam literatur Fikih memiliki persamaan dan perbedaan dengan diksi menstruasi dalam ilmu kesehatan.
Penulis pernah mengulik hal ini dengan melakukan kajian teks juga observasi terhadap pengalaman perempuan yang berbeda-beda. Di mana secara garis besar menyimpulkan, bahwa haid dalam kajian Fikih adalah: pertama, darah yang keluar dari rahim perempuan yang sehat pada usia tertentu. Pada pemaknaan ini, haid sama dengan menstruasi.
Kedua, darah yang keluar dari rahim perempuan yang hamil dan telah mencapai kurun waktu 24 jam, sehari semalam. Pemaknaan kedua ini adalah pemaknaan yang menunjukkan alangkah humanisnya ajaran agama Islam yang mempertimbangkan pengalaman biologis perempuan.
Secara ilmu kesehatan, sangat mustahil perempuan hamil mengalami menstruasi, karena sel telurnya telah terbuahi. Akan tetapi, perempuan hamil sangat mungkin mengalami haid, yakni ketika ia mengalami pendarahan yang memenuhi jangka waktu 24 jam.
Oleh karena itu, haid dalam kondisi ini adalah takhfifan, keringanan bagi para perempuan hamil untuk boleh tidak melaksanakan ibadah-ibadah yang sifatnya fardlu ‘ain. Seperti salat dan puasa; takhfifan ini diformulasikan -Imam Syafii khususnya- sebagai respon atas kondisi kehamilan tiap perempuan yang tidak sama. Tujuannya agar kewajiban-kewajiban syariat tidak membebani mereka dalam kondisi darurat yang dapat mempertaruhkan nyawa di dalamnya.
Bukan Tanda Lemah Akal
Lagi-lagi, haid bukanlah tanda lemah (akal dan agama) dan kotornya (fisik) perempuan. Melainkan bentuk dari cinta Tuhan dalam proses keberlangsungan kehidupan generasi selanjutnya.
Seandainya kita membaca teks ini secara tekstual, maka teks agama akan selalu terbentur dengan sains yang berkemajuan, seolah-olah teks agama sangat terbelakang. Menjadi hal berbeda saat kita membacanya dengan memberikan sentuhan perspektif gender berdasarkan pengalaman perempuan.
Maka kita akan menemukan banyak pengetahuan yang mencerahkan, tentang bagaimana kerasnya ikhtiar para mujtahid akbar tersebut dalam merumuskan fatwa. Yakni tentang komprehensifnya literatur terdahulu yang dapat kita jadikan yurisprudensi sepanjang zaman. Lalu tentang tantangan bagi penyampai teks keagamaan di era sekarang untuk memiliki kemampuan mengalih-bahasakan literatur keislaman, agar memiliki spirit adil gender, juga sinergitas terhadap ilmu pengetahuan.
Jika telah demikian, agama bukanlah dogma yang isinya tentang tahayul dan ancaman menakutkan, melainkan tentang pengetahuan kehidupan yang selalu kita cari-cari dan kita butuhkan, bukan ditinggalkan.
Hal serupa untuk kasus yang berkelindan dengan kodrat haid, yakni tentang isu kuku dan rambut perempuan. Apakah wajib untuk kita kumpulkan dan kita sucikan bebarengan saat mandi besar, atau tidak wajib untuk melakukan itu.
Tentu penulis tidak akan menuliskan panjang lebar terkait teks-teks khilafiyah/perbedaan pendapat di dalamnya, karena membutuhkan halaman yang tidak sedikit untuk membincangnya. Dalam tulisan ini penulis hanya ingin menuliskan refleksi di balik perbedaan pendapat atas isu tersebut, sebagai kontribusi dalam wacana keislaman. Bahwasanya sejatinya ajaran agama itu bukan untuk menyulitkan, melainkan untuk menyelamatkan.
Perbedaan Pendapat Ulama
Pada infografis Instagram BincangMuslimah.com tertuliskan, perbedaan-perbedaan pendapat para ulama dalam mengakomodir isu rambut perempuan saat haid. Yaitu meliputi kuku, gigi, kulit, dan anggota tubuh lainnya. Perbedaan tersebut hadir sebagai respon atas syarat sah bersuci dari hadas besar. Yakni terbasuhnya semua anggota tubuh yang dapat terjangkau air oleh aliran air dalam prosesnya.
Hal ini berdampak pada beberapa praktik yang menakutkan, menyulitkan dan memberatkan perempuan. Tidak sedikit perempuan yang mengumpulkan rambut dan kukunya selama haid untuk kemudian kita sucikan bersama ketika mandi besar.
Bahkan tidak sedikit pula perempuan yang menghindari membersihkan rambut kepalanya untuk meminimalisir rontoknya rambut yang mereka miliki. Dan, tidak sedikit penyakit baru bermunculan karena kurangnya ikhtiar membersihkan diri saat hadas besar.
Tidak masalah jika hadas besar hanya berlangsung 1 atau 2 hari. Lantas bagaimana jika hadas tersebut mencapai 60 hari, seperti pada perempuan yang sedang nifas? Di sinilah agama tergambarkan menjadi aspek yang mendiskriminasi perempuan, dalam perkara yang nampak sederhana sekalipun.
Realitanya, pendapat atas isu itu sangat beragam, ada yang menganjurkan untuk kita sucikan bebarengan. Ada juga yang tidak mensyaratkan hal tersebut. Tiada yang salah dari kedua pendapat tersebut, sehingga tidak perlu kita perdebatkan. Perbedaan pendapat harus tetap eksis untuk mengakomodir pengalaman, perasaan dan pengetahuan yang sangat beragam. Demikianlah maksud dari Islam yang rahmatan.
Makna di Balik Perbedaan
Esensi di balik perbedaan pendapat ini adalah, setiap manusia, dianjurkan untuk lebih perduli kepada kebersihan dan kesehatan diri, ini tidak saja berlaku pada perempuan. Melainkan juga pada laki-laki; karena di antara 6 sebab yang menjadikan wajibnya mandi besar bagi manusia. Empat sebab yang ada juga dimiliki oleh laki-laki, sehingga yang menjadi syarat sahnya juga menjadi perkara yang harus kita perhatikan bebarengan.
Rambut (di mana pun letak tumbuhnya) dan kuku merupakan anggota tubuh yang memiliki perawatan sedikit ekstra daripada anggota tubuh lainnya. Minimal seminggu sekali kuku harus kita potong atau kita bersihkan, karena berkaitan dengan kualitas pencernaan dalam proses makan.
Demikian juga pada rambut, entah itu kita keramas, dilembutkan, diwarnai, ia adalah anggota tubuh yang selalu mendapatkan perawatan ekstra, bagi laki-laki dan perempuan.
Keduanya menjadi salah satu indikator untuk menilai kualitas kesehatan manusia. Saat manusia ingin membersihkan diri dari hadas kecil dan besar, agama menganjurkan untuk memperhatikan anggota tubuh ini pula.
Apakah kuku kita mengalami perubahan warna dan bentuk, apakah rambut kita mengalami kerontokan yang banyak atau sedikit, keperdulian kita terhadap hal ini merupakan ikhtiar untuk menjaga kebersihan dan kesehatan diri.
Arah dari ajaran agama yang demikian adalah membimbing kita untuk memiliki waktu lebih untuk me time dengan diri kita yang lain. Yakni kuku, rambut, kulit, dan lainnya. Lagi-lagi, bukan untuk memberatkan, melainkan cara lain dari perwujudan kasih sayang Tuhan.
Gradasi Hukum Syariat
Demikian pula terhadap khilafiyah pada treatment yang dilakukan pada anggota tubuh tersebut, seperti memakai kutek, menyambung rambut, sulam alis, sulam bibir, menyemir rambut, mengikir dan belungsung gigi.
Sejatinya para ulama terdahulu sudah mengakomodir kebutuhan perempuan yang berbeda-beda kebutuhan dan kondisinya. Tugas para mubaligh adalah menyampaikan gradasi hukum yang ada. Bukan berusaha memonopoli bunyi hukum berdasarkan pengalamannya saja.
Penulis pernah bertanya pada drg. Dea Safira tentang veneer gigi, sebagai seorang dokter gigi beliau menjawab, bahwasanya treatment tersebut membutuhkan biaya dan usaha lebih banyak dalam perawatannya. Selain itu juga pasien tidak akan mampu menggigit makanan yang keras selayaknya gigi biasa tanpa di-veneer.
Untuk yang membutuhkan perawatan ini, menjadi wajib untuk menunjang penampilan. Tentunya dengan biaya yang kita siapkan. Namun untuk yang tidak terlalu memerlukan, dan tidak memiliki biaya dalam perawatan, lebih baik jangan.
Di sinilah fungsi dari gradasi hukum syariat yang para ulama tawarkan. Tidak saja mempertimbangkan aspek kesehatan, tetapi juga ekonomi, sosial, psikis, yang semuanya untuk kebaikan dan kemudahan perempuan, dengan berbagai kondisi dan kebutuhannya. Sehingga, apapun yang menjadi pilihan perempuan terhadap tubuhnya, seyoyanya tidak lagi menjadi perdebatan. Karena agama Tuhan hadir untuk menyayangi semua pilihan dalam hidupnya.
Biarlah perempuan yang berijtihad untuk dirinya sendiri, karena ia yang paling tahu apa yang paling ia butuhkan. Demi kebaikan hidupnya, yang bersifat lahiriyah (fisik) dan batiniyah (mental). Dengan demikian, semua perempuan akan bahagia, karena sejatinya, Tuhan menyayangi mereka. []