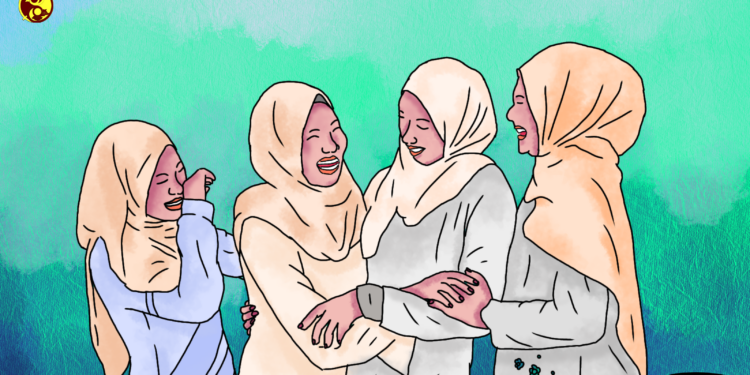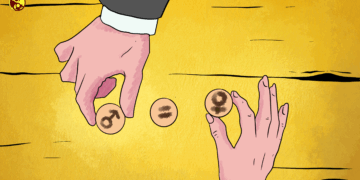Mubadalah.id – Beberapa tahun yang lalu, ketika saya masih duduk di bangku kelas XI Aliyah, tepatnya pada pelajaran taqrib, seorang guru berkopiah hitam menjelaskan bab pernikahan. Tepat pada suatu matan yang Imam Abu Syuja’ Rahimahullah ungkapkan, menyatakan bahwa:
وَالنسَاءُ عَلى ضَرْبَيْن: ثَيباتٍ، وَأبكَارٍ: فَالبكْر يَجُوز لِلأبِ وَالْجد إخبَارُهَا عَلى النَكَاحِ، والثيب لَا يجوزُ تَزُوِيجُهَا إلا بَعْدَ بُلوغِهَا وإذْنِهَ
“Dan wanita itu ada dua macam; janda dan gadis. Diperbolehkan bagi ayah dan kakek ‘memaksakan’ pernikahan seorang gadis. Adapun janda, tidak boleh menikahkannya kecuali setelah ia baligh dan diminta izinnya.”
Guru tersebut melanjutkan “jadi, seorang ayah (kandung) dan kakek dari perempuan yang masih gadis boleh memaksakan mereka untuk menikah”. Lebih lagi ustadz tersebut menjelaskan dengan bahasa sehari-hari dengan menyebutkan “Jadi ndak usah kaget kalau mbak-mbak (kalian) pulang ke rumah tiba-tiba ada seorang laki-laki yang akan dipilih menjadi menantu oleh ayah mbak-mbak sekalian.”
Di dalam kelas tersebut tidak ada tanda-tanda ketidaksetujuan dari teman-teman, yang terdengar hanyalah suara lirih akan candaan tentang perjodohan. Aku menggerutu dalam hati karena tidak bisa merespon ungkapan ustadz tersebut.
Aku menunggu seseorang mengeluarkan pendapat lain. Tapi tidak ada. Mengapa mereka tidak memikirkan posisi mereka sebagai perempuan? Mengapa mereka tidak memikirkan bahwa perannya ada pada posisi yang sangat pelik.
Jika keadaan tersebut benar terjadi, mereka akan berhadapan dengan dua pilihan, menolak dengan artian menentang orang tua. Namun bagaimana bisa kita menerima yang tidak kita kehendaki menjadi pasangan kita? Bukankah tindakan demikian termasuk ke dalam kawin paksa? Padahal kenyataannya, kawin paksa bukanlah tujuan dari adanya hak ijbar.
Wali Mujbir dan Penyelewengan Hak Ijbar
Hak ijbar adalah suatu kekuasaan wali dari perempuan yang belum pernah menikah. Maka dalam hal ini wali tersebut kita namakan wali mujbir. Dalam fiqih munakahat, kedudukan wali menjadi sangat penting dalam sebuah akad pernikahan.
Wali dalam kekuasaan untuk menikahkan seseorang terbagi menjadi dua, yaitu wali mujbir dan wali ghairu mujbir. Wali mujbir yaitu orang yang mempunyai hak untuk menikahkan perempuan yang ada dalam kekuasaannya tanpa izin dan ridla dari perempuan tersebut.
Sedangkan Wali ghairu mujbir adalah orang yang mempunyai hak untuk menikahkan prempuan yang ada dalam kekuasaannya tetapi harus dengan izin dan ridla dari perempuan tersebut.
Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa wali mujbir adalah ayah dan kakek. Sedangan madzhab Maliki dan Hanbali wali mujbir adalah ayah saja. Dalam pandangan madzhab Hanafi, semua wali dianggap mujbir sehingga tidak ada wali yang ghairu mujbir karena wali memiliki kuasa atas orang lain. Baik itu ridla atau tidak.
Dalam perjodohan antar orang tua, memanglah kedua belah pihak orang tua berdalih dengan alasan klasik yang mengatas namakan kebaikan. “Setiap orang tua menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya.”
Namun faktanya, yang terjadi pada orang tua banyak yang menggunakan kuasa hak ijbar dengan tujuan yang melenceng dari maksud baik ijbar. Seperti perjodohan yang dilakukan keluarga.
Di mana mereka ingin melanggengkan kekuasaan atau banyak juga yang sering terjadi adalah karena faktor ekonomi sang wali mujbir. Bisa jadi ayah atau kakeknya memaksakan anak gadisnya di bawah umur agar dinikahi laki-laki yang menurutnya baik sesuai dengan ekspektasinya. Lah iya kalau jodoh, kalau tidak bagaimana?
Praktik Perjodohan Paksa
Fenomena tersebut marak terjadi di berbagai wilayah pedesaan atau masyarakat yang masih tradisionalis. Anak gadis yang masih di bawah umur itu mereka nikahkan untuk mengurangi beban keluarga dan melimpahkannya pada suami. Alih-alih meneruskan pendidikannya, anak perempuan mengorbankan jiwa raganya untuk menjadi istri di saat masih memiliki hak untuk belajar dan bermain sebagaimana anak yang lain.
Perjodohan seperti permasalahan antik yang menjadi problematika menarik bagi para produser untuk menggarap serial film percintaan. Namun sayangnya, film yang masyarakat sukai itu tidak menjadikan penonton memandang buruk perjodohan.
Memang, perjodohan bukanlah hal yang salah dan banyak yang menikah karena orangtua jodohkan dan berhasil. Namun, jagan sampai menutup mata bahwa banyak yang masih bermasalah dalam praktik perjodohan paksa di Indonesia.
Perempuan seringkali menjadi korban utama dalam perjodohan. Karena praktik perjodohan bisa menjadi awal dari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Perjodohan menampilkan angan-angan yang orangtua inginkan. Di mana orangtua enggan memikirkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi. Tak jarang mereka memperdulikan kondisi kesiapan anak perempuan mereka. Ketidaksiapan seorang perempuan untuk menikah dan memiliki keturunan sangat memojokkan perempuan.
Lalu, Benarkah Seorang Perempuan Tidak Berhak Memilih Pasangan?
Setiap orang tidak patut untuk kita tindas haknya, begitu juga di dalam institusi keluarga. Di dalam aspek perjodohan, orang tua mempertimbangkan berbagai aspek sebagai penilaian dalam perjodohan. Dalam masyarakat jawa kita sering mendengar istilah bibit, bebet dan bobot atau juga karena alasan kekerabatan.
Namun sebenarnya, ada yang tidak kalah penting dari itu semua yang akan menjadi tolak ukur berhasilnya misi pernikahan, yaitu kerelaan (ridla). Kerelaan pada diri seorang perempuan yang kita jodohkan.
Sebagaimana penjelasan Buya Husein, bahwa ridla menjadi hal yang sangat mendasar bagi akad perkawinan. Dan kerelaan seorang perempuan untuk laki-laki nikahi tertandai dengan kebalighan keberakalan atau kedewasaannya. Seorang perempuan yang sudah baligh dan berakal memiliki sikap yang terbuka.
Stigma yang selama ini beredar di masyarakat kita adalah perempuan hanya menunggu untuk terpilih, bukan memilih. Perempuan berhak memilih kepada siapa ia menjatuhkan pilihannya, perempuan berhak untuk memiih kapan ia akan menikah, perempuan berhak memilih.
Perkara memilih pasangan, Nabi juga memiliki kebiasaan untuk musyawarah dengan putri-putrinya. Pada saat itu, kebiasaan para putri nabi akan diam jika memilih untuk menerima. Sedangkan untuk menolak, para putri nabi langsung menutup tirainya secara rapat-rapat. Sikap nabi yang demikian hendaknya bisa kita contoh untuk mendengarkan hak anak-anak perempuannya, kendati beliau memiliki hak ijbar atas perkara tersebut.
Perempuan Berhak Menentukan Jodoh Sendiri
Di lain masalah, Aisyah RA. pernah bercerita mengenai seorang perempuan bernama Khansa binti Khidam Al-Anshoriyah. Dia adalah salah seorang sahabat nabi yang juga meriwayatkan beberapa hadits. Ia menceritakan bahwa ayahnya menikahkan dia secara paksa.
Pada waktu itu terdapat dua orang yang melamarnya, yaitu Abu Lubabah bin Abdul Mundzir dan yang kedua adalah seorang laki-laki dari Bani Amr bin Auf yang tidak lain adalah kerabatnya sendiri. Namun, Khansa lebih tertarik kepada Abu Lubabah, sedangkan ayahnya lebih tertari kepada laki-laki yang masih menjadi kerabatya.
Oleh sebab itu, Khansa berniat menemui Rasulullah. Setelah itu ia berkata “Wahai Rasululah, sesungguhnya ayah saya telah memaksa saya untuk menikah dengan seseorang yang beliau inginkan, sedangkan saya tidak mau.”
Kemudian Rasulullah menjawab, “Tidak ada menikah dengannya, menikahlah dengan yang kamu cintai.” Kemudian ia menikah dengan Abu Lubabah.
Dalam riwayat yang lain, pada kitab al-Mabsuth dikisahkan bahwa Khansa berucap “Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayah saya telah menikahkan saya dengan keponakannya.”
Kemudian Rasulullah menjawab “Laksanakan saja apa yang ayahmu inginkan”. Lalu Khansa menimpali “Tetapi saya tidak suka dengan hal tersebut”. “Kalau begitu, pergilah dan nikahlah kamu dengan orang yang kamu cintai”.
Selain itu, dalam kitab Nisa’ haula Rasul, Khansa juga menumpahkan rasa kecewa dengan berkata seperti ini “Wahai ayahku, engkau telah menyiksaku dan membebankanku dengan sesuatu yang berat. Engkau telah mengantarkanku pada orang yang memandang rendah diriku.”
“Wahai ayahku, jika bukan karena kegundahan yang menghimpitku, aku tidak akan memohon kepadamu untuk lepas darinya. Namun sungguh aneh, seorang perempuan cantik yang gaunnya ditarik untuk disandingkan dengan orangtua dari suatu kaum. Pria tua tersebut mengatakan padanya bahwa ia memiliki tali kerabat. Maka celakalah bagi anak paman baik dari ayah maupun ibu.”
Dari cerita tersebut, kita dapat memahami bahwa yang paling berhak untuk menentukan pasangan adalah perempuan itu sendiri. Bukan berada di tangan ayah maupun orang lain. Memilih menerima perjodohan mungkin sebagai bakti kepada orang tua.
Namun, dalam urusan perjodohan dengan menimbang kebahagiaan dan ketentraman hidup seorang anak. Jika bakti harus mengorbankan kelanjutan hidup anak, Rasulullah lebih menyarankan untuk menikahkan dengan seseorang yang membuat hati tentram. Karena pernikahan yang baik harus kita bangun di atas kasih sayang dan ridla antara laki-laki dan perempuan. []