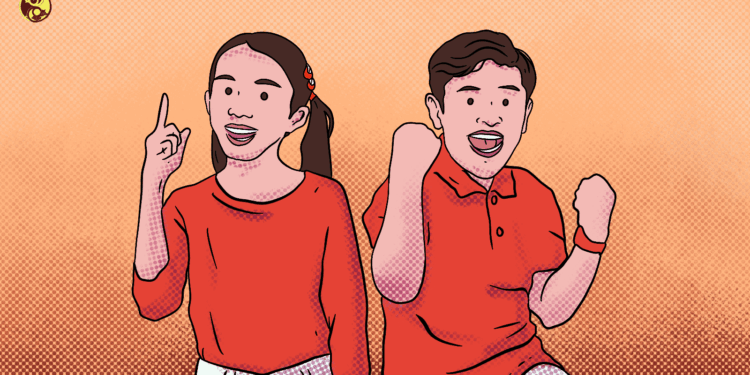Mubadalah.id – Pertanyaan tentang hak anak di luar perkawinan untuk memperoleh nafkah kerap menjadi perdebatan di masyarakat, baik dari sudut pandang hukum maupun moral. Anak lahir di luar ikatan pernikahan resmi seringkali mengalami stigma sosial yang berat. Namun, dari perspektif hukum dan agama, keberadaannya tetap terakui dan hak-haknya harus terjamin, termasuk hak atas nafkah.
Dalam hukum Islam, anak di luar perkawinan, meskipun lahir dari hubungan yang tidak sah secara syariat, tidak kehilangan hak-hak dasar sebagai manusia. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 11 Tahun 2012 secara tegas menegaskan bahwa anak hasil zina memiliki hak untuk menerima nafkah dari ayah biologisnya.
Fatwa ini menekankan bahwa kewajiban nafkah adalah hak anak. Bukan kebaikan yang bersifat sukarela dari orang tua. Anak di luar nikah tetap merupakan subjek hukum yang harus terlindungi, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup, pendidikan, dan kesejahteraan psikososialnya.
Dalam konteks hukum positif Indonesia, kewajiban nafkah anak diatur melalui KUHPerdata Pasal 299–301, yang membedakan antara anak sah dan anak di luar kawin. Nnamun tetap memberikan hak kepada anak luar nikah untuk mendapatkan nafkah dari ayah biologisnya.
Selain itu, UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan bahwa setiap anak berhak hidup, tumbuh, dan berkembang secara layak. Termasuk memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar dari orang tua, tanpa diskriminasi atas status kelahiran. Dengan kata lain, hukum nasional menegaskan bahwa hak anak di luar nikah bukan sekadar hak moral, tetapi hak legal yang dapat kita tegakkan melalui pengadilan.
Menilik Peran Pengadilan Agama
Sementara itu, peran pengadilan agama menjadi penting dalam penegakan hak ini. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan kewenangan kepada pengadilan agama untuk menetapkan kewajiban nafkah anak luar nikah.
Hakim dapat menggunakan instrumen taʿzīr, yakni hukuman atau sanksi yang bentuk dan besarnya diserahkan kepada hakim, untuk memastikan ayah biologis memenuhi kewajibannya. Pendekatan taʿzīr ini bersifat fleksibel dan adaptif. Sehingga memungkinkan hakim menyesuaikan kewajiban nafkah dengan kemampuan ekonomi ayah dan kebutuhan anak.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa hak anak di luar perkawinan sering kali sulit kita tegakkan. Banyak ayah biologis enggan memenuhi kewajiban nafkah, dan stigma sosial membuat anak dan ibunya enggan menempuh jalur hukum.
Di sinilah peran asas kepentingan terbaik anak (best interest of the child) menjadi relevan. Prinsip ini menuntut setiap keputusan hukum terkait anak untuk menempatkan kepentingan dan kesejahteraannya sebagai prioritas utama. Dalam konteks nafkah, hakim tidak hanya melihat formalitas hukum atau status pernikahan, tetapi harus memastikan anak mendapatkan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak.
Kajian akademik juga menegaskan bahwa anak di luar nikah berhak atas nafkah, pendidikan, dan perlindungan psikologis. Menurut Prof. Euis Nurlaelawati, seorang ahli hukum keluarga Islam, penerapan taʿzīr dalam kewajiban nafkah anak luar nikah harus berlandaskan prinsip keadilan substantif, bukan sekadar formalitas hukum.
Hal ini sejalan dengan pendapat Sulhani Hermawan, yang menekankan pentingnya ijtihad qadhāʾī untuk menjamin hak anak secara nyata dan tidak diskriminatif.
Anak di Luar Perkawinan Berhak Mendapatkan Nafkah
Tidak hanya dari perspektif hukum Islam, teori hukum positif dan hak asasi manusia juga memperkuat argumen bahwa anak luar nikah berhak mendapat nafkah. Konvensi Hak Anak (UNCRC, 1989) menegaskan hak setiap anak untuk hidup, berkembang, dan terlindungi tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, status kelahiran tidak boleh menjadi alasan bagi orang tua atau masyarakat untuk menolak pemenuhan hak anak.
Di sisi lain, implementasi putusan hakim terkait nafkah anak luar nikah masih menghadapi kendala. Dalam banyak kasus, ayah biologis tidak menepati kewajibannya. Sementara mekanisme hukum untuk menegakkan putusan sering lambat atau rumit.
Di sinilah taʿzīr, kita kombinasikan dengan pengawasan hukum, menjadi penting sebagai instrumen memaksa pemenuhan kewajiban. Tanpa sanksi yang efektif, hak anak berisiko tidak terpenuhi, meskipun secara normatif terakui.
Dengan demikian, jawaban atas pertanyaan “Benarkah anak di luar perkawinan berhak mendapat nafkah?” adalah ya! Secara hukum dan agama anak di luar nikah tetap berhak atas nafkah dari ayah biologisnya.
Hak ini terjamin oleh hukum Islam melalui fatwa MUI. Kemudian hukum positif Indonesia melalui KUHPerdata dan UU Perlindungan Anak, serta oleh prinsip hak asasi anak secara internasional. Tantangannya bukan pada keberadaan hak, tetapi pada implementasi dan penegakan hukum yang memastikan hak tersebut terpenuhi secara nyata.
Kesimpulannya, anak di luar perkawinan bukanlah pihak yang kehilangan hak fundamentalnya. Kewajiban nafkah bagi ayah biologis bukanlah sekadar anjuran moral, melainkan kewajiban hukum yang sah dan dapat ditegakkan di pengadilan.
Prinsip kepentingan terbaik anak harus menjadi pedoman setiap keputusan hukum, sehingga anak luar nikah memperoleh kehidupan yang layak, aman, dan terjamin kesejahteraannya. Dalam kerangka ini, istilah taʿzīr bukan hanya bentuk hukuman, tetapi juga instrumen keadilan yang menjembatani fleksibilitas hukum dengan perlindungan hak anak. []