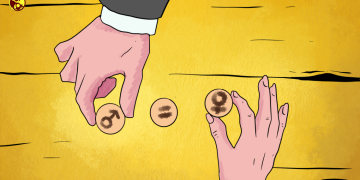Mubadalah.id – Dalam medis, istihadhah merupakan problem kesehatan yang cukup serius. Pendarahan yang terus-menerus dapat mengakibatkan kelelahan, menurunkan daya tahan tubuh, bahkan bisa mengancam nyawa.
Bagi sebagian perempuan, terutama yang mendekati masa menopause atau yang menggunakan alat kontrasepsi tertentu. Kondisi istihadhah ini juga menimbulkan bahaya.
Maka, pertanyaan yang muncul adalah di mana letak pertimbangan kemanusiaan dalam hukum untuk perempuan dengan kondisi lemah semacam ini?
Kita harus berani mengakui bahwa sebagian produk fiqh memang mereka susun tanpa mempertimbangkan secara memadai pengalaman dan kondisi perempuan. Karena selama ini fiqh lahir dalam konteks sosial-budaya yang sangat patriarkal, di mana ruang dan suara perempuan terbatas.
Padahal, hukum Islam seharusnya berpihak pada kemaslahatan dan kemudahan (taisir), bukan menambah kesulitan (ta’sir). Sebagaimana prinsip ushul fiqh menyebutkan, “Al-masyaqqah tajlibu at-taysir” — kesulitan harus mendatangkan kemudahan.
Namun, Nyai Hj. Badriyah Fayumi dalam tulisannya di Kupipedia.id, menegaskan bahwa tidak semua produk fiqh bersifat kaku dan menekan perempuan.
Dalam khazanah fiqh Islam terdapat pula pandangan yang lebih akomodatif dan realistis terhadap kondisi perempuan. Misalnya, dalam hal batas minimal waktu haid. Imam Syafi’i berpendapat bahwa haid minimal berlangsung satu hari. Sementara Imam Abu Hanifah menetapkannya tiga hari.
Pandangan ini memiliki konsekuensi hukum yang cukup berat. Terutama bagi perempuan yang mengalami haid sangat singkat atau tidak teratur.
Namun ada pendapat lain dari Imam Malik yang lebih membumi: bahwa tidak ada batas minimal haid. Artinya, setiap darah yang keluar pada masa haid —meskipun hanya sesaat— tetap dianggap haid.
Pandangan ini terasa lebih manusiawi, karena mengakui kenyataan biologis perempuan yang beragam. Pendekatan seperti inilah yang semestinya dijadikan dasar dalam memahami dan mengembangkan fiqh yang empati kepada perempuan. []